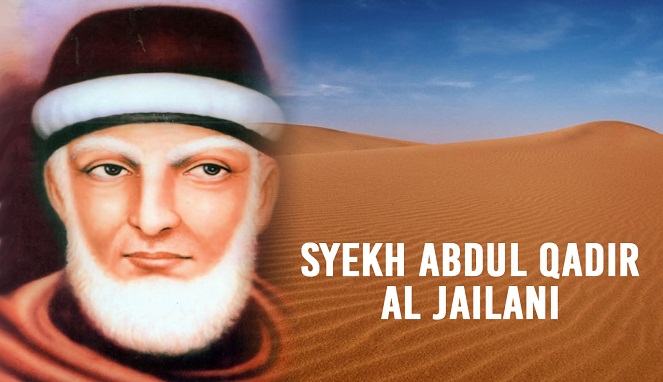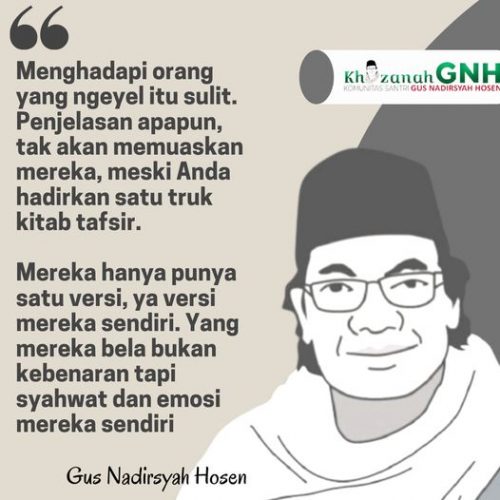Makna Fana Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani (2).
Oleh Edi AH Iyubenu, wakil ketua LTN PWNU DIY
Dalam kitab Adab al-Suluk wa at-Tawashshul Ila Manazil al-Muluk, Syekh Abdul Qadir al-Jailani qaddasahuLlah mengatakan: “Bagaimana kau mau berbangga dan pamer kebaikanmu serta menuntut balasan terhadapnya, sedangkan semua kebaikan berasal dari kekuatan yang dianugerahkan Allah Swt, melalui taufik, pertolongan, daya, kehendak, dan karuniaNya? Begitu pula dengan penyingkiran bermaksiat terhadapNya.
Semua laku ini hanya berkat perlindungan dan pertolonganNya. Mana bentuk kesyukuranmu terhadap hal tersebut, juga pengakuanmu atas segala nikmat yang telah dianugerahkanNya kepadamu? Apa-apaan dengan semua kelancangan dan kebodohan ini!”
Kita telah bersama-sama mengkaji ihwal tauhid di berbagai seri tulisan ini sebelumnya, yang berinti pada “pemfanaan diri” (pendhaifan, peniadaan diri) dari segala kemampuan untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan dan kekuatan untuk menghindarkan keburukan-keburukan.
La haula wala quwwata illa biLlah, tiada daya dan kekuatan kecuali atas izin Allah Swt.
Siapa yang hatinya semakin dihunjami keyakinan demikian, menjiwai segenap keinginan, kehendak, dan perbuatannya, itu tanda semakin fananya ia di hadapan Allah Swt; semakin leburnya ia memanunggal dalam hadirat Allah Swt.
Dan sebaliknya.
“Dan janganlah kau sembah selain Allah Swt, (menyembah) Tuhan yang lain. Tidak ada Tuhan selain Allah Swt. Segala sesuatu pasti binasa kecuali WajahNya. BagiNya lah segala ketentuan dan kepadaNya lah kau akan dikembalikan” (QS. Al-Qashash 88).
Karenanya, mari bercermat diri selalu betapa ini merupakan hakikat tauhid kepadaNya dan pula ajang tantangan bagi pikiran, godaan bagi hawa nafsu, dan tipu daya bagi iblis (setan) yang sangat rawan membajak kemurnian tauhid kita.
Apa yang belakangan ini rajin benar dikampanyekan sebagai “memurnikan tauhid”, kiranya relevan kita maknai dalam arah tersebut. Bukan selainnya, seperti penisbatan pada diri yang kuat, mampu, dan berdaya. Berhati-hatilah, jangan sampai terkecoh, pekik “memurnikan tauhid” ternyata hakikatnya bukanlah ikrar pemfanaan diri itu sendiri.
Memang, alamiah, di fase awal-awal, kita besar kemungkinan bergerak dalam aras diri tersebut. Namun, jangan terus-terusan. Jangan berlarut-larut. Apalagi selamanya. Bisa terjungkal pada “peyembahan hawa nafsu” malah.
Negasi atau fana adalah semata-mata merayakan Kemahaan Alah Swt. Diri yang boleh jadi kini sedang digetolkan oleh (bayang-bayang) rajinnya diri, pintarnya diri, sabarnya diri, hingga tercerahkannya iman dan takwa diri, marilah itu pahami dengan saksama sebagai tahap sementara saja.
Berikutnya, mestilah kita menanjak ke derajat yang lebih tinggi, kafah, yakni kefanaan tersebut.
Apa yang saya maksudkan “mestilah” tersebut, yang kesannya masih saja menisbatkan kepada diri, bukan Allah Swt, ialah semata intensitas tinggi diri untuk bermohon segala pertolongan, hidayah, taufik, dan karuniaNya untuk senantiasa membingkai diri kita. Jika diri terus berlatih membiasakan berada dalam “relasi tertolong” demikian, seperti dirajinkanNya beribadah, diarahkanNya berdoa, digerakkanNya dekat kepada perintahNya dan dijauhkanNya dari laranganNya, dan sejenisnya, maka julangan kedirian itu akan meluruh pelan demi pelan.
Luruhnya diri ini bukan berarti tiadanya diri dalam arti sebenar-benarnya. Kita yang awam begini bukanlah berada di derajat ahli Hadratul Quds demikian.
Diri ini tetap ada, aktif berikahtiar, hanya biasa tersegerakan bertawajjuh kepadaNya. Menghadap lagi kepadaNya.
Boleh jadi, misal, mulai dari shalat Subuh berjamaah di masjid tadi, lalu lanjut shalat Dhuha, lalu ngaji, dzikiran, terus ke shalat Dhuhur berjamaah lagi, diri ini alpa bahwa semua itu adalah semata berkat karuniaNya dan pertolonganNya. Kealpaan yang sudah berlalu, biarkanlah berlalu.
Diri yang telah alpa tadi akan bersegera kembali ke hadiratNya sebagai Sang Penolong dan Sang Pengarunia jika telah biasa punya intensitas tinggi dalam melatih tawajjuh itu.
Dalam ungkapan lain beliau qaddasahuLlah menguraikan tentang “ketergelinciran-ketergelinciran” diri dalam bentuk lalai, alpa, lupa kepadaNya sebagai Pencipta amal-amal kebaikan kita. Tatkala terjadi hal demikian, bersegeranya diri kembali kepada hadiratNya merupakan momen yang diberikanNya bagi “terbentuknya kembali” diri ini dalam BentukNya.
Artinya, kita yang tadinya lalai padaNya, tergelincir, hancur, kini kembali terbentuk oleh BentukNya. Dan tentulah ini mesti dirujukkan kepada pertolonganNya.
Maka, ungkapan “mohon hidayah, taufik, inayah, dan karuniaNya” memang mestilah benar-benar tiada ujungnya, hingga akhir ajal. Sebab nyatanya kita kerap betul tergelincir, hancur, lalu terbentuk lagi; lalu kembali tergelincir, hancur, dan terbentuk lagi, lagi, dan lagi.
Seluruh rangkaian “tergelincir, hancur, terbentuk lagi” ini jika terus dibingkai oleh keyakinan atas Kehendak, Keputusan, dan PerbuatanNya, secara tulus dan haq dalam batin, bukan lagi jadi soal. Tiada sesal yang perlu terus dirayakan hingga membuat diri terbekap nestapa. Sebab itu semua telah diyakini sebagai KeputusanNya….
Jadi, logisnya, tatkala kita melakoni kebaikan-kebaikan sesuai perintahNya, tiada hasrat pada diri untuk mendapatkan begini dan begitu lagi, apalagi hal-hal yang berbau material duniawi. Begitupun bila diri terhindarkan dari kemaksiatan-kemaksiatan, tiada lagi perayaan atas keistimewaan diri.
Diri ini dalam kefanaannya yang telah menghunjam di hati adalah ketiadaan belaka. Segala denyar keinginan, kehendak, dan perbuatan diri telah dinisbatkan kepadaNya semata melalui mekanisme tawajjuh itu. Dalam bahasa umum, munajat. Semua apa yang diri rasakan, inginkan, angankan, kehendaki, cita-citakan, dan lakukan, senantiasa telah dimunajatkan ke hadiratNya.
Ini sekaligus memperlihatkan bahwa jalan menjadi fana kiranya tidak semata dengan jalan ‘uzlah, khulul, jauh dari kegiatan duniawi. Sepanjang tawajjuh senantiasa telah membingkai diri dalam seluruh aktivitasnya, lahir dan batin, boleh jadi itulah jalan fana seseorang.
“Perbaikilah lakumu. Syukur dan pujian hanya bagi yang menolong. Nisbatkanlah segala sesuatu kepadaNya dalam segala kondisi….” tutur beliau qaddasahuLlah.
“Nisbatkanlah segala sesuatu kepadaNya dalam segala kondisi”, yakni tersambungnya diri dalam kesenantiasaan iman, takwa, dan khusyuk kepada KemahaanNya Swt.
Wallahu a’lam bish shawab.
Jogja, 20 Agustus 2019
_______________
Semoga artikel Makna Fana Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani (2) ini memberikan manfaat dan barokah untuk kita semua, aminn..
simak artikel terkait Makna Fana Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani (2) di sini
simak video terkait di sini