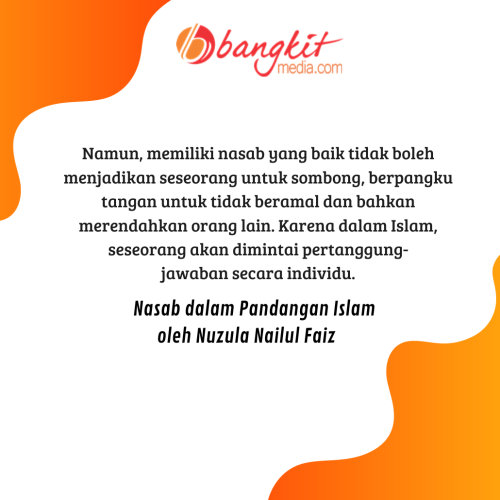“Tulisan ini adalah resume Ngaji Kitab Ihya’ Ulumuddin dari Kiai Ulil Abshar Abdala selama bulan Ramadhan. Ngaji ini diresume oleh Alimah Fauzan.”
Nafs merupakan istilah ketiga dari 4 (empat) istilah yang sering dipakai dalam kajian tasawuf, yaitu tentang Qalb (hati), ruh, nafs atau jiwa, dan ‘aql. Lalu, apa itu nafs atau jiwa dan bagaimana Imam Al-Ghazali membahas tentang jiwa?
Istilah ketiga adalah an-Nafs atau jiwa. “Nafs” merupakan satu lafadz namun memiliki banyak makna. Namun pada pembahasan Imam Ghazali dalam kitab Ihya ‘Ulumuddin, Nafs memiliki 2 (dua) pengertian berikut ini:
Pertama, Ketika kita menyebut kata “nafs”, dia merujuk pada kemampuan mental pada diri manusia, kemampuan untuk tidak menyukai sesuatu (marah) dan menyukai sesuatu. Kalau dia tidak marah, maka dia menyukai sesuatu yang berlebihan. Penggunaan ini adalah yang umum, bahwa nafsu adalah kecenderungan yang ada pada diri manusia terhadap dua hal, kecenderungan untuk marah dan menyukai sesuatu. Karena ahli tasawuf pada umumnya ketika menggunakan kata nafsu merujuk pada pengertian yang mencakup sifat-sifat yang tercela pada diri manusia atau sesuatu yang negatif, maka ada pernyataan “kita harus memerangi nafsu” (La Budda min mujahadatin nafs).
Kenapa nafsu harus diperangi? Karena nafsu berkaitan dengan sifat negatif. Ada juga hadits yang menunjukkan pengertian yang sama, seperti ”musuhmu yang paling keras adalah nafsumu yang ada di antara 2 sisi badanmu”. Jadi, nafsu pada makna pertama ini memiliki pengertian sebagai “sifat yang tercela pada manusia”. Sifat pokok seperti “marah atau membenci sesuatu” dan “menyukai sesuatu”. Misalnya ketika kita menyukai salah satu atau beberapa aktivitas seperti wisata kuliner misalnya, maka itu juga termasuk nafsu, selain itu ketika kita marah atas kritikan yang ditujukan kepada kita melalui sosmed dll, maka itu juga disebut nafsu.
Kedua, Makna kedua dari nafsu adalah sesuatu yang lembut, dimana ini adalah sifat manusia yang sesungguhnya. Nafsu dalam hal ini adalah sesuatu yang sifatnya lembut pada diri manusia, karena itu merupakan jati diri manusia, jiwa, hakikat manusia. Nafsu dalam pemaknaan ini juga merupakan esensinya (dzatnya), tetapi nafsu ini juga bukan yang tunggal maknanya. Artina, nafsu memang memiliki sifat-sifat yang berbeda. Nafsu dalam pengertian kedua ini, dia tenang dalam kendali, serta terhindar dari sebuah kebimbangan (kegalauan). Karena kemampuan kita mengendalikan syahwat, maka nafsu semacam ini sesungguhnya adalah jiwa yang tenang (annafsul mut’mainnah), jiwa yang berhasil dikendalikan oleh manusia. Ini disebut dengan nafsu mutma’innah.
Jika kita merujuk pada istilah psikologi yang dipakai oleh Freud, makna nafsu kedua ini adalah super ego, keadaan dimana kita bisa mengendalikan insting hewaniyah (kasar) yang ada dalam diri kita. Karena kita bisa mengendalikannya, maka itu menjadi super ego. Jadi yang disebut nafs al mutma’innah itu super ego. Terkait nafsu ego ini juga dijelaskan dalam al-Qur’an yang menjelaskan mengenai contoh nafsu yang seperti itu: “Ya ayyuhan nafsul muthmainnah…” yang memiliki arti lengkapnya “wahai nafsu yang tenang, kembalilah kepadaku dalam keadaan yang penuh dengan ketenangan.”
Jadi, bisa disimpulkan bahwa makna nafsu yang pertama adalah “sebuah kekuatan untuk tidak menyukai sesuatu (marah) atau menyukai sesuatu”. Makna nafsu yang pertama ini bukan nafsu yang bisa kembali kepada Allah Swt, karena hanya nafsu yang tenang yang bisa kembali kepada Allah Swt. Kenapa tidak bisa kembali? Karena nafsu ini dijauhkan dari Tuhan (Allah Swt), nafsu ini nafsu yang masuk dalam bloknya setan, atau kekuatan jahat dalam diri manusia. Lalu bagaimana jika ketenangan nafsu (makna nafsu yang kedua) tidak sempurna? Meskipun tidak sempurna, tetapi nafsu tadi dapat melawan nafsu yang pertama (atas kemampuannya untuk marah atau menyukai sesuatu). Sementara nafsu pertama belum sampai berhasil mengendalikan diri, namun makna nafsu yang kedua berusaha mengendalikan dirinya. Maka, nafsu ini disebut sebagai nafsu yang suka melakukan autokritik, nafsu lawammah, nafsu yang selalu mengingatkan kita.
Kyai Ulil juga menjelaskan:
Ada nafsu yang disebut selalu mendorong atau memerintah manusia untuk melakukan kejahatan. Memerintahkan dengan sepenuh tenaga, dengan penekanan yang intensif. Nafsu ini disebut nafsu Amaroh. La uqsimu binnafsil lawamah, nafsu yang selalu memerintahkan pada tindak kejahatan. Kadang-kadang nafsu ini mendorong tindakan jahat, nafsu dalam pengertian tendensi-tendensi marah dalam diri kita. Itu adalah nafsu dalam pengertian yang pertama. Maka, madhmummatun, kekuatan amarah dan syahwat itu dicela, yaitu disebut nafsu yang paling rendah sekali, “Nafsu purba”, ketika manusia masih pada tahap belum mengalami civilization (berperadaban). Nafsu dalam pengertian ini selalu melakukan autokritik, atau nafsu yang mencapai ketenangan, nafsul insani adalah jiwa manusia, Soul of the human being. Jadi kalaupun dia tidak sepenuhnya nafsul mutmainnah, maka minimal bisa melakukan autokritik, yang dapat mengetahui pengetahuan-pengetahuan yang lain. Itulah sejatinya manusia, sementaran nafsu yang pertama adalah menunjukkan esensi kebinatangan.