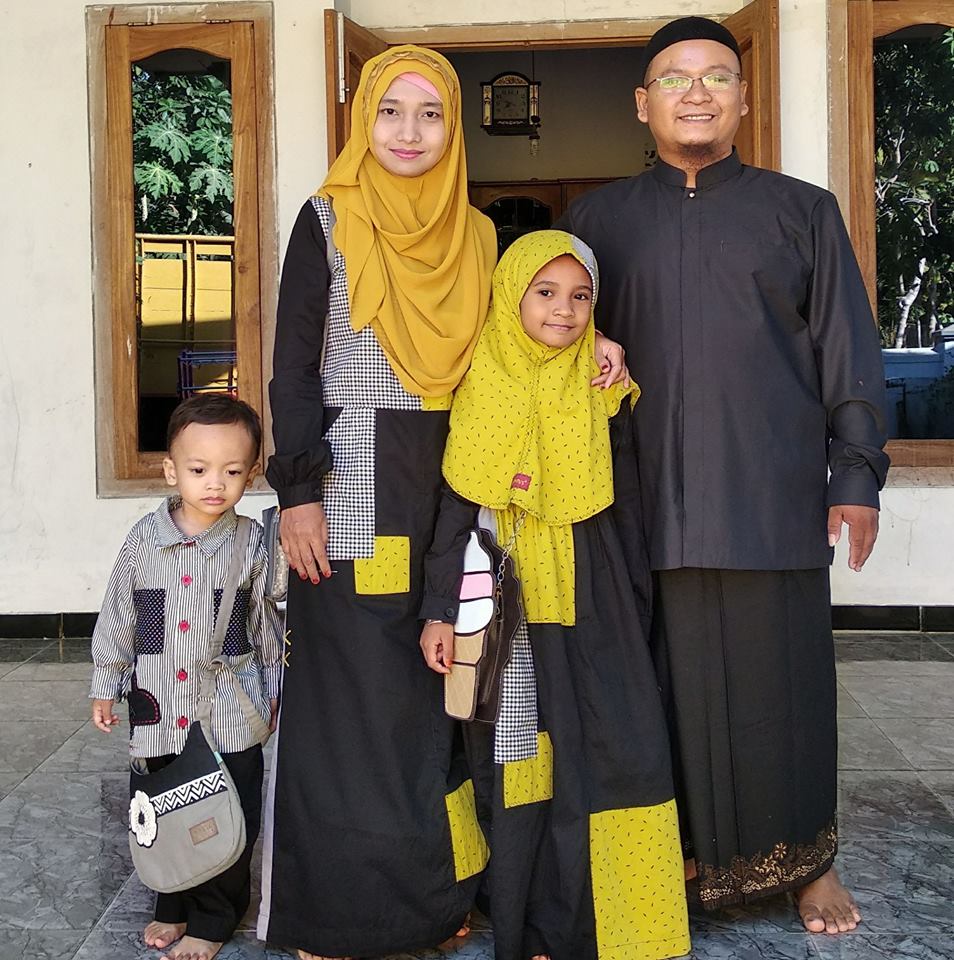Suatu ketika, Ummul Mukminin Aisyah r.a., ditanya oleh seorang sahabat mengenai aktivitas Rasulullah SAW di dalam rumah. Beliau tersenyum lantas menjawab, “Melakukan apa yang tidak kalian lakukan. Yaitu menjahit pakaian, menambal sandal, dan memasak di saat para pembantu beliau kecapekan.”
Beberapa pekerjaan domestik di atas seringkali dipahami “hanya” pekerjaan istri. Padahal, dalam kehidupan berumahtangga, Rasulullah SAW telah memberikan teladan apabila segala sesuatu di dalam rumahtangga bisa dikerjakan bersama-sama. Saling bekerjasama dan saling membantu. Tidak ada egoisme seorang suami yang enggan mengerjakan pekerjaan rumah. Tidak ada pula rasa gengsi beliau dalam melakukan pekerjaan yang dianggap remeh.
Dalam kisah lain, Rasulullah juga melibatkan para istrinya dalam beberapa keputusan penting. Beliau menempatkan istrinya sebagai lawan diskusi yang cerdas. Menghormati para istri sebagai seorang manusia yang memiliki akal pikiran yang bisa memberikan solusi jitu dalam sebuah permasalahan yang pelik. Misalnya, ketika Rasulullah berangkat ke Makkah pada tahun keenam hijriyah untuk melaksanakan umrah.
Pada saat itu, karena terikat dengan Perjanjian Hudaibiyah, maka kaum muslimin tidak boleh melaksanakan umrah di sana dan mereka baru diperbolehkan ke Makkah pada tahun berikutnya. Karena itu, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat agar menyembelih hewan kurban dan mencukur rambut. Namun, kaum muslimin tidak bergerak dari tempat duduknya, dan tidak menghalalkan ihram mereka. Mereka sangat sedih karena belum menyempurnakan umrahnya.
Di sinilah, Ummul Mukminin Ummu Salamah r.a. memberikan saran kepada Rasulullah SAW, sang suami tercinta. “Wahai Rasulullah, keluarlah dan jangan berbicara dengan salah satu dari mereka sebelum engkau menyembelih untamu dan memanggil tukang cukur untuk mencukur rambutmu.” Rasulullah keluar lantas melaksanakan apa yang dikatakan oleh Ummu Salamah r.a., sehingga kaum muslimin mengikutinya.
Fakta ini menunjukkan apabila manusia parpurna tersebut sangat menghormati istrinya dan bersedia bermusyawarah dengannya. Dengan perilaku ini, beliau juga menandaskan melalui sabdanya dalam sebuah kesempatan, “Sebaik-baik kaum muslimin adalah yang orang yang paling baik memperlakukan istrinya.”
Sebagai kepala rumahtangga, Rasulullah menangani setiap persoalan yang timbul dalam rumahtangga beliau dengan sikap yang tenang, pandangan yang jernih, dan tindakan yang bijak. Tidak pernah ada catatan beliau marah kepada istrinya dengan amarah yang meluap-luap. Tidak ada kisahnya beliau melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tidak pula beliau mencacimaki istri beliau, maupun melontarkan kata-kata yang bernada menghina dan merendahkan martabat istrinya. Kalaupun beliau marah, hanya sebentar, kemudian menjadi lembut.
Karena itu, dalam berumahtangga, perlu adanya kesepakatan ruang “kerja” sekaligus komitmen untuk berbagi bersama-sama. Tugas memandikan anak, misalnya, bukan lagi dianggap sebagai tugas istri. Melainkan suami juga memiliki tanggungjawab untuk melakukannya sebagai wujud cinta kepada buah hatinya. Demikian pula pekerjaan lainnya. Jika istri memasak, maka suami bisa membantunya membersihkan dapur maupun mencuci piring. Sebuah hal remeh yang membuat istri bertambah sayang kepada suaminya.
Perilaku berumahtangga yang demikian ini merupakan implementasi konsep berumahtangga ala Rasulullah. Beliau melakukan prinsip Mubaadalah. Istilah berasal dari bahasa Arab. Artinya, tukar menukar, baik besifat fisik seperti perdagangan maupun non-fisik seperti perilaku tenggang rasa. Ia juga berarti timbal-balik, resiprositi, atau kesalingan.
Dalam rumahtangga, mubaadalah berarti relasi suami istri yang saling melengkapi, saling mencintai, saling setia, saling bekerjasama demi kehidupan yang lebih baik, adil, damai dan sejahtera. Tepatnya untuk kebaikan di dunia dan akhirat.
Dalam perspektif sedehana, menurut Ustadz Faqihuddin Abdul Qadir (mubaadalah.com), jika senyum, keramahan, melayani dan segala tindakan yang menyenangkan adalah baik dilakukan istri kepada suami, maka ia juga baik dilakukan suami kepada istri. Begitupun, jika berkata buruk, tidak pandai bersyukur, memghina, mengumpat, memukul, dan tindakan kekerasan lain tidak baik dilakukan suami kepada istri, maka demikian pula sebaliknya.
Pola interaksi semacam ini dilakukan karena pada hakikatnya rumahtangga dibangun berdua. Suami dan istri. Karena itu keduanya memiliki kontribusi yang sama. Tidak saling menuntut. Sebab, dalam istilah KH. A. Mustofa Bisri, “Adakalanya suami menuntut istri agar sempurna. Demikian pula sebaliknya. Padahal keduanya diciptakan untuk saling menyempurnakan.”
Oleh karena itu, betapa indahnya jika rumahtangga dibangun berlandaskan cinta dan kebersamaan. Interaksi berlandaskan prinsip mubaadalah. Sebab, Kebahagiaan rumahtangga tidak terletak pada harta melimpah dan fasilitas hidup yang serba mewah. Jamak kita jumpai pasangan yang sama-sama kaya namun kehidupan berumahtangganya tidak bahagia. Sebaliknya, banyak pula pasangan yang sejak menikah hingga meninggal hidup dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan, namun bisa menjalani pernikahan dengan bahagia. Dugaan saya, pasangan jenis kedua ini melaksanakan prinsip mubaadalah, sebuah prinsip yang menekankan apabila kebahagiaan terletak pada kesediaan setiap individu, bukan hanya saling mencintai, melainkan juga saling mengalah dan berkorban.
Wallahu A’lam Bisshawab
Tulisan ini dimuat di Majalah AULEEA, Edisi November 2018
(Penulis: Gus Rijal Mumazziq Z, Rektor Institute Agama Islam Al-Falah As-Sunniyyah (INAIFAS) Kencong Jember)