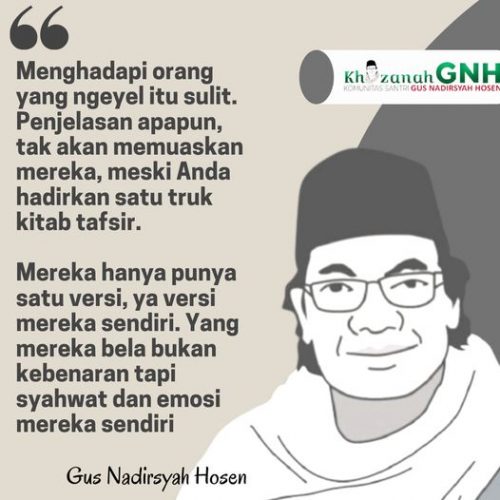“Yang Mutlak” Tak Mungkin Digusur “Yang Relatif”.
Oleh Edi AH Iyubenu, Wakil Ketua LTN PWNU DIY
“Saya telah bersedekah sebegitu rajinnya, tetapi rezeki saya tak kunjung berlimpah ruah pula, bagaimana ya kok janji Allah Swt dalam begitu banyak ayat al-Qur’an tak terwujud begini?”
“Saya telah rajin beribadah, mendoakan, mendidik, dan memberi makan halal kepada anak, tetapi mengapa anak saya kok jadi senakal sebandel itu, ya, seolah janji Allah Swt dalam al-Qur’an tak terwujud?”
“Saya merasa telah begitu salehnya, semua perintahNya saya laksanakan, semua laranganNya saya hindarkan, bahkan yang sunnah pun saya amalkan, tetapi mengapa ya kok pasangan saya nampak tak sesaleh yang saya impikan?”
Pertanyaan-pertanyaan galau sejenis itu barangkali akan membuat Anda tersentak kaget bila saya respons dengan ungkapan nyegrak begini: “Siapa kamu kok hendak mengatur-ngatur Allah Swt? Dia adalah Tuhan Yang Maha Bebas, Maha SemauNya, Maha Suka-sukaNya; tiada kewajiban bagiNya untuk mesti sesuai dengan hajatmu, impianmu, bahkan ibadah-ibadahmu yang diyakini berfadhilah begini begitu atas dasar dalil-dalil apa pun….”
Ada sebuah hadis yang sangat populer yang “menegasi” semua peribadatan yang kita lakukan. Ya, semuanya.
Dari Jabir bin Abdullah, Rasul Saw bersabda, “Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari siksa neraka. Tidak juga denganku, kecuali dengan rahmat Allah Swt.” (HR. Muslim).
Lalu mari perhatikan surat al-Hadid ayat 28: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Swt dan berimanlah kepada RasulNya Saw, niscaya Allah Swt akan memberikan rahmatNya kepadamu dalam dua bagian, (yakni) menjadikan buatmu cahaya yang dengannya kamu bisa berjalan (di jalan Allah Swt) dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Swt Maha Pengampun dan Penyayang.”
Kedua dalil ini adalah “yang mutlak” dari sisi Allah Swt. Sekali lagi, “yang mutlak”, yakni proklamasi kemahakuasaan Allah Swt sebagai Tuhan yang Maha Segalanya, Maha Tak Terbatas. Pada derajat ini, relevan pelbagai ungkapan, misal dari Imam Ja’far al-Shadiq, “Janganlah hukum Allah kamu batas-batasi dan ukur-ukur dengan akalmu.” Allah Swt adalah semata Allah Swt yang Maha Berkehendak dan Berbuat apa saja, tanpa perlu terikat pada apa saja. Mana pantas Tuhan Yang Maha Kuasa kok terikat-ikat?
Beriman kepada Allah Swt tentu saja secara hakiki semata menisbatkan kewajiban kepada kita untuk memposisikan diri bagai budakNya. Allah Swt adalah Tuan kita. Ketika Sang Tuan memerintahkan salat, ya salat. Memerintahkan sedekah, ya sedekah. Memerintahkan berbuat baik kepada orang tua, ya lakukan. Mau terpahami secara nalar logika atau tidak, mau selaras dengan pengertian teks dalilnya atau tidak, ya sudah saja. Dan sebagainya.
simak artikel terkait “Yang Mutlak” Tak Mungkin Digusur “Yang Relatif” di sini
Soal Sang Tuan menjanjikan begini begitu kepada hamba-hamba yang mematuhi perintah-perintahNya, dan apakah janji-janji itu dikabulNya dengan begitu saja saat ini, atau diwujudkanNya dengan kondisi tertentu yang berbeda, atau kelak saja di akhirat, itu semata kemutlakan wewenang Allah Swt. Bukan urusan kita lagi semestinya. Jika kita sibuk mengurusnya yang notabene bukan hak kita, rawan betul risikonya untuk membuat kita jatuh pada mempertanyakanNya, meragukanNya, dan itu sama sekali tak ideal buat rohani seorang hamba.
Apakah setelah banyak bersedekah, tapi oleh Alah Swt tak kunjung dilimpahkan rezeki kita sebagaimana janjiNya dalam al-Qur’an, misal dalam surat al-Baqarah ayat 261 hingga 269, kita hendak meragukan kemahakuasaanNya atau sekalian meninggalkan perintah sedekah tersebut dengan hati kecewa?
Kedua sikap tersebut jelas bermasalah secara iman tauhid. Bermasalah. Kita terlihat tidak benar-benar mengabdikan diri sebagai hambaNya di hadapan Tuannya. Kita begitu “memaksa” Sang Tuan untuk sesuai dengan hajat dan impian kita, via amal-amal kita. Bagaimana logisnya Tuhan yang kita sembah kok kita paksa-paksa pula untuk mesti sesuai dengan pengharapan-pengharapan kita?
Coba kita renungkan lagi ayat 28 al-Hadid itu. Terlihat jelas bahwa umpama pun kini kita sedang rajin ibadah, ahli sedekah, tanda kita secara lahiriah berjalan di jalanNya, itu semestinya selalu kita pandang semata sebagai sebuah bagian dari karuniaNya, bukan?
Umpama kita sedang hijrah, atau rajin istighfar entah karena merasa pernah melakukan dosa besar di masa lalu, lalu Allah Swt mengampuni dosa-dosa kita, bukankah itu sejatinya merupakan satu bagian lagi dari karuniaNya?
Bisa beribadah saja adalah karuniaNya, masak pantas lagi buat kita untuk menyandera Tuhan supaya memberikan begini dan begitu kepada amal-amal ibadah kita sesuai dengan fadhilah-fadhilah yang kita dengar dan yakini?
Tentu, secara sederhana, mengharapkan karuniaNya dalam rupa fadhilah-fadhilah amal kita sahih belaka. Menjadikannya sebagai spirit dan motivasi ya sahih saja. Toh ya memang benar-benar ada riwayat sahih perihal hal-hal tersebut.
Hanya, secara rohani, tauhid, keimanan, seyogianya kekabulan fadhilah-fadhilah amal itu harus selalu kita pandang dan yakini bukan berkat fadhilah amal-amal kita itu, melainkan semata karunia Allah Swt. Mesti begitu. Jangan dibalik.
Sehngga, bila amal-amal kita belum terwujudkan buahnya sesuai fadhilah-fadhilah yang kita pahami tersebut, kita takkan terjatuh pada meragukan kebenaran janji Allah Swt, apalagi kemahakuasaanNya. Pun umpama fadhilah-fadhilah amal itu terwujud, itu pun terpandang semata sebagai karuniaNya, bukan sebab kokoh dan sucinya amal-amal diri ini. Ingat selalu kuncinya: kita beribadah dan bermal saleh adalah sebuah bentuk dari karuniaNya.
Terlihat jelas kini mana “yang mutlak” sebagai wilayah kekuasaanNya dengan mana “yang relatif” sebagai medan kita.
Maka, tiada kepantasan sedikit pun bagi kita yang relatif, beserta seabrek amal saleh yang pula relatif, hendak menggusur otoritas Allah Swt yang mutlak. Allah Swt mari tetapkan dengan haq selalu sebagai Yang Mutlak; sedangkan seluruh amal ibadah kita, apa pun fadhilahnya, sedawam apa pun dilakoni, tempatkan selalu sebagai tiada lain karena kita menyembahNya. Seluruh amal ibadah kita tempatkan selalu semata karena kita mematuhi perintahNya, sebab kita adalah budakNya. Selesai, kan?
Atas pemahaman sejenis ini, insya Allah kita akan bisa lebih tenang, kalem, dan santai dalam beribadah di antara realitas apa pun yang ditakdirkanNya. Kita beribadah ya beribadah saja, kita mengamalkan sunnah-sunnah dengan fadhilah apa saja, ya amalkan saja. Ya karena semata kita menyembahNya, mengabdi kepadaNya, dan memohon hanya kepadaNya.
Kecenderungan umum psikis kita untuk mendamba keputusan Allah Swt berdasar fadhilah amal-amal kita cukuplah jadi “batu loncatan” saja. Yakni sebagai sebuah motivasi, penyemangat, pengharapan, dan permohonan kepadaNya. Seiring waktu, seyogianya semakin “dewasalah” kita dalam menghamba padaNya. Makin menep, kata orang Jawa. Makin legawa, makin tawakal, makin ikhlas.
Sudah pasti, sikap rohani demikian tak pernah sama lho dengan beribadah padaNya dengan enteng-entengan, sesuka-suka, atau seenak-enaknya. Kepada diri sendiri, ini tak tepat dijadikan dalih untuk bermalas-malasan dalam menyembah dan mengabdi kepadaNya. Allah Swt Maha Tahu isi hati kita, bukan?
________________
Semoga artikel “Yang Mutlak” Tak Mungkin Digusur “Yang Relatif” ini memberikan manfaat untuk kita semua, amiin..
simak artikel terkait “Yang Mutlak” Tak Mungkin Digusur “Yang Relatif” di sini
simak video terkait di sini