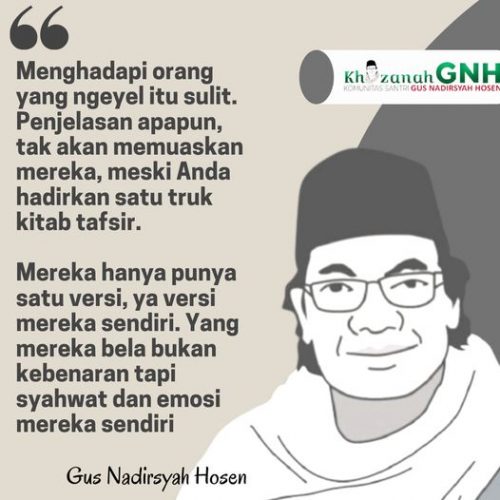Oleh Edi AH Iyubenu, Wakil Ketua PWNU DIY
Jamak kita menyamakan atau mensejajarkan pemahaman antara “iman” dan “takwa”. Apakah keduanya berbeda?
Iya, berbeda.
Saya kerap membuat ilustrasi bahwa beriman kepada Allah Swt ibarat akar bagi sebuah pohon. Yang pertama mesti ditancapkan dan dikokohkan adalah akar tersebut. Ikrar la ilaha ilalLah (dan Muhammad rasululLah) sebagai proklamasi iman kita, rukun pertama dalam memeluk Islam, adalah fana (negasi) terhadap segala sesembahan (ilah), apalagi hanya kita dalam segala wujudnya (lahir dan batin), dan kemudian yang tegak sebagai tsiqah (tsabit, tegak, mengakar, afirmasi) hanyalah Allah Swt. Maka, beriman pada hakikatnya adalah pemfanaan-segala-termasuk-diri-kecuali-afirmasi-Allah Swt. Segala sesuatu tiada selain Allah Swt –termasuk diri yang lumat dalam tauhid yang memfanakan kita.
Adapun takwa adalah cabang-cabang bagi pohon tersebut. Ia berlimpah ruah bentuknya. Yang menjadi batangnya adalah syariat. Dari batang syariat itulah menyebar segala cabang ketakwaan. Maka bentuk ketakwaan itu tak terbatas….
Patuh kepada orang tua adalah wujud cabang takwa. Santun kepada orang lain adalah wujud cabang takwa. Menundukkan pandangan dari lawan jenis non mahram adalah wujud cabang takwa. Meninggalkan ghibah adalah wujud cabang takwa. Memberi makan kucing adalah wujud cabang takwa. Memindahkan duri dari jalan adalah wujud cabang takwa. Dan sebagainya, dan seterusnya.
Iman adalah akar di dalam diri (hati, batin) dan takwa adalah wujud ekspresi kepatuhannya ke luar diri. Takwa, dengan kata lain, adalah kepatuhan kepada Allah Swt di bawah sinaran CahayaNya sehingga memproduksi kebaikan-kebaikan (ibadah dan sosial).
Dalam kitabnya, Sirrul Asrar Fima Yahtaj Ilaihi al-Abrar, untuk menjabarkan ihwal takwa, Syekh Abdul Qadir al-Jailani menukil surat An-Nisa’ ayat 131: “…Dan Kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang telah diberikan Kitab sebelum kamu dan kepada kamu yang hidup sesudahnya untuk bertakwa (patuh) kepada Allah Swt….”
Beliau mendorongkan derajat ruh kepatuhan kepada Allah Swt tersebut hendaknya melampaui zahrah al-hayah al-dunya, segala keindahan hidup di dunia. Sebab –beliau menukil sebuah hadis Rasul Saw—“Dunia adalah penjara bagi orang mukmin (dan lalu muttaqin)” dan “Dunia adalah surga bagi orang kafir.”
Jadi, di titik awal ini, kita bisa mendulang pemahaman bahwa yang dimaksudkan “takwa” adalah kepatuhan mutlak kepada Allah Swt mengenai segala ketentuanNya dalam bentuk perintahNya dan laranganNya, serta sekaligus kepada dunia yang rawan memenjara mukmin/muttaqin hingga lupa dan lalai dari kepatuhan mutlak kepada Allah Swt tersebut.
Inilah kepatuhan yang haq, takwa yang hakiki, sikap rohani yang hanifan.
Untuk menggapai derajat takwa kafah begini, Syekh Abdul Qadir al-Jailani memetakan takwa ke dalam beberapa tahap:
Pertama, takwa dari dosa syirik atau menyekutukan Allah Swt.
Kedua, takwa dari dosa-dosa besar.
Ketiga, takwa dari dosa-dosa kecil.
Keempat, takwa dari segala yang dipandang makruh.
Kelima, takwa dari segala yang dipandang mubah.
Keenam, takwa dari ketidakikhlasan.
Boleh jadi, kita memandang simpel terhadap bentuk takwa pertama, kedua, dan ketiga. Tapi, mari kita simak nasihat Syekh Abdul Qadir al-Jailani berikut.
Sekalipun Allah Swt Maha Pengampun (Ghafur) dan Maha Penyayang (Rahim), di mana kedua sifatNya ini mengasumsikan pemahaman bahwa terjatuh pada perbuatan dosa, besar atau kecil, selain syirik, bisa dihapuskan olehNya, perilaku tersebut tetaplah sebuah halangan rohani (hijab) yang buruk bagi perjalanan rohani salik. Maka ia mesti dihindarkan.
Dosa-dosa kecil yang sering kita andaikan luruh dengan sekadar berwudhu, misal, tidak lagi pantas dipahami sebagai “kecil dan mudah luruh”, tetapi dampak hijabnya kepada rohani kitalah yang menjadikannya masalah serius. Karenanya, tiada pilihan bagi seorang salik kecuali menghindarkannya selalu. Bahkan, penghindarannya secara lahiriah mestilah terus diiringi dengan permohonan taubat (istighfar) kepadaNya.
Jadi, beristighfar kepada Allah Swt tak perlu lagi menunggu kita menyadari telah melakukan sebuah dosa. Beristighfar adalah lelaku yang lekat dengan lahir dan batin seorang salik muttaqin yang haq. Kapan pun dan di mana pun.
Peta keempat ialah meninggalkan segala hal yang makruh. Atau, samar hukumnya. Atau, banyak ikhtilaf di kalangan ulama. Begitupun peta kelima, meninggalkan perkara mubah –yang jelas lebih tinggi maqamnya.
Bila kepada yang mubah (boleh) saja ditinggalkan –dalam artian mubah yang memicu tak sinambungnya diri dengan dzikrulLah dan mendekatkan pada laghwun (kesia-siaan) sebab seluruh denyut napas dan waktunya semata untuk tersambungkan kepada Allah Swt—apalagi kepada yang di bawah itu maqamnya. Tentu niscaya!
Betul, tak berarti memang bahwa ungkapan “buang-buang waktu dalam kesia-siaan” memaksudkan mutlak selalu menjauhi isi dunia ini. Tidak. Bagaimanapun, kita adalah manusia lahiriah (wadag) yang hidup di tengah pusaran dunia. Syekh Abdul Qadir al-Jailani juga mengatakan dalam bab rezeki Allah Swt bahwa rezeki itu mestilah rezeki yang benar-benar bersih tanpa bercampur noda-noda duniawi; rezeki itu (bisa) berupa kenikmatan yang berbaur dengan kesusahan maupun nikmat yang diiringi kemewahan, namun yang terpenting rezeki itu berasal dari segala yang diridhai Allah Swt. Insya Allah saya kaji lain waktu soal rezeki ini.
Ungkapan tersebut di atas menunjuk kepada segala gerakan atau kegiatan apa pun yang memutus kita dari dzikrulLah, ingat kepada Allah Swt, dan apalagi menyeret kita kepada hal-hal makruh, apalagi haram, apalagi syirik. Ini poinnya.
Maka, umpama kita berbisnis, itu sahih belaka di satu sisi sesuai dengan maqam hidup kita, akan tetapi hendaknya kegiatan bisnis tersebut senantiasa dibingkai dengan dzikrulLah. Bisa dari aspek niatnya untuk menafkahi keluarga, bisa dengan mengawalinya dengan berbismilLah, dan bisa dengan meyakini bahwa pendapatan bisnis kita nanti (untung atau rugi) adalah semata ketentuan Allah Swt yang mesti kita terima dengan tawakkal dan legawa. Ini contoh barang mubah yang migunani secara rohani.
Tapi jika kita berbisnis dengan membenarkan segala cara dan pula abai kepada syariat Allah Swt, apalagi ingatan kepada kemahaanNya dalam karunia-karunia keuntungan yang kita dapat, dan apalagi uangnya lalu kita pakai untuk bermaksiat, maka kemubahan berbisnis tadi menjadi terlarang secara rohani.
Peta kelima, dan inilah derajat takwa yang paling tinggi serta meliputi semua pilar takwa lainnya, adalah menjunjung selalu keikhlasan kepadaNya semata.
Ikhlas atas semua kehendakNya, ketetapanNya, dan keputusanNya yang diterjadikanNya ke dalam hidup kita, baik urusan duniawi maupun ukhrawi.
Jika kita berbisnis, hendaknya aktivitas bisnis tersebut dijalankan sesuai syariatNya, kemudian dijiwai oleh keyakinan kepada kemahakuasaanNya untuk memberikan kita keuntungan atau kerugian, dan finalnya keikhlasan selalu menjadi ruh kegiatan tersebut. Dengan ruh ikhlas, apa pun yang terjadi, kita akan tetap tenang dan tentram belaka –dan inilah yang oleh al-Qur’an diistilahkan “nafsul muthmainnah”. Allah Swt lah yang menenangkan dan menenteramkan hati kita. Allah Swt lah yang mengayomi dan melindungi kita dalam keadaan apa pun –dan itulah kondisi terbaik yang boleh jadi hanya Dia Swt yang mengetahuinya.
Ikhlas cum tawakkal dengan sendirinya adalah isi hati kita –yang selain-lainnya, seperti perasaan mampu dan kuat tak kita ijinkan bersemayam di dalamnya. Hanya Allah Swt yang Maha Kuat dan Maha Mampu.
Umpama kita sedang sedang bertahajjud, sedang mengaji al-Qur’an, sedang berpuasa, sedang berdzikir, sedang bersedekah, dll., maka kita mesti menghadapkan atau mengembalikan segera keadaan mampu dan kuat tersebut semata kepada Allah Swt yang mengaruniakannya kepada kita sehingga amaliah salehah itu menjadi terjadi.
Maka, hikmahnya, jangan jemawa!
Jangan pongah dan berbangga hati bila kita sedang beramal ibadah dan menolong orang lain atau sedang terhindar dari suatu kemungkaran dan kemaksiatan. Hati kita akan mampat, lalu kelam, dan kemudian mati bila kita membiarkan rasa jemawa itu menghijabi rohani kita. Mari ingat bahwa ternyata amaliah salehah pun bisa menjadi hijab batin kita.
Maka mari kita genggam selalu: hakikatnya adalah Allah Swt lah yang menjadikan kita mampu melakukan amal-amal kebaikan syariat dan sosial itu; Allah Swt lah yang menolong kita bisa menghindarkan suatu kemungkaran dan kemaksiatan, maka tiada alasan pembenar buat kita untuk tidak bertasyakur kepadanya dengan cara ikhlas dan tawakkal. Selalu ada alasan untuk bersyukur kepada karunia Allah Swt.
HasbunalLah wa ni’mal wakil.
Semoga kita semua senantiasa diberikan karunia oleh Allah Swt untuk bisa menatapi amal-amal ketakwaan dengan semata lilLahi Ta’ala. Amin.
Wallahu a’lam bish shawab.
Jogja, 25 Juli 2019