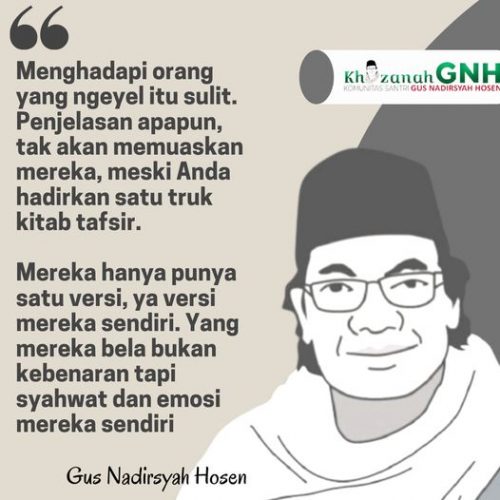Oleh Edi AH Iyubenu, wakil ketua LTN PWNU DIY.
Orang sufi, menurut Syekh Abdul Qadir al-Jailani dalam kitabnya, Jala’ al-Khatir fi al-Bathin wa al-Dzahir, adalah orang yang batin dan dzahirnya jernih dengan mengikuti al-Qur’an dan sunnah. Setiap kali kejernihannya bertambah, ia akan semakin keluar dari lautan wujudnya, serta meninggalkan keinginan, pilihan, dan hasratnya.
Baik, bagaimanapun, kita adalah makhluk wadag (lahiriah, badaniah). Kita butuh makan, minum, pakaian, hunian, keluarga, pekerjaan, dan penghasilan. Kita butuh materi-materi duniawi.
Bagaimana kita menempuhi “keluar dari lautan wujud, meninggalkan keinginan, pilihan, dan hasrat” di antara fakta lahiriah/badaniah ini?
Di titik krusial inilah rohani berperan hebat. Di luar dimensi wadag yang terbekap dalam kehidupan duniawi, rohani kita seyogianya menjadi Tuan bagi diri kita, wadag kita. Bukan sebaliknya, menjadi budaknya.Ini akar krusial yang mesti kita pecahkan dulu.
Rohani dan Wadag
Di dalam hati, batin, rohani kita, sejatinya di situlah Allah Swt bertahta.
Kita sering mendengar ungkapan populer sejenis ini: “Seburuk-buruknya perilaku kita, niscaya hati kita mengetahui bahwa keburukan-keburukan kita adalah kesalahan.”
Pengetahuan otomatis hati ini sering pula kita sebut sebagai “kata hati” atau “nurani”. Inilah yang dimaksud “Tahta Allah di dalam hati”. Dan Tahta ini telah disematkanNya sejak kita pertama kali ditiupkan ruh di alam rahim oleh Allah Swt: “alastu birabbikum, bukankah Aku ini adalah Tuhanmu?” dan ruh kita menjawab: “bala, iya betul”. Para akademisi, seperti Sayyed Hossein Nasr, menyebutnya “Perjanjian Primordial antara Tuhan dan Manusia”.
Masalahnya kini adalah bagaimana kita mendudukkan dimensi rohani dan wadag itu dalam diri kita? Apakah hati yang utama, ataukah sebaliknya, wadag cum hawa nafsu?
Bila wadag cum hawa nafsu yang kita junjung di Tahta, jelas kita akan menjadi budak dunia beserta seluruh candaan, godaan, dan tipu dayanya (la’ibun wa lahwun wa ghurur). Tahta Allah Swt kita abaikan begitu saja, kita singkirkan bahkan. Walhasil, kita lalu menjelma ahli maksiat, pengingkar ajaran-ajaranNya. NaudzubilLah min dzalik.
Bila hati yang kita jadikan Tuan, komitmen primordial dengan Allah Swt kita patuhi di TahtaNya, maka inilah peluang besar kita untuk menggapai nasihat Syekh Abdul Qadir al-Jailani tersebut.
Ini bukan berarti lalu kita mesti mencampakkan dunia wadag kita demi bertahtanya Allah Swt di dalam hati kita. Sebentar dulu, jangan terburu putus asa. Sungguh Allah Swt Maha Rahman dan Rahim.
Boleh jadi kita tetap berjibaku dengan pernak-pernik dunia, seperti berbisnis dan berumah tangga, tetapi yang paling esensial adalah kita tak menjadi budaknya. Hati kita tetap kekar untuk menggerakkan seluruh sumber daya pikiran dan tindakan kita untuk senantiasa selaras dengan syariatNya dan sekaligus terus melaju tinggi kepada kesadaran atas KemahakuasaanNya Swt semata.
Ada orang, misal, yang mengutarakan: “Saya memang bekerja keras untuk mencari uang sebagai ikhtiar lahiriah saya, tetapi secara rohani saya tak mencintai uang.”
Inilah maksud dari hati yang bertahta sebagai Tuan –sehingga apa pun yang kita kerjakan dan geluti secara duniawi, ia bukanlah tujuan dan hakikatnya. Tujuan dan hakikatnya tetaplah semata Allah Swt.
Maka boleh jadi tatkala kita bekerja keras dan menghasilkan uang yang banyak, kita semata memandang pekerjaan dan uang itu adalah tajalli (manifestasi) Allah Swt. Boleh jadi pula, kala lain, kita sedang dirundung kemerosotan atau bahkan kegagalan dalam suatu bisnis, kita tetap memandangnya tenang sebagai tajalli Allah Swt.
Begitulah contoh nyata dari nasihat: “Setiap kali kejernihannya bertambah, ia akan semakin keluar dari lautan wujudnya, serta meninggalkan keinginan, pilihan, dan hasratnya.”
Tajalli
Syekh Abdul Qadir al-Jailani mengatakan: “Jika hati benar/sehat (jernih), maka ia tidak perlu lagi pada orang-orang yang menyelisihi atau setuju dengannya; orang-orang yang memuji atau mencelanya; orang-orang yang memberi atau bakhil kepadanya; orang-orang yang mendekati atau menjauhinya; serta orang-orang yang menerima atau menolaknya. Ia dipenuhi oleh tauhid, tawakkal, yakin, taufik, ilmu, iman, dan dekat kepadaNya. Maka ia lalu memandang seluruh makhluk dengan pandangan kelemahan, kehinaan, dan kefakiran (karena Yang Maha Kuasa hanyalah Allah Swt). Bersamaan dengan itu, ia tidak sombong terhadap orang yang berada di bawahnya.”
Tajalli adalah manifestasi (pengejawantahan) Allah Swt sebagai Yang Maha Kuasa di jagat raya ini dalam segala bentuk. Ia bisa dihitung (muta’addidah) namun sekaligus tak terhitung (ghairu muta’addidah). Ia nyata dan sekaligus tak nyata. Kasat dan sekaligus maya. Rasional dan sekaligus suprarasional.
Purnama yang indah di suatu malam, misal, adalah tajalliNya. Laut dan gelombang-gelombangnya yang maha luas adalah tajalliNya. Kerikil di antara telapak kaki adalah tajalliNya. Kucing yang mengambil ikan di meja dapur pada suatu malam adalah tajalliNya. Karyawan adalah tajalliNya. Istri/suami, anak, kerabat, dan sahabat, serta tetangga adalah tajalliNya. Omset yang berlimpah di luar prediksi adalah tajalliNya. Tagihan yang tak terbayar adalah tajalliNya. Kejujuran adalah tajalliNya. Dusta adalah tajalliNya. Khusyuknya shalat adalah tajalliNya. Mabuk di sebuah karaokean adalah tajalliNya. Dan sebagainya, dan seterusnya.
Pinsipnya adalah semua makhluk dan segala peristiwa mustahil tak terpotret dalam KemahaanNya. Semuanya diketahuiNya dan hanya mungkin terjadi dengan ijinNya–soal suatu perbuatan diridhaiNya karena mengikuti syariatNya atau dibenciNya karena melanggar syariatNya adalah hal lain lagi.
Begitupun umpama kita terbangun di suatu malam buta untuk tahajjud hingga menangis di atas sajadah dalam dzikir-dzikir yang panjang dan dalam atau di suatu masa tergoda oleh kemolekan tubuh wangi lawan jenis yang bukan hak kita, itu pun adalah nyata tajalliNya, manifestasi KekuasaanNya.
Maka, mari kini renungkanlah, bila ada seseorang yang berkata buruk tentang kita, padahal kita telah menjulurkan tangan menolongnya beberapa hari lalu, dan kita mampu memandang dengan ‘ainul yaqin bahwa kejadian tersebut adalah tajalli kemahakuasaanNya kepada kita, entah dengan hikmah apa saja kemudian, maka gerangan apakah alasan logis kita untuk bermurka durja kepada pelakunya?
Tak ada! Sama sekali tak ada alasan logisnya.
Sungguh, ini yang lalu mendesak untuk senantiasa kita latih dan gerakkan, semuanya adalah semata manifetasiNya dalam segala bentuknya, apa saja, bagaimana saja. Dan, sumber segala bentuk manifestasi tersebut atau yang memanifestasi (mutajalli) adalah satu semata, yakni Allah Swt ‘Azza wa Jalla.
Jika kita bisa memahami dan memegang teguh prinsip rohani tajalliini, insya Allah yang berikutnya akan selalu menyala di hati kita di hadapan makhluk dan kejadian apa pun adalah semata bisikan batin: “Tiada daya dan upaya kecuali di Tangan Allah Yang Maha Agung lagi Maha Mulia.”
Inilah nasihat pokok Syekh Abdul Qadir al-Jailani dalam konteks ini. Semoga bermanfaat. Amin.
WalLahu a’lam bish shawab.
Jogja, 19 Juli 2019