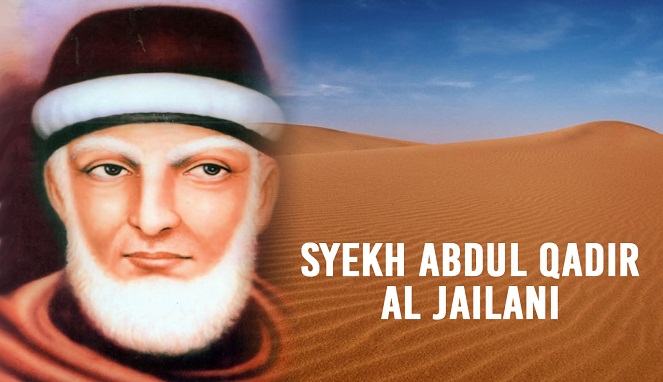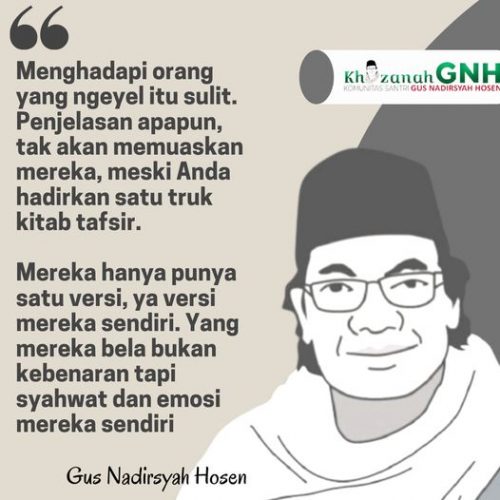Oleh Edi AH Iyubenu, wakil ketua LTN PWNU DIY
Kita tahu bahwa Allah Swt memperjalankan Rasulullah Saw, kemudian memi’rajkannya, yakni menaikkannya menembus langit-langit hingga Sidratul Muntaha. Beliau Saw didapuk menjadi imam salat bagi seluruh makhluk Allah Swt di langit, dari para malaikat hingga para nabi.
Selanjutnya, beliau Saw naik ke Sidratul Muntaha seorang diri dan memperoleh sapaan “As-salamu ‘alaika” langsung dari Allah Swt.
Jibril As yang menemaninya berkata, “Sampai batas di sini saja aku dapat mengantarmu, wahai Muhammad. Jika aku bergerak selangkah lagi, maka aku akan hangus.”
Syekh Abdul Qadir al-Jailani qaddasahuLlah dalam kitab Sirrul Asrar Fima Yahtaj ilaihi al-Abrar menakwilkan bahwa “batasan” yang tidak bisa dijangkau Jibril As adalah Dzat Allah Swt yang Qadim dan ‘Azali.
Dzat Qadim dan ‘Azali Allah Swt adalah Kemutlakan yang Haq. Tiada yang bisa memandang, menjangkau, dan apalagi menyentuhnya. Kemudian, Dzat Allah Swt tersebut memendarkan Cahaya dalam wujud pelbagai hal yang memungkinkan bagi kita, manusia, untuk mengenali dan merasakannya, seperti sifat-sifatNya dan af’al-Nya (perbuatan-perbuatan).
Beliau qaddasahuLlah mengatakan lebih lanjut: “Cahaya Allah Swt tidak pernah padam. Ia Qadim dan ‘Azali. Dzat dan (lalu) sifat Allah Swt senantiasa mewujud (mengejawantah). SifatNya adalah Cahaya yang terbit dari Dzat itu (yang Qadim dan ‘Azali; begitupun af’alNya, dan lainnya). Penzahiran DzatNya dan (dalam) penzahiran sifatNya bergantung kepada (hakikat) DzatNya, (maka) karena DzatNya Qadim, ia (penzahiran yang tidak qadim) tidak sama denganNya atau menyerupaiNya.”
Dalam studi Tasawuf, kita mengenal istilah tanzih dan taysbih. Keberbedaan dan sekaligus keserupaan. Ingat tegas-tegas di sini agar sealuclear bahwa tanzih dan tasybih itu pun sama sekali tak sama dengan Dzat Allah Swt yang Qadim dan ‘Azali. Tanzih dan tasybih kiranya menjadi “semata keperluan” keterbatasan nalar dan ilmu kita untuk mendapatkan pemahaman dan gambaran yang paling memungkinkan perihal Dzat Allah Swt.
Ketika dikatakan “yaduLlah” (tangan Allah Swt), ungkapan tersebut tidak tepat sama sekali untuk dipahami bahwa Allah Swt bertangan sebagaimana kita bertangan. Tidak. Ia adalah tanzih (pembedaan) antara Dzat Allah Swt dengan dzat manusia yang terlihat terang. Tetapi ia pun mengandung makna tasybih, penyerupaan, ketersamaran, bahwa Allah Swt “memiliki tangan”.
Ihwal bagaimana tangan Allah Swt yang hakiki, tiada yang tahu. Acap karenanya lalu dimaknai bahwa maksud “yaduLlah” adalah kekekuasaanNya. Sifat Ya Malikal Mulki, misal, bisa dijadikan representasi simbolis bagi makna tersebut.
Dengan kata lain, derajat tak tepermanai Allah Swt yang menjadi batas bagi jangkauan sosok Jibril As sekalipun mengisyaratkan Kemahaan Dzat Allah Swt yang paling agung, luhung, dan parpurna. Segala imaji kita tentangnya pasti tak pernah bisa menjangkaunya. Selalu ada di bawahnya.
Kiranya bijak sekali tuturan beliau qaddasahuLlah perihal “penzahiran Dzat Allah Swt” melalui ragam sifatNya yang kita kenal dari Asmaul Husna, misal, di satu sisi tak pantas disebut sebagai Dzat Allah Swt, tetapi (di sisi lain) jelas-jelas itu semua merupakan ejawantah bagi Hakika Dzatnya Swt.
Ketika dikatakan “Ya Rahman ya Rahim” (Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang) sebagai dua asma, sifat, tertinggiNya, maka seberapa pun kita mengkonsepsikan, bahkan merasakan di dalam hati yang paling sunyi sekalipun tentang dua sifatNya tersebut, bangunan pemahaman-pemahaman diri tersebut bukanlah Dzat Allah Swt sama sekali.
Kepengasihan dan Kepenyayangan Allah Swt niscaya melampaui jauh di atas yang kita pikirkan, juga rasakan. Jauh sekali derajatnya!
Maka dikatakan Dia lah Swt Sang Cahaya di atas Cahaya.
Memang boleh jadi dari desir-desir rasa yang bersumber dari akal dan desir-desir perasaan yang bersumber dari hati, yang paling personal, rahasia, dan dalam, lalu menjelmawashilah bagi kita untuk bisa merasakan hadirNya, kuasaNya, dan Welas AsihNya. Kemudian, tatkala ia berjumbuh menjadi iman yang makin mendalam, takwa yang makin khusyuk, dan ketawadhuan yang makin runduk, hingga akhlak karimah yang paling hasan, itulah indikasi masuknya CahayaNya.
Boleh jadi.
Allah Swt sungguh selalu Maha Kuasa untuk menciptakan jalan skenario apa pun, sampai yang paling tak terperikan, bagi masuknya CahayaNya ke rohani kita melalui ragam ejawantah apa saja. Bisa saja dari sifat-sifatNya dalam Asmaul Husna. Kita diajarkanNya untuk berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna, misal.
Bisa pula dari af’al-Nya berupa turunnya hujan, menyambarnya halilintar, gunung meletus, kematian orang tua, jodoh yang menyenangkan, sahabat yang tidak pernah perhitungan, harta yang berlimpah begitu deras mengalir maupun rezeki yang seret dan rumit, dan sebagainya.
Maka beliau qaddasahuLlah menasihatkan kemudian:
“Ibadah yang hakiki hanya dapat dilaksanakan apabila hijab yang menyelubungi hati tersingkap sehingga CahayaNya yang Qadim datang menyinarinya. Hanya dengan cara itulah hati akan bercahaya dengan Nurr-Nya. Hanya dengan cara itu jugalah ruh akan bisa melihat hakikat melalui ‘lubang’ (misykat) rohaniah.”
Kita bisa meraih pemahaman dari nasihat tersebut sekarang bahwa jalan-jalan yang dibukakanNya bagi pintu masuknya CahayaNya, dalam segala ejawantah DzatNya yang Qadim dan ‘Azali, amatlah tak terbatas.
Untuk itu, janganlah kita berani lancang membatas-batasi keluasan kemungkinan karunia hidayah dari Allah Swt.
Bila pun kini kita pribadi sedang rajin melakoni suatu amaliah salehah, tiadalah boleh pilihan dan minat personal tersebut menjadikan kita merasa lebih baik dan lebih lurus atau lebih benar dibanding orang-orang lain dalam jalan lelakunya masing-masing. Bahkan termasuk kepada mereka yang secara lahiriah kelihatan beluam sesuai dengan ajaran teks syariat yang umum kita pahami.
Itu pesan pertamanya.
Pesan keduanya ialah pintu bagi masuknya Cahaya yang dipancarkan Dzat Qadim dan ‘Azali Allah Swt ke dalam hati manusia hanya dimungkinkan bila hijab hati telah disingkapkan. Ada begitu banyak lapisan hijab yang mengeruhkan hati dengan selubung-selubungnya. Entah itu hijab kemaksiatan hingga hijab ilmu dan bahkan hijab amal saleh.
Mari berhati-hatilah selalu.
Karunia Allah Swt dan RahmatNya lah yang memungkinkan hijab-hijab itu disingkapkanNya. Tentu, menjadi kewajiban lahiriah bagi kita untuk memantik dan menekuninya, serta menekurinya, melalui kepatuhan syariat yang mantap di satu sisi serta penyelaman tafakur dan dzikir di sisi lain. Dan jangan lupakan senantiasa memohon hidayah dan bimbingaNya Swt.
Bisa saja dengan rahmatNya, dari jalan ikhtiar begitu lalu hijab-hijab hati setahap demi setahap disingkapkanNya, dienyahkanNya, sehingga hati kita menjadi lebih peka dan jernih lagi.
Orang ‘Arif, misal, yang telah semakin tersingkapkan hijab-hijab hatinya memiliki kehati-hatian bahkan kepada hal-hal yang secara lahiriah halal, misal tidur. Mereka mengurangi tidur panjang dalam maksud menguatkan keintiman bersama Allah Swt. Entah melalui tafakur, tadabur, ziarah, dzikir, dan lainnya.
Situasi tersebut tentulah beda dengan orang awam yang selubung hatinya begitu tebal terhijabi. Dan seterusnya.
Pesan ketiganya ialah meyakini selalu bahwa ejawantah Cahaya Allah Swt yang bersumber dari DzatNya yang Qadim dan ‘Azali, yang sangat Agung tak terjangkau, yang berhasil kita rasakan merupakan “caraNya” untuk mengenalkan diriNya kepada kita. Agar kita lalu semakin dalam dan khusyuk dalam menyembahNya, memujaNya, dan menauhidiNya. Dan “cara Allah Swt” sungguhlah tiada terkira….
Begitu baikNya Allah Swt kepada semua kita, semua manusia, hingga Allah Swt berkenan meruahkan rahmat-rahmatNya dalam pelbagai bentuk ejawantahNya yang tiada ternalar sama sekali keluasan rupa dan bentuknya.
Begitulah kiranya fadhilah mi’rajNya kepada kita semua. Semoga Allah Swt senantiasa menolong dan menjaga kita. Amin.
Wallahu a’lam bish shawab.
Jogja, 15 September 2019