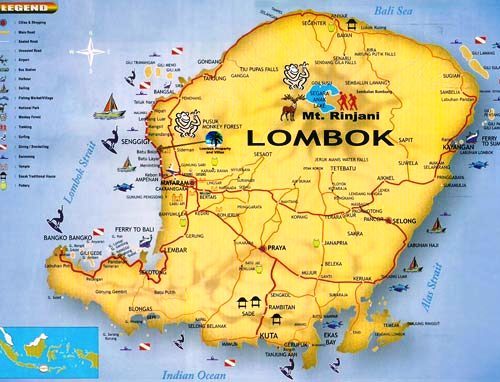Oleh Edi AH Iyubenu, esais dan wakil ketua LTN PWNU DIY @edi_akhiles
Meruahnya keluhan masyarakat melalui berbagai media, utamanya sosial media, perihal kerap terjadinya praktik-praktik khutbah (utamanya pada shalat Jumat) yang disinyalir bermuatan ideologis-sektarian, ujaran kebencian (hate speech), hingga takfir (di dalamnya tercakup penyalahan dan penyesatan pada amaliah-amaliah pihak lain yang telah mapan dan diterima luas di kalangan umat Islam Indonesia) telah direspons sejak lama oleh Manteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin. Publik kemudian mengenalnya sebagai wacana sertifikasi khatib. Pro dan kontra pun terjadi. Dan, yang terbaru, Kementerarin Agama merilis rekomendasi (catat: rekomendasi) sejumlah nama dai, muballigh, dan khatib yang dinyatakan “otoritatif” –sembari tak menafikan pertambahan-pertambahan atau koreksi-koreksi yang bisa dikembangkan kemudian. Ini pun memicu pro dan kontra.
Menteri Agama kemudian memberikan klarifikasi bahwa Kementerian Agama tidak bermaksud melakukan legislasi sertifikasi khatib (sebagaimana pula tidak bermaksud menjadikan harga mati dalam rekomendasi para dai, muballigh, dan khatib), karena secara teknis hal itu akan sangat pelik dan sensitif. Yang kiraya sangat penting dimafhumi oleh para dai, muballigh, dan khatib, tegas Menteri Agama, ialah jangan sampai khutbah terjatuh kepada tindakan-tindakan atau ujaran-ujaran diskriminatif antargolongan, antarkelompok muslim, tegasnya terendus menguarkan SARA, sehingga rawan memicu perpecah-belahan di antara umat Islam sendiri dan seluruh elemen bangsa ini umumnya. Tentu ini sangat bisa disepakati. Kemudian, yang juga urgen dimafhumi publik luas ialah bahwa sikap dan kebijakan Kemenag tersebut dapat diisyaratkan sebagai langkah konkret otoritas sah negara dalam bidang keagamaan dalam merespons laporan dan realitas lapangan yang terjadi dalam praktik-praktik khutbah keagamaan yang tiada lain kecuali dimaksudkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan keutuhan NKRI yang majemuk.
Mekanisme Kontrol
Masjid sebagai “rumah bersama” idealnya memang tidak menjadi tempat shalat belaka. Sebagaimana di Masjid Nabawi Madinah dan Masjidil Haram Mekkah, masjid-masjid juga menjadi wadah edukasi keislaman dan sosial-kemasyarakatan bagi umat Islam.
Situasi ideal tersebut telah diteladankan oleh Nabi Muhammad Saw yang menjadikan masjid sebagai sentral produksi peradaban umat Islam era awal. Dalam arus yang murni edukatif tersebut, kita mengerti dengan mudah betapa mendesaknya untuk membingkai segala aktivitas non mahdhah di masjid, sebutlah pengajian, ceramah, khutbah, atau pun diskusi agama dan keumatan, tidak sepatutnya terjerumus pada aksi-aksi tendensius apa pun, entah politik partisan atau publikasi pemahaman keagamaan yang rawan tendensi sektarian.
Di negeri kita, pola penunjukan khatib lazimnya dilakukan melalui mekanisme rapat takmir masjid dan tokoh masyarakat. Pilihan para khatib niscaya berkorelasi erat dengan kapasitas pandangan, jaringan, dan jangkauan para pengurus masjid itu sendiri.
Boleh jadi ada sebuah masjid yang mampu mendatangkan para khatib dengan integritas keilmuan dan keislaman yang telah terbukti mumpuni secara akademik, tetapi ada pula masjid yang hanya mampu menghadirkan khatib yang sebenarnya secara pondasi keilmuan kurang memadai. Misal tidak fasih membaca ayat dan hadits, tidak memahami kaidah bahasa Arab, atau tidak memiliki basic ilmu-ilmu sosial-kultural yang notabene sangat vital dalam bangunan pemahaman keislaman.
Jika kedua contoh kapasitas khatib ini berhenti hanya di level syiar Islam yang otentik, niscaya tidaklah akan menjadi masalah aapa-apa. Kalaupun ada dampak keterbatasan pengetahuan dan integritas khatib, ia bisa ditoleransi sebagai proses pembelajaran semua sumber daya yang terlibat di dalamnya.
Akan tetapi tentu akan jauh berbeda dampaknya bagi masyarakat bila kedua level integritas khatib ini memuat kepentingan-kepentingan ideologis-sektarian atau politis-praktis-partisan. Misal hasrat menyatakan amaliah-amaliah tertentu salah dan sesat dengan pelbagai argumennya –yang tentu saja bisa dibantah oleh argumen-argumen pelaku amaliah-amaliah tersebut—seperti amaliah tahlilan, tawashul, dan ziarah kubur yang paling amat sering dijadikan sasaran tembak. Jika praktik khutbah sejenis ini dikuarkan terus-menerus, tentunya potensial benar memantik perselisihan dan bahkan perpecahan dan sentimen sosial di antara umat Islam sendiri.
Potensi rawan berikutnya ialah tatkala materi khutbah yang disampaikan seseorang lahir dari kurangnya pengetahuan keislaman (luasnya tafsir dan pandangan para imam mazhab dan mufassir) plus dibalut kengototan persoalnya akan kebenaran pandangannya. Ini pun sangat problematis.
Tentu disayangkan jika materi khutbah yang bersumber dari pengetahuan yang dangkal, lateral, dan tidak kontekstual dengan realitas majemuk masyarakat setempat dipanggungkan di mimbar-mimbar khutbah dengan cara-cara yang hegemonik. Ia amat berisiko hanya mewedarkan narasi-narasi khutbah yang saklek, artifisial, bahkan terjatuh pada klaim benar dan fatwa salah. Pada produksi khutbah begini, kemajemukan pemahaman dan pandangan serta anutan umat Islam menjadi rawan terpecah-belah.
Sudah niscaya menjadi problematis benar tatkala materi-materi khutbah sejenis itu ditelan bulat-bulat oleh masyarakat yang kurang kritis. Balutan ayat-ayat, hadits-hadits, dan kitab-kitab salaf yang dinukil secara sepihak, misal, bisa menciptakan world view yang memukau secara religius di mata jamaahnya tetapi secara sosial yang luas justru rawan memantik keretakan-keretakan. Akhirnya masyarakat majemuk yang mulanya guyup menjadi terpolarisasi secara biner benar versus salah dan bahkan faksional-ideologis ahli puritan versus ahli bid’ah.
Bukti-bukti nyata atas meruahnya khutbah-khutbah sejenis sangat mudah dijumpai hingga ke masjid-masjid di pelosok kampung seiring dengan memanasnya berbagai fenomena politik yang dibingkai tashih-tashih keagamaan, sebutlah Pilkada di masa lalu dan sebentar lagi Pilpres. Ontran-ontran pengharaman memilih pemimpin non-muslim, misal, begitu mudahnya menggema dari speaker-speaker masjid tanpa tedeng aling-aling, yang jelas sangat rawan menyakiti perasaan teologis tetangga-tetangga masjid yang berbeda keyakinan dan pilihan politik. Kohesivitas asali warga kampung yang majemuk menjadi pertaruhan sosial yang amat mahal harganya untuk dibiarkan terus menerjal.
Di Jakarta, dengan mengelus dada, kita telah menyaksikan bagaimana ekstremnya dampak pilihan politik yang profan itu merasuki persoalan-persoalan keislaman yang sakral. Masjid lalu menjadi corong politik-pragmatis-partisan; tatanan sosial yang majemuk dikoyak oleh tegaknya spanduk yang mengharamkan shalat jenazah pada pemilih politik tertentu yang berbeda. Sungguh menyedihkan.
Pada derajat inilah, mekanisme kontrol pengurus masjid dan tokoh masyarakat menjadi modal dan strategi sosial yang harus selalu dijaga. Kohesivitas masyarakat yang majemuk jelas merupakan pondasi utama public sphere yang harus selalu dilindungi dari percik-percik hate speech berbingkai narasi-narasi keislaman, seperti khutbah-khutbah politis dan ideologis.
Di masjid kampung saya, misal, An-Nur, Bantul, takmir masjid bersepakat meletakkan kode etik bahwa siapa pun khatibnya bila menyampaikan materi faksional-ideologis dan berbau hate speech, ia tidak akan diundang lagi. Ini menjadi langkah nyata para pengurus masjid dan tokoh masyarakat setempat untuk melindungi marwah kohesi sosial kemasyarakatan senantiasa sejuk dan harmonis.
Andai narasi-narasi khutbah dan ceramah yang bernuansa sektarian dan bahkan ideologis itu didenyarkan dalam ranah personal atau kelompok eksklusif saja, sudah pasti itu hak bebas setiap orang dan kelompok untuk merayakannya sebagai hadiah indah dari demokrasi yang kita anut –tentu, sepanjang tidak bertentangan dengan tata aturan legal-formal pemerintah. Tetapi pada ranah sosial-masyarakat yang majemuk, public sphere semacam masjid, semua kita seyogianya selalu mengerti dan taat bahwa kita diikat penuh oleh hukum positif negara dan norma adat masyarakat setempat.
Tepat pada senantiasa adanya ikatan formal berbangsa dan bermasyarakat inilah –sebagai modal utama keharmonisan semua kita—kiranya jauh lebih afdahl, ahsan, dan Islami bila setiap kita yang kebagian jadwal khutbah, ceramah, dan taushiyah menjadikan panggung-panggung publik itu sebagai medium untuk menyerukan keimanan, kebaikan, keadaban, dan keharmonisan sosial sebagai puncak marwah Islam yang rahmatan lil ‘alamin dan berakhlak karimah.
Semoga.