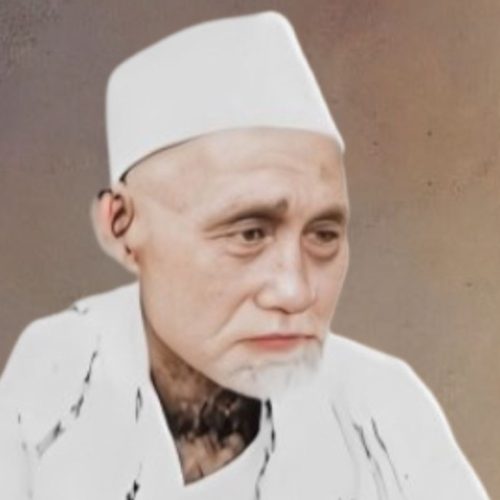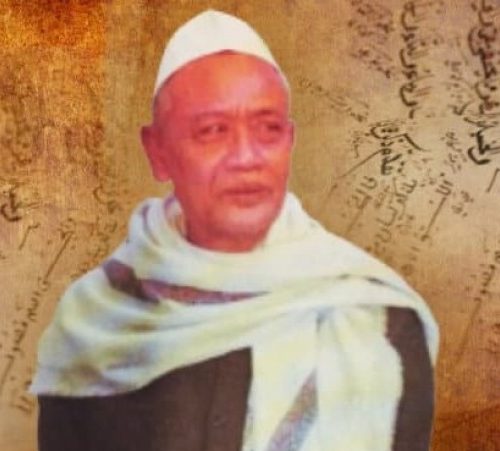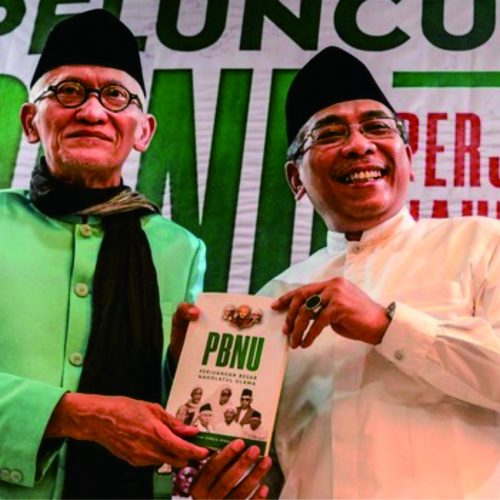Prof KH Muhammad Machasin, Mustasyar PBNU
Di dalam sejarah umat Islam, agama selalu kelihatan—atau sengaja ditampilkan agar kelihatan—mendasari hampir seluruh tindakan, kebijakan dan sikap penguasa, serta gerakan masyarakat. Halal-haram, boleh atau tidak boleh, pantas atau tidak pantas selalu dilandasi alasan keagamaan. Ini dilakukan untuk pengabsahan atau keabsahan semua itu.
Orang kebanyakan pun sangat mudah digerakkan dengan alasan keagamaan. Ini antara lain yang tampak dalam semacam konsideran yang terbaca dalam surat perintah al-Ma’mun kepada pejabat kepercayaannya untuk melakukan pengujian terhadap keimanan para pejabat dan tokoh masyarakat. (Saat itu Khalifah sedang berada di Tarsus [Ταρσός], di pantai selatan Turki, dalam usaha melebarkan kekuasaan ke wilayah Romawi Timur).
Akan tetapi juga perlu diingat logika kekuasaan yang mencakup hal-hal seperti bahwa tidak boleh ada pesaing yang dirasakan mengancam kekuasaan sang penguasa. Tidak boleh ada matahari kembar. Karena itu, sikap terhadap pesaing adalah “dukung aku atau kau kusingkirkan”. Kekuasan politik juga diperoleh dari pengabsahan dari orang banyak dalam bentuk kepatuhan semua orang yang berada di dalam wilayah kekuasaan. Keabsahan sering kali dikalahkan oleh ketiadaan pengabsahan dari orang banyak.
Di konsideran yang disinggung sebelumnya pun kelihatan logika kekuasaan: ada orang-orang tertentu yang berusaha untuk menguasai jiwa orang banyak atau rakyat awam. Mereka bertindak seakan akan pemimpin yang memberikan keadilan kepada rakyat (وتصنعا للرياسة والعدالة فيهم). Orang-orang itu menyatakan diri sebagai ahl al-Sunnah, orang-orang yang berpegangan dengan tradisi yang berasal dari Nabi. Tentu al-Ma’mun tidak setuju dengan klaim mereka itu dan karenanya memerintahkan untuk memeriksa kemurnian akidah mereka.
Di sini berkelindan antara tugas keagamaan dan kepentingan politik atau yang disebut al-dīnī wa-l-siyāsī (الديني والسياسي). Tindakan politik berwarna agama, tindakan keagamaan bercorak politik.
Menjadi pertanyaan yang masih sulit untuk dijawab: Mengapa al-Ma’mūn menjatuhkan perintah miḥnah ketika ia berada jauh dari pusat pemerintahan?
Khalifah ini memang mengokohkan kekuasaannya di luar ibu kota. Ketika saudaranya lain ibu, al-Amīn menjadi Khalifah di Baghdad, ia memerintah di wilayah timur kekhalifahan yang berpusat di Khurasan. Oleh ayahnya, Hārūn al-Rasyīd, ia diberi kewenangan untuk mengelola kekuasaan di tempat asal ibunya ini dengan kebebasan yang sekarang dapat disebut otonomi seluas-luasnya.
Setelah ayah mereka meninggal, al-Amīn yang menggantikan sang ayah sebagai Khalifah berusaha untuk mengurangi kewenangan al-Ma’mūn. Al-Ma’mūn tidak menerima perlakuan al-Amīn dan terjadilah perang saudara yang berakhir dengan kekalahan, bahkan kematian, al-Amīn. Peperangan ini menjadikan Baghdad kehilangan keamanan antara lain karena al-Amīn yang kekurangan pasukan mempekerjakan kaum preman (al-‘ayyār) dan runtuhnya kendali pemerintahan.
Dalam keadaan seperti ini muncul kelompok-kelompok pengamanan sukarela yang disebut al-Muṭawwiʻah (المطوّعة). Kebanyakan pemimpin dan anggota kelompok-kelompok ini adalah kaum Ahl al-Ḥadīts yang di antara pemimpinnya yang paling dihormati adalah Aḥmad bin Ḥanbal (lengkapnya: Abū ‘Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal al-Syaibānī al-Dzuhlī, 164-241 H/780-855 M). Karena tindakan mereka Baghdad pun kembali kepada keamanannya dan karenanya banyak orang merasa berhutang budi kepada mereka. Mereka sangat disukai rakyat di ibu kota, sementara sang pemenang masih berada jauh di Khurasan.
Tambahan lagi, Aḥmad bin Ḥanbal dan kaum Ahl al-Ḥadīts telah berhasil dalam menyerukan penghormatan kepada ‘Alī bin Abī Ṭālib dalam apa yang disebut al-tarbīʻ (التربيع, penyebutan sebagai yang keempat), yakni memasukkannya dalam “Para Khalifah yang Lurus” (al-Khulafā’ al-Rāsyidūn الخلفاء الراشدون). Bani hanya menyebut tiga Khalifah dari mereka: Abū Bakr, Umar dan ‘Utsmān. Kemudian Imam Aḥmad menyerukan untuk memberikan penghormatan yang wajar juga kepada Muʻāwiah. Tentu ini membuat gerah penguasa Bani ‘Abbas yang ada saat itu. Akan tetapi, menurut kalkulasi politik, tidak mungkin melakukan tindakan kekerasan kepada orang-orang yang mendapat dukungan dari rakyat. Salah-salah justru akan timbul pembangkangan besar-besar yang akan berakibat kekacauan. Mungkin karena perhitungan ini juga, al-Ma’mun baru masuk Baghdad enam tahun setelah al-Amin terbunuh (198 H), yakni pada tahun 204 H.
Perlu pula diperhatikan bahwa beberapa dari orang-orang yang diajukan ke pengadilan miḥnah adalah orang-orang yang mempunyai track-record permusuhan kepada Bani ‘Abbās, seperti Abū Mashar al-Dimasyqī, Ibrāhīm bin al-Mahdī, Aḥmad bin Naṣr al-Khuzāʻī dan Yazīd bin Hārūn. Jadi, miḥnah dapat disebut sebagai semacam “balas dendam” terhadap musuh-musuh lama.
Juga menarik untuk dicatat bahwa al-Ma’mūn baru menjatuhkan perintah miḥnah pada tahun terakhir masa hidupnya (218 H), padahal ia sudah duduk di singgasana Baghdad sejak tahun 204 H.
Apakah ini karena masih banyak pemberontakan di daerah-daerah tempat banyak pendukung al-Amīn? Karena ia belum menemukan cara yang dianggap aman untuk menyingkirkan lawan-lawannya? Atau karena ia belum yakni bahwa alasan keagamaan itu efektif untuk mencapai tujuannya? Atau karena ia baru menemukan orang yang dianggap dapat diandalkan untuk mendukung kebijakan ini, yakni Ibn Abī Du’ād?
Mungkin gabungan dari semua persoalan itu yang membuatnya menunggu sampai 14 tahun (dari saat ia masuk Baghdad) atau bahkan 20 tahun (sejak al-Amīn terbunuh).