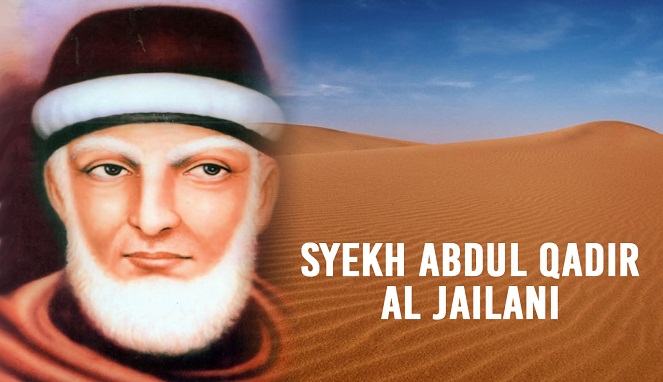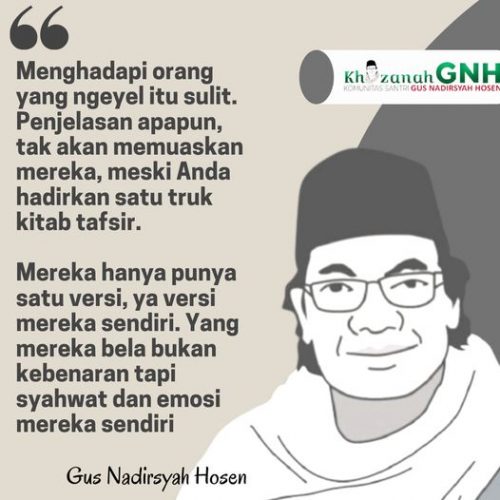Oleh Edi AH Iyubenu, Wakil ketua LTN PWNU DIY
Pertanyaan besar sejak zaman dulu kala di kalangan para ahli kalam ialah apakah kita yang dzat nisbi ini bisa memandang Allah Swt yang Dzat Hakiki?
Dalam kitab Adab al-Suluk wa at-Tawashshul Ila Manazil al-Muluk, Syekh Abdul Qadir al-Jailani qaddasahuLlah menjelaskan:
“Tuhan dapat dipandang melalui mata Basyirah, yakni mata hati. Hanya orang-orang yang telah bermakrifat kepada Allah Swt yang bisa merasakannya. Namun, ada pula cara lain untuk memandangNya, yakni dalam perasaan yang tak dapat disifatkan, bahkan musykil diungkapkan dalam bentuk apa pun, seperti mereka yang tidak dapat memulai ibadahnya bila tidak memandang Allah Swt.”
Beliau qaddasahuLlah kemudian melanjutkan bahwa selain melalui perjumpaan langsung dengan Allah Swt (langsung di sini maksudnya adalah ‘manifestasi sifat keindahan dan kesempurnaan Allah Swt’) di akhirat kelak kepada para mukmin (insya Allah), di dunia ini bisa saja Allah Swt dipandang melalui pendzahiran sifat-sifatNya yang memantul dari cermin hati yang bersih dan suci.
Beliau qaddasahuLlah mengutip ungkapan Umar bin Khattab: “Hatiku melihat Tuhanku dengan cahaya Tuhanku.” Juga tuturan Ali bin Abi Thalib: “Aku tidak akan memohon kepada Allah Swt melainkan aku melihatNya.”
Begitulah contoh dari “keduanya (Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib) yang telah melihat pendzahiran sifat-sifat Keilahian.”
Lebih sederhana lagi, beliau qaddasahuLlah memberikan ilustrasi berikut: “Bila seseorang melihat cahaya matahari melalui jendela dan berkata, ‘Aku melihat matahari.’, maka ia telah berkata benar. Allah Swt memberikan contoh yang paling indah tentang pendzahiran sifat-sifatNya.”
Dalam pemahaman kita, apa yang dimaksud dengan “Aku melihat matahari.”, sejatinya mata hati tidaklah berhenti pada pendar-pendar cahaya matahari yang disaksikan mata lahiriah di pagi hari yang indah, menelusup dari balik dedaunan, diiringi cericit burung-burung. Basyirah yang peka dan tajam akan jauh melampaui wujud cahaya matahari yang terpandang mata lahiriah itu, menyeruak ke dalam batin sebagai pandangan atas Kemahaindahan Allah Swt serta KemahakuasaanNya yang bertahta di balik semburat cahaya matahari lahiriah itu.
Ini dalam kajian tasawuf lazim disebut tajalli: manisfetasi tanda-tanda kemahakuasaan Allah Swt dalam segala bentuknya di dunia ini, seperti cahaya matahari pagi itu.
Dalam surat al-Baqarah ayat 26, misal, Allah Swt berfirman: “Sesungguhnya Allah Swt tidak segan memberikan perumpamaan berupa nyamuk atau (makhluk) yang lebih rendah lagi. Maka orang-orang yang beriman akan berkata bahwa perumpamaan ini adalah benar dari sisi Allah Swt….”
Maksud “benar dari sisi Allah Swt” tersebut ialah meyakini kemahaan Allah Swt dalam wujud diciptakanNya nyamuk, yang bila semakin dalam dan sublim akan berakhir dengan lirih bisik batin: rabbana ma khalaqta hadza bathilan subhanaka faqina ‘adaban nar, ya Tuhan kami, tiada hal yang Engkau ciptakan dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, selamatkanlah kami dari azab neraka….
Pernahkah kita merasakan desir ketakjuban rohani demikian di dalam batin tatkala menyaksikan gerimis di depan mata kepala ini?
Jika iya, itulah yang dimaksud desir tajalli tadi. Tepat pada hadirnya rasa kagum tersebut, yang bekerja pada batin ialah Mata Basyirah, Mata Batin, ‘Ain al-Basyirah. Allah Swt dalam segala wujud kejalaliyahan dan kejamaliyahanNya menjadi terpandang di dalam hati kita.
Buahnya adalah ketundukan diri kepada perintah-perintahNya, kerendahan diri di hadapan kemahakuasaanNya, dan meruah dalam rupa kerendahan hati kepada seluruh makhlukNya.
Merawat sinyal Mata Batin (‘Ain al-Basyirah) begini agar terus menyublim di dalam hati, hingga menjadi jiwa eksistensial kita dalam seluruh gerak-gerik laku kehidupan, entah dalam peribadatan maupun pekerjaan, meniscayakan memanunggalingnya diri ini dalam rengkuhanNya selalu.
Rezeki yang didapatkan dari sebuah pekerjaan menjadi tertejemahkan sebagai karuniaNya semata; makanan dan minuman yang disantap, menjadi terpandang sebagai karunia Rahman RahimNya semata; kesehatan yang melimpah menjadi terpandang sebagai kesyukuran belaka kepada karuniaNya, dlsb.
Syekh Abdul Qadir al-Jailani qaddasahuLlah menukil hadis Rasul Saw tentang seorang mukmin sebagai cermin bagi mukmin lainnya (al-mukminu mir-atul mukmin).
Apa yang dimaksud mukmin pertama ialah diri yang hatinya telah membasyirah di hadapan segala kejadian, peristiwa, pahit mupun manis, lapang maupun sempit, sebagai makhlukNya semata yang Dia Swt mentajalli di dalamnya. Allah Swt adalah Dzat yang Mutajalli. Segala pandangan mukminnya yang telah semata “menjelma Kemahaan Allah Swt” begitu adalah maujud Mukmin kedua.
Ini bukan berarti lalu diri yang mukmin-manusia menjelma MukminNya Swt. Tidak. Tetapi Allah Swt sebagai Mukmin Yang Hakiki mentajalli kepada mata Basyirah diri mukmin-manusia. Wujudnya tetaplah dzat yang wadag dan Dzat Hakiki yang berbeda, tak sama, tetap Dzat Yang Hakiki itu memantul bagai Cahaya Cermin bagi mukmin yang wadag. Mari renungkan: bukankah salah satu asma Allah Swt adalah Al-Mukmin?
Diri mukmin pertama (rohani serta wadagnya) selalu memandang keterleburannya sendiri dalam Diri Mukmin Allah Swt (Diri Kedua). Inilah maksud ungkapan “Memandang Allah Swt dengan ‘Ain al-Basyirah”.
Wallahu a’lam bish shawab.
Jogja, 28 Agustus 2019