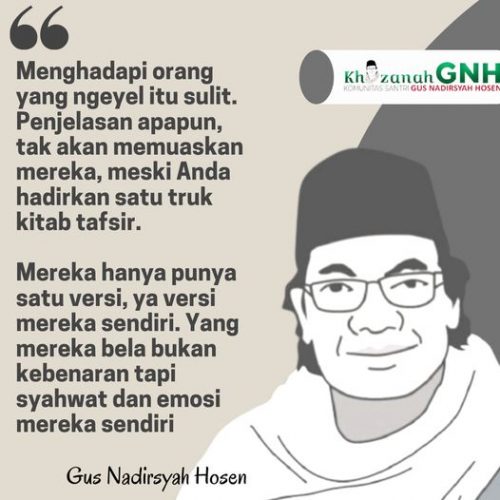Oleh Edi AH Iyubenu, wakil ketua LTN PWNU DIY.
Para sufi atau ahli makrifat, juga para salik, senantiasa menasihatkan dan sekaligus mengamalkan kepatuhan syariat dengan cara yang luar biasa. Sampai di sini, sekilas, mereka nampak sama belaka dengan orang-orang umum yang juga menjalankan amaliah syariat dengan kepatuhan tinggi.
Namun sesungguhnya yang menjadikan mereka berbeda ialah syariat sebagai amaliah lahiriah tidak diberhentikan hanya sebagai lelaku ritual legal-formal, seperti sujud, rukuk, dzikir, puasa, mendaras al-Qur’an, sedekah, dan sebagainya. Amaliah syariat itu sekaligus dijadikan pintu masuk lebih dalam bagi amaliah rohaniahnya, batiniahnya, dengan muara spiritual setamsil kemesraanhakiki bersama Allah Swt. Melalui lelaku kedua pilar amaliah inilah mereka menggapai puncak makrifatulLah –dalam pelbagai istilahnya, seperti mahabbah, ittihad, wahdlatul wujud, ‘arif, tauhid, hingga manunggaling kawula Gusti.
Barangkali, dan boleh jadi, adanya sejumlah kalangan yang memandang kurang sejuk terhadap pelaku tasawuf semenjak dulu semata dipantik oleh pemahamankurang utuh terhadap pernyataan sejumlah sufi dan salik yang terkesan di permukaan “menyepelekan” amaliah syariat.
Ibnu Taimiyah, misal, dalam literatur yang saya jangkau sesungguhnya tidak pernah benar-benar menyatakan menolak tasawuf, kendatipun ia tak pula terobsesi untuk mengakui tasawuf secara jalan lelaku kesalehan yang khusus. Iapernah menyebut Syekh Abdul Qadir al-Jailani sebagai “syaikhuna” (guru, leluhur, kami) yang menandakan ta’dhim mendalamnya kepada sulthanul auliya’ itu.
Ia hanya menyebutkan bahwa praktik tasawuf yang dilakoni dengan “jalan ketarekatan” –yang tak dicontohkan oleh Rasulullah Saw—dan apalagi sampai menepikanotoritas syariat atau menomorsekiankannya adalah masalah tauhid yang sangat serius.
Model beginilah yang ia tampik. Baginya, mematuhi syariat bagi seorang muslim adalah kewajiban mutlak dan cara menjalankannya adalah semata dengan meneladani amaliah Rasulullah Saw. Ihwal kemudian pelaku syariat menekurinya dalam permenungan mendalam hingga lahir taqarrub ilalLah, itulah tugas hakiki seorang hamba Allah Swt. Maka, baginya, berbaiat kepada sebuah tarekat sama sekali bukanlah kewajiban tauhid dan malah mesti diwaspadai supaya tidak terjerumus ke dalam praktik berislam yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Saw.
Baiklah, insya Allah suatu saat saya akan tuliskan khusus perihal Ibnu Taimiyah dan Tasawuf ini.
Sekarang, saya akan mengangkat tiga tokoh besar dalam tradisi sufistik yang kita kenal, yang sama-sama menyatakan dan mengamalkan sekaligus kepatuhan syariat dengan cara yang luar biasa.
Pertama, Imam Junaid al-Baghdadi (830-910 M). Beliau lebih suka memilih sebutan ‘arif dan tauhid ketimbang makrifat atau makrifatulLah untuk menunjuk orang-orang saleh yang menggapai derajat keluhungan rohani. Betul, walau secara istilah tak sama, pada hakikatnya apa yang dimaksud ‘arif dan tauhid oleh beliau adalah kemakrifatan ala ahli tasawuf itu sendiri.
Dalam sebagian suratnya, beliau pernah mengungkapkan kemasygulan terhadap praktik tasawuf yang “kebablasan”, yang ditujukannya kepada ungkapan-ungkapan mistis sejumlah sufi yang menimbulkan kontroversi khalayak. Salah satu yang beliau maksudkan adalahal-Hallaj yang terkenal dengan ungkapan mistis “Ana al-Haq” (Akulah Sang Kebenaran), yang ternyata pernah menjadi muridnya.
Kemasygulan beliau ini tidak bisa diartikan bahwa Imam Junaid menista al-Hallaj dengan trimatra ajaran sufinya: Ittihad (penyatuan diri dengan Allah Swt), Hulul (infusion, penyerapan diri dari/kepada Allah Swt), dan Wahdlatul Wujud (Manunggaling Wujud). Tidak. Tak pernah ada pernyataan terbukanya yang menunjukkan hal demikian.
Yang ada adalah (dan nampaknya inilah tujuan utama Imam Junaid) dorongan untuk menghindarkan polemik di masyarakat dan sekaligus risiko intimidasi penguasa yang tidak berada di derajat pemahaman yang sama dengan tasawuf yang begitu rupa, yang kemudian hanya akan menisbatkan masalah-masalah sosial-politik bagi para ahlus shuffah. Dan ini memang terjadi kemudian. Al-Hallaj dihukum gantung dan para sufi mesti bersembunyi dari kajian dan kegiatannya setelah insiden itu.
Imam Junaid menasihatkan bahwa ketundukan kepada syariat Allah Swt yang haq, yakni al-Qur’an dan sunnah Rasul Saw, adalah keniscayaan amal yang mesti dijunjung selalu oleh siapa pun, termasuk para sufi. Inilah jalan yang benar untuk menggapai derajat ‘arif dan tauhid itu.
Namun, tentu saja, amaliah lahiriah syariat ini pun mesti difondasikan kepada jelajah rohani dan batiniah yang mendalam. Tak cukup hanya berhenti di praktik amal lahiriah legal-formal.
Maka, misalnya, lalu muncul ungkapan kondangnya: “Aku ingin menjadi awan yang menaungi para saleh dan tidak saleh di bawahnya; aku ingin menjadi bumi yang di atasnya berjalan orang saleh dan ahli maksiat; dan aku ingin menjadi hujan yang mengalir ke tempat yang bersih dan pula tempat kotor….”
Tepat pada ungkapan esoteris ini, kita memahami dengan mendalam bahwa gapaian rohani ‘arif (atau makrifat) tersebut menandakan telah beyond-nya beliau dari sekat-sekat primordial kemakhlukan. Ia yang mendirikan Madrasah Sufi di Baghdad telah sampai pada mata hakikat dalam memandang segala realitas semata dari kacamata Gusti Allah Swt –sebagaimana yang pula dituturkan para salik lainnya.
Kedua, Imam Ghazali (1058-1111 M). Tokoh satu ini dikenal sekali di antara kita. Ia berlatar akademisi dan teoritikus yang sangat cemerlang, tetapi kemudian meninggalkannya di usia lanjut demi melakoni jelajah rohani dengan karakter kezuhudan yang paripurna. Terlihat jelas kualitas teoritisnya kala beliau mengkritik tajam para filsuf melalui Tahafut al-Falasifah –yang kemudian dikritik balik oleh Ibnu Rusyd (generasi sesudahnya) melalui buku Tahafut Tahafut al-Falasifah—dan juga buku Kimyatus Sa’adah (Kimiawi Kebahagiaan) yang sangat bernas ilmiah itu.
Karya emasnya, Ihya’ Ulumuddin, oleh Annemarie Schimmel disebut sebagai ‘generated system of Islamic law”. Kita kini terus membaca dan mengkajinya –di kita hari ini yang sangat fenomenal ialah kegiatan “Ngaji Online Ihya’ bersama Gus Ulil Abshar Abdalla” yang semakin sering dihelat di darat pula.
Terlihat jelas dalam kitab tersebut betapa Imam Ghazali sangat menekankan pentingnya memahami dan melakoni sekaligus syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Swt dan RasulNya. Ihya’ Ulumuddin memuat ajaran syariat cum fiqhnya dengan sangat luas –dengan kekhasan utama, yakni berbingkai nilai-nilai sufistik.
Beliau dengan lantang pula mengatakan: tiada makna apa-apa perjalanan tawasuf tanpa fondasi amaliah syariat yang baik.
Karakter utama tasawufnya yang amat diberi penekanan luar biasa –dan sekaligus diamalkannya—ialah kezuhudan. Bab zuhud langsung diterakan di bagian awal kitab Ihya’ Ulumuddin dengan jelas dan terus tersebar nilai-nilainya di nyaris seluruh bagiannya hingga jilid terakhir. Dari watak zuhud ini, berlabuhlah beliau kepada konsep Mahabbah (Cinta).
Beliau memberikan ilustrasi menarik tentang Cinta ini melalui cerita seseorang yang mencintai anaknya dan rindu betul untuk berjumpa. Maka segala apa yang datang dari anaknya (entah sekadar kabaratau perlambang) akan sangat diterimanya dengan hati senang dan tiada lagi kepedulian baginya kepada selain-selainnya.
Begitulah seyogianya cahaya rohani seorang Pencinta kepada Tuhannya. Apa pun yang datang dari Tuhannya, ia mencintai dan menyenanginya hingga tak lagi sudi berpaling kepada selain-lainNya.
Hal menarik lainnya dari Imam Ghazali yang mengikuti Mazhab Syafii ialah nasihatnya ini: “Ilmu pengetahuan tidaklah sempurna bila belum berfondasikan Cinta dan Cinta kepada Allah Swt takkan bisa memenuhi hati manusia bila belum disucikan dari segala cinta kepada dunia (dan seisinya) yang hanya bisa didapatkan dengan jalan kezuhudan.”
Ketiga, Syekh Abdul Qadir al-Jailani (1077-1166 M). Beliau yang lahir di Iran ini dijuluki Sulthanul Auliya’, pemimpin para waliyulLah, dan juga mursyid Tarekat Qadiriyah atau sering pula disebut Qadiriyah-Naqsabandiyah yang diikuti dengan luas di negeri ini.
Dalam sejumlah karya emas yang diwariskannya, sebutlah Sirrul Asrar dan Jala’ al-Khatir, terang sekali dipaparkan bahwa kepatuhan kepada syariat Allah Swt sebagaimana dikandung oleh al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah Saw adalah kewajiban yang tak boleh dipinggirkan oleh semua pelaku hakikat (salik). Amaliah syariat adalah pilar bagi seluruh perjalanan rohani para saleh.
Syekh Abdul Qadir al-Jailani dengan terang melontarkan peringatan rohani kepada para sufi agar tak pernah mengendurkan praktik patuh syariat ini dengan dalih apa pun. Dalam bab dzikir, misal, beliau menyatakan bahwa ingat dan menyebut Allah Swt mestilah menjadi bagian lekat dari hidup seorang hamba Allah Swt, seorang saleh. Apalagi amaliah-amaliah mahdhah.
Tentu, ajaran beliau tak hanya berhenti di derajat lahiriah ini. Beliau pun menasihatkan dengan panjang lebar ihwal pintu masuk lebih dalam kepada kemesraan dengan Allah Swt, yakni denganmenggapai kualitas hati yang bersih dari setitik noda dunia dan ketergantungan kepada makhluk. Ada nuansa kuzuhudan dan sekaligus ketawakalan di dalamnya.
Jika kita, dengan kata lain, masih terikat kepada kekuatan-kekuatan makhluk (atau orang lain), itu menandakan hati kita belumlah benar-benar bersih dan itulah penghalang (hijab) bagi rohani kita untuk mengenal Allah Swt –apalagi intim manunggal denganNya.
Maka, selain dengan menjalankan perintah-perintah syariat Allah Swt sepenuh patuh, seorang salik mestilah senantiasa menghiasi dirinya dengan amaliah-amaliah Cinta lainnya kepada Allah Swt, seperti dzikir tiada henti dan tobat dalam amal kebaikan sekalipun.
Dari dua tamsil ini saja terlihat bahwa capaian rohani yang jernih –sebagai tujuan utama lelaku tasawuf—tidaklah kafah untuk hanya bersendi kepada amal-amal lahiriah kebaikan (seperti rajin shalat, puasa, sedekah, dll.), tetapi mesti melompat terus menuju kemanunggalan dengan Allah Swt dalam wujud keyakinan kafah bahwa Allah Swt lah Yang Maha Kuasa atas segala hal (termasuk kita bisa patuh syariat) sedang kita tak lebih dari sekadar ‘wayang’ yang melakoninya. Ini dikenal dengan ajarannya: at-tabarrau minal haul wal quwwah (terbebaskannya rohani diri dari merasa mampu menjalankan perintahNya dan mampu menjauhi laranganNya).
Dari konteks rohani ini, lahirlah lalu ajaran beliau berikutnya kepada kita untuk terus intim dalam kesabaran dan ketawakalan semata kepada Kehendak Allah Swt.
Begitulah segelintir ajaran, nasihat, dan tuturan para sufi agung ini.
Terang sekarang bahwa lelaku rohani mestilah selalu sejalan seiring dengan lelaku syariat. Mari mawas diri dan berendah hati, sedangkan para ulama agung saja sangat menekankan dan mengamalkan syariat dengan luar biasa, bagaimana mungkin kita yang awam-awam ini lancang mendaku salik di saat kualitas kepatuhan syariat kita masih tergolong biasa-biasa saja?
Mari pula kita buat tolak ukur lahiriah kepada diri masing-masing: “Tatkala kepatuhan amaliah syariat kita semakin waktu semakin meningkat kuantitas dan kualitasnya, itulah sejatinya isyarat rohani bagi kita untuk memasuki pintu yang lebih dalam dan dalam lagi dengan mengarungi samudera olah rohani melalui tafakkur dan riyadhah demi menuju lebih dekata kepada WajahNya ‘Azza wa Jalla.
Mari secara kognisi kita mesti memahami dengan seksama –dengan menukil nasihat Imam at-Thusi rahimahulLah—bahwa syariat Allah Swt itu tidak hanya mengandung perintah amaliah lahiriah, tetapi juga meliputi semesta batiniahnya, rohaniahnya. Itulah syariat yang kafah, sesuai al-Qur’an dan sunnah RasulNya Saw.
Semoga kita semua diberi pertolongan oleh Allah Swt untuk mampu melakoninya. Insya Allah, amin, amin, amin.
Wallahu a’lam bish shawab.
Jakarta, 22 Juli 2019