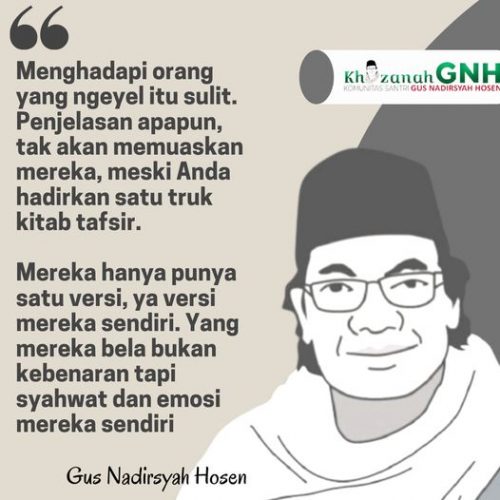Oleh Edi AH Iyubenu, Wakil Ketua LTN PWNU DIY
Siapa yang tidak menguasai ilmu Mantiq,
maka pendapatnya tidak terpercaya.
Imam Ghazali
Rasulullah Muhammad Saw menangis ketika turun surat Ali Imran ayat 190-191. Ayat tersebut bertutur tentang “ulul albab”: “Orang-orang yang mengingat Allah Swt dalam keadaan berdiri dan duduk dan pula berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini semua dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari siksa neraka.”
Usai menangis, beliau Saw berkata, “Sungguh celaka orang yang membaca al-Qur’an tetapi tidak memikirkannya….”
Dari riwayat yang saya nukil dari Prof. Quraish Shihab ini, kita sekarang kenal diktum yang mengkorelasikan agama (Islam) secara intensif dengan nalar akal. La dina liman la qala fih, tidak ada agama bagi orang yang tak berakal, misal.
Diktum ini juga memiliki sandarannya dari hadis Rasul Saw, yakni: “Akan muncul di akhir zaman sekelompok orang-orang muda yang pendek akalnya, mengucapkan sebaik-baik perkataan manusia. Mereka membaca al-Qur’an tetapi tidak sampai tenggorokannya. Mereka keluar dari agama seperti melesatnya anak panah dari busurnya.” (HR Muslim)
Istilah “pendek akal” selaras dengan ungkapan di atas, la dina liman la qala fih. Ini tertashih benar melalui sabdanya: “Mereka (karena pendek akal) keluar dari agama seperti melesatnya anak panah dari busurnya”. Lalu “mengucapkan sebaik-baik perkataan manusia” dapat kita sebut “ayat-ayat Allah Swt dan RasulNya”. Di al-Qur’an, juga ada ayat yang menyebut sejenis: “Apakah ada perkataan yang lebih baik dari perkataan Allah Swt?”
Di dalam al-Qur’an, tuturan tentang “berakal” selalu berpungkas pada sebutan ulul albab. Maka pertanyaannya kini: apa itu ulul albab?
Surat Ali Imran ayat 7 mengidentifikasi ulul albab sebagai: “Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min ‘indi rabbina, dan orang-orang yang rasikh dalam ilmu berkata ‘Kami beriman kepada semua kandungan al-Qur’an, semuanya berasal dari sisi Tuhan kami.”
Kata “ar-rasikh” arti lafalnya adalah ketiak (atau sesuatu yang sangat lekat), yakni (dalam konteks ini memaksudkan) orang yang kedalaman ilmunya telah mencapai “saripati” hingga ke bagian-bagian yang tersembunyi atau tak banyak orang umum yang menguasainya. Atau, dalam istilah Gus Mus, mereka adalah orang-orang yang telah malakah ilmunya (mbalungi, kata orang Jawa).
Rasikh berarti orang yang “telah selesai” dengan perkara-perkara teoritis lahiriah ilmu, dan nilai-nilai keilmuan yang luas dan dalam itu telah menyerap ke dalam hatinya menjadi world view atau welstanchauung. Untuk menggapai derajat ini, ia selibat lekat antara nalar rasional di satu sisi dan kejernihan rohani di sisi lain. Buahnya, dalam bahasa kita, sang bijak bestari.
Pengertian tersebut selaras betul dengan definisi ulul albab. Secara makna lafal, etimologis, ulul albab berasal dari kata al-labab, artinya intinya inti atau saripati. Ulul albab adalah orang yang memiliki keluasan dan kedalaman ilmu sampai pada derajat rasikh tadi, sehingga yang lalu mencahayai pikiran dan hatinya adalah saripati ilmu dan rohani. Buahnya adalah pula sang bijak bestari.
Pengertian ulul albab ini menarik sekali untuk diperbandingkan dengan sebutan al-Qur’an juga dalam surat Ali Imran ayat 7 pada kaum berilmu tetapi berbeda jauh buahnya dengan ulul albab, yakni orang-orang yang “fi qulubihim zaighun” (di dalam hatinya ada penyakit); mereka cenderung kepada “samar-samarnya ayat al-Qur’an” (mutasyabihat) untuk menghadirkan takwil-takwilnya.
Kaum ziaghun dalam konteks ini adalah juga para ahli ilmu. Bagaimanapun, kita mengerti, untuk bisa menakwil ayat-ayat dengan argumentasi kokoh dan meyakinkan, apalagi yang berkategori dzanniyah dalalah (samar makna hukumnya), dibutuhkan perangkat ilmu metodologis dan analisis ilmiah yang mapan.
Tapi mengapa Allah Swt membedakan dengan telak kelompok zaighun ini dengan kaum ulul albab, ar-rasikhun toh keduanya boleh jadi sama-sama berlandaskan pada ilmu yang sama, sebutlah Ushul Fiqh warisan Imam Syafii?
Akar pembeda antarkeduanya adalah adanya zaighun tadi atau tidak.
Boleh jadi ada dua orang yang sama-sama ahli ilmu al-Qur’an, hadis, dan Ushul Fiqh, tetapi produk nalar atau pemikiran keduanya berbeda telak semata dikarenakan yang pertama menyimpan tendensi-tendensi politis-ekonomis, tidak lillahi ta’ala, sedangkan yang kedua menakwil ayat yang sama dengan sepenuh ketulusan. Wajar bila hasil pemikirannya juga berbeda.
Kepada kelompok pertama inilah Allah Swt mengecam dan kepada kelompok kedua inilah Allah Swt memujinya.
Jadi, sampai di sini, pada hakikatnya memang bukanlah julangan ilmu itu sendiri yang menjadi tonggak keluhungan agama. Bukan!
Ilmu ‘sekadar’ metode analitik yang secara lahiriah kita butuhkan untuk meneliti, mengkaji, dan menyimpulkan kandungan ayat-ayar Allah Swt dan RasulNya Saw. Tetapi tepat di detik yang sama kontribusi ilmu kepada kualitas taqarrub ilaLlah sebagai tujuan utama kita berilmu sangat ditentukan oleh ada tidaknya zaighun di hati.
Di titik ini, kita bisa mengail kesimpulan pendek bahwa produk ilmu dan pemikiran dari ulul albab akan menghantar lebih dekat kepada Wajah Allah ‘Azza wa Jalla dan tidak berlaku sebaliknya.
Prototip ulul albab yang oleh al-Qur’an sendiri dirujukkan kepada “ar-rasikhun fil ilmi”, sang ahli ilmu bijak bestari, lalu menarik sekali pula untuk dikorelasikan dengan sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Rasul Saw berkata, “Aku adalah kota ilmu dan Ali bin Abi Thaib adalah pintu gerbangnya. Siapa yang hendak memasuki kotaku, maka ia harus melewati pintunya.”
Majas “kota” dalam hadis tersebut dapat kita maksudkan sebagai “ilmu yang menghantar kepada taqarrub ilaLlah”. Gerangan apa lagi yang lebih adiluhung dibanding tuntunan Rasul Saw? Tak ada.
Lalu, majas “pintu gerbang” dapat kita pahami sebagai washilah atau sanad atau jalan. Ya, jalan yang menjadi rujukan sumber ilmu yang kita pakai hari ini. Lahiriah dan batiniah, tentu saja.
Kendati memang pastinya bukan hanya Ali bin Abi Thalib sahabat terkemuka Rasul Saw yang luas ilmunya –toh kita banyak menukil riwayat Rasul Saw dari para sahabatnya yang lain seperti Abu Hurairah—hadis tersebut dapat kita jadikan petunjuk ihwal pentingnya merujukkan ilmu kita kepada sebuah sanad yang otoritatif.
Sejarah empat imam mazhab itu menarik betul untuk dibabarkan dalam konteks ini.
Ada satu nama besar dalam khazanah panjang tradisi keilmuan Islam ini yang selalu muncul di depan mata, yakni Imam Ja’far ash-Shadiq. Beliau rahimahuLlah adalah bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husein bin Ali bin Abi Thalib. Nama Imam Ja’far ash-Shadiq tersambung sangat dekat dengan pintu gerbang ilmu pengetahuan yang disebutkan Rasul Saw.
Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, berguru langsung kepada Imam Ja’far ash-Shadiq. Begitupun Imam Malik, pendiri Mazhab Maliki. Kemudian Imam Syafii yang beda zaman dengan Imam Ja’far ash-Shadiq, berguru kepada Imam Malik. Dan Imam Ahmad, pendiri mazhab Hanbali, berguru kepada Imam Syafii.
Saya kerap sekali merenungkan catatan sejarah ini.
Betapa nampaknya ketersambungan sanad ilmu para imam mazhab itu amatlah nyata dan dekat sekali kepada sang pintu gerbang kota ilmu pengetahuan itu, Ali bin Abi Thalib, sehingga tentulah semua ilmu mereka sangat otoritatif. Lahiriah dan batiniah.
Jika kemudian di antara para imam mazhab itu berbeda pendapat, pandangan, dan kesimpulan hukum Islam, ini bukanlah karena adanya fi qulubihim zaighun. Itu mustahil. Mereka adalah sebenar-benarnya ulul albab.
Lalu mengapa perbedaan pendapat itu tetap terjadi?
Ini sama sekali bukanlah anomali. Ini justru menunjukkan dengan jernih bahwa maqam ulul albab melazimkan belaka terjadinya perbedaan pendapat (khilafiyah) di satu sisi, yang mencerminkan sekaligus keragaman metode berpikir dan analisis masing-masing sebagai kerja ilmu. Jadi, khilafiyah, bukan khilafah, pada asalinya adalah realitas yang “diijinkan” oleh kota ilmu pengetahuan, yakni Rasul Saw. Dan tuturan tentang hal ini cukup banyak dalam khazanah hadisnya.
Akan tetapi, di sisi lain, tepat sekaligus, kamajemukan produk nalar tersebut tidak pernah dipentaskan oleh para pemuka mazhab ahli ilmu nan adiluhung itu jadi ketegangan dan konflik antarmereka dan apalagi antarumat. Perbedaan-perbedaan capaian nalar itu selalu berdenyar dalam rahmat yang meneduhkan semuanya tanpa kecuali.
Tepat di titik ini, kita bisa mendulang kesimpulan besar bahwa diktum la ‘ilma liman la aqla fih sebagai kebutuhan niscaya bagi dinamika pemikiran dan realitas hidup umat Islam di atas adalah (1) jenis ilmu yang dikembangkan secara rasional dalam kajian-kajian keislaman yang terus bergerak dinamis, yang (2) produknya secara alamiah memungkinkan terjadinya khilafiyah yang luas di antara umat Islam, tetapi (3) tidak pernah menyeret umat ke dalam jurang permusuhan dan perselisihan yang merusak (wala tafarraqu wakhtalafu min ba’di ma ja-a humul bayyinat) –untuk sekadar membedakan dengan istilah “kritisisme” sebagai spirit ilmu.
Tegasnya, secara terbalik, jika ada suatu produk hukum, takwil, yang ternyata mendesakkan konflik dan ketegangan sosial di antara umat, mau terkesan seotoritatif apa pun metodologi dan analisisnya, patut diwaspadi bahwa ia hanya produk pemikiran yang terlahir dari “fi qulubihim zaighun”, bukan “ar-rasikhuna fil ilmi” atau “ulul albab”. Ia dengan sendirinya tersapih dari taqarrub ilaLlah.
Mari mawas diri selalu dalam memilah keduanya yang secara lahiriah sama-sama berjubahkan ilmu. Semoga kita semua senantiasa dibimbing oleh Allah Swt dalam menggali dan mengembangkan ilmu yang bisa makin mendekatkan diri kepadaNya semata. Amin.
Wallahu a’lam bish shawab.
Jogja, 27 Agustus 2019