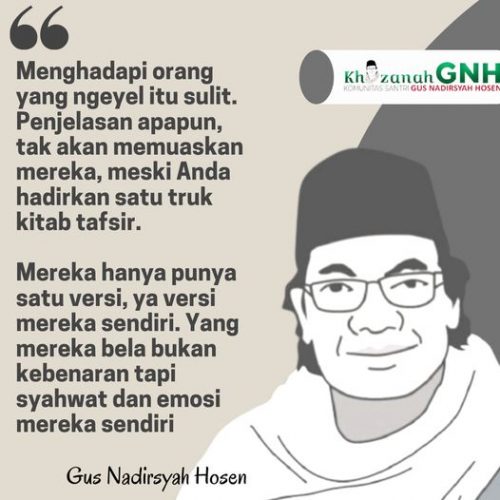Ibuku kepingin naik haji
Setiap orang pasti pingin hidup BAHAGIA dunia akhirat. Bahasa santrinya Fiiddunya khasanah wafil aakhiroti khasanah. Kalau sempurna tambah waqinaa ‘adzaabannaar. Terjaga dari siksa neraka.
Kebahagiaan hidup di dunia ini bersifat relatif.Tidak bisa diukur dengan Materi harta kekayaan, pangkat jabatan, gelar akademik dsb. Demikian pula ukuran kesuksesan orang, tentu ukurannya tidak seperti itu.
Orang kaya yang tidur di hotel mewah dengan tarif lebih 900 $ per malam. Bisa kalah bahagia dengan sopir becak yang tidur di atas becaknya di pinggir jalan sambil memeluk radio baterai mendengarkan siaran wayang.
Sering kalau ngobrol tentang resep hidup bahagia, saya biasanya ngomong: hormati dan bahagiakan orang tua semampumu. Dan jika keduanya sudah tiada, rajinlah mendoakannya.
Saya ngomong seperti itu tentu ada dasarnya. Di samping dalil-dalil agama, juga fakta dan realita kehidupan yang saya temui. Orang yang menurutku bahagia dan yang tidak atau belum. Ternyata tergantung kepada Birrul Waalidain (baca… Aku Dianggap Orang Pintar (3)…).
Kenapa Allah “menggandengkan” kewajiban menghamba kepada Nya dengan kewajiban berbakti kepada kedua orangtua, seperti dalam Al Israa 23: “Allah telah menetapkan agar kalian tidak beribadah melainkan kepada Nya, dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orangtua”.
Dalam ayat yang lain untuk perintah berbuat baik kepada kedua orangtua Allah memakai lafadz “washsho” wasiat, kok tidak “Amaro, kataba, farodho” atau yang lain…(Al Ahqoof 15), ini menunjukkan urgensinya Birrul Waalidain.
Sangat banyak hadis Nabi SAW berkaitan dengan Tarhib dan Targhib, ancaman dan anjuran untuk berbakti kepada Bapak Ibu. Dan sayapun berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkannya.
Sekitar Tahun 2003. Saat mau keluar kota saya menawari Ibuku yang sudah sepuh (hampir 70 Th) mau minta oleh-oleh apa? Ibu menjawab tidak pingin apa-apa, saya desak terus : “Lha Ibu sebenarnya apa yang dipingini?” Sambil menatapku iba, Beliau menjawab punya keinginan tapi nggak mungkin terlaksana yaitu pingin melihat Ka’bah langsung, alias pingin Naik Haji. Memang saat itu kondisi ekonomi keluarga belum memungkinkan.
Jujur semenjak Ibu ngendiko seperti itu saya jadi sulit tidur. Namun ada celah kemungkinan yaitu saya harus menjual satu satunya Mobil yang baru saja kubeli, baru satu bulan.
Istriku kuajak musyawarah terbuka. Alhamdulillah ia full setuju, bahkan mengingatkan dulu saat nikah ya ndak punya apa-apa. Sekalian mendoakan pasti Alloh akan siapkan gantinya, langsung kucium kening Isteri yang bau minyak angin.
Kalau Ibu tahu saya jual mobil pasti beliau tidak berkenan. Karena di mata Ibu, saya anak yang paling prihatin sejak kecil dari sepuluh bersaudara. Sampai nikahpun saya beaya sendiri tanpa membebani orang tua.
Maka saya lobbi semua saudaraku tentang keinginan haji Ibu itu. Hasil kesepakatan nanti saya yang matur Bapak Ibu bahwa beaya Haji itu dipikul sepuluh bersaudara. Walau formalitas ada yang iuran cuma ala kadarnya bahkan ada yang cukup doa.
Setelah mobil laku, diam-diam KTP dan Kartu Keluarga Bapak sama Ibuku saya “curi” untuk daftar calon Haji, maksudku untuk surprise. Kedua orangtuaku baru tahu setelah ada Panggilan Cek Kesehatan di Puskesmas, itupun tahunya setelah pulang dari Puskesmas saya ditanya kok tadi disuruh tanda tangan di Buku Hijau itu buku apa? Barulah saya berterus terang Bahwa Bapak Ibu sudah harus persiapan untuk berangkat Haji.
Kulihat mata Ibuku berkaca kaca. Sempat Beliau bertanya, uangnya dari mana? Saya jawab dari semua putra putri Bapak dan Ibu sepuluh orang. (Alkhamdulillah sampai Bapak Ibuku meninggal Beliau berdua tidak tahu kalau beaya Haji itu dari uang jual mobil kesayanganku).
Sehari menjelang berangkat haji, saya pulang ngaji sekitar jam satu malam pinjem mobil kakakku. Capek ngantuk jadi satu. Begitu mau berbaring, bapakku minta diantar ziarah ke makam kakek yang jaraknya cukup jauh. Saya tidak protes, padahal banyak saudaraku yang mestinya lebih layak disuruh. Tetapi mungkin bapakku menganggapku yang “iurannya” paling sedikit, maka sayalah yang disuruh.
Sampai di makam hampir jam dua malam. Begitu Bapak saya antar masuk makam, saya masuk ke mobil mau istirahat. Tapi Bapak nyamperin lagi supaya ikut masuk makam, sayapun nurut tanpa protes, padahal tengah malam, dingin gerimis campur capek dan ngantuk. Lagian nyamuk kuburannya segedhe jangkrik. Demi orang tua kujalani dengan ikhlas. Mumpung masih mampu.
Kisah ini sudah saya ceritakan kepada anak-anakku. Entah direspon atau tidak saya nggak mikir. Yang penting saya sudah mengajari anak-anak dengan contoh nyata. Urusan difahami kemudian ditiru. Semua saya serahkan kepada Allah SWT.
Sempat pula saya bercerita, kira-kira tiga bulan sebelum Ibu meninggal. Aaya tergesa gesa mau berangkat mengajar, Ibu menyuruhku membeli singkong rebus yang tidak pakai santan. Langsung kukerjakan, tanpa protes walau sudah ditunggu jamaah. Bagiku nuruti Ibu harus didahulukan.
Keluar masuk beberapa pasar dan bikin heboh pasar karena lebih 50 tahun tidak pernah masuk pasar hanya mencari singkong rebus seharga dua ribu rupiah. Itupun habis dapet sempat menyuapin Ibu singkong yang diinginkan walau cuma dua suapan. Air mataku hampir netes nulis ini. Karena itu suapan yang terakhir sebelum Beliau wafat. Tidak sebanding dengan suapan Ibu kepadaku yang tidak terhitung jumlahnya.
Allohummaghfir lahuma… Ya Allah… Ampunilah dosa Ibu Bapakku… Kasihanilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka berdua mengasihi aku sedari kecil…
Alkhamdulillah yang jelas… Dalam sisa hidup ini, ada rasa lega dalam hati bahwa Ibuku sudah sempat melihat Ka’bah secara langsung sesuai yang Beliau inginkan sebelum meninggalkanku selama-lamanya dan mobil yang dulu kujual sekarang malah bertambah banyak, karena saya makelar mobil…
Tinggal harapan yang tersisa adalah semoga saya bisa berkumpul kembali dengan Bapak Ibuku di surga nanti…
Aamiin Ya Robbal Alamiin.
Penulis: KH Henry Sutopo, Krapyak Yogya, santri KH Ali Maksum. (*Tulisan ini diambil dari buku Catatan Seorang Santri karya Henry Sutopo hal. 311).