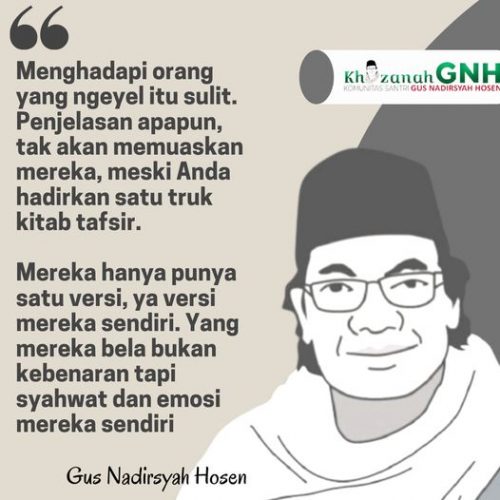Oleh Edi AH Iyubenu, wakil ketua LTN PWNU DIY.
Memahami Sensitivitas Amanat dan Praktik Amar Ma’ruf Nahi Munkar
Apakah amar ma’ruf nahi munkar merupakan kewajiban (taklif) kepada setiap orang Islam? Dan, bagaimana seyogianya kita memahami dan menyikapi amanat amar ma’ruf nahi munkar di hadapan suatu kemungkaran atau kemaksiatan?
Ada banyak ayat dalam al-Qur’an yang bertutur tentang amanat amar ma’ruf nahi munkar ini. Anda bisa mencarinya sendiri dengan mudah. Saya hanya akan mengutipkan dua ayat yang paling mewakili krusialitas dan sekaligus sensitivitas amanat amar ma’ruf nahi munkar tersebut, yakni surat Ali Imran ayat 104-105:
“Dan hendaklah sebagian dari kalian menjadi golongan yang menyeru kepada kemakrufan dan mencegah dari kemungkaran (amar ma’ruf nahi munkar), mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kalian menyerupai golongan orang yang berpecah-belah dan bermusuhan setelah turunnya keterangan ini (al-Qur’an), mereka itulah golongan orang yang ditimpa azab yang pedih.”
Ayat pertama (104) menyerukan SEMUA kita untuk ber-amar ma’ruf nahi munkar; ganjaran yang dijanjikan Allah Swt adalah “menjadi orang-orang yang beruntung”. Luar biasa! Namun jangan pisahkan ayat 104 tersebut dengan ayat berikutnya, 105, yang tepat seketika men-takhshish (mengkhususkan –ini termasuk yang dimaksud dalam Ushul Fiqh sebagai tafsir al-Qur’an bi al-Qur’an) lingkup pertama (waltakun, semua kalian) menjadi lingkup lebih khusus (minkum, sebagian dari kalian).
Hasilnya adalah amar ma’ruf nahi munkar terspesialisasikan hanya untuk (1) sebagian dari kalian (minkum) dan (2) jangan memicu perpecah-belahan dan permusuhan.
Dua takhshish ini dengan sendirinya menisbatkan syarat kepada mereka yang hendak memasuki lingkup pertama (kelian ber-amar ma’ruf nahi munkar). Atas dasar ini, kerap dikatakan bahwa amanat amar ma’ruf nahi munkar bukanlah fardhu ‘ain (kewajiban yang berlaku kepada semua orang), tetapi fardhu kifayah (kewajiban yang berlaku kepada sebagian orang).
Kecenderungan menghukumi kifayah kepada amar ma’ruf nahi munkar sepintas mudah sekali untuk dimengerti demi melihat beratnya dua syarat tersebut: (1) sebagian orang (yakni hanya orang-orang yang memiliki hak hukum macam ulil amri dan para ahli ilmu dan suri teladan macam ulama), dan (2) mampu bersikap makruf pula alias bijaksana (tidak memicu perpecah-belahan dan permusuhan).
Musykillah semua orang lalu mampu memikul dua syarat tersebut, bukan? Akan tetapi, faktanya, mengapa justru kebanyakan kita nampak dengan sengaja meletakkan diri memikul amanat tersebut, menyatakan seolah diri mampu memikul dua syarat berat tersebut?
Mari saya kutipkan dulu hadis sahih ini: “Dari Abi Sa’id al-Khudri Ra ia berkata: Aku telah mendengar Rasulullah Saw bersabda: “Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya, jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya, dan jika tak bisa, ubahlah dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman.” (HR Muslim).
Hadis yang amat populer ini menjadi sumber naqli yang paling sering kita dengar dipakai sebagai landasan utama menyokong gerakan amar ma’ruf nahi munkar bagi semua orang (lalu seolah ia adalah fardhu ‘ain). Bahkan, lebih jauh lagi, hadis tersebut (ini titik paling krusialnya) sekaligus dijadikan dasar pembenar bagi tindak-tindak tegas dan keras (bahkan kekerasan macam sweeping, pembubaran, dan pengrusakan sesuatu atau aktivitas kelompok lain). Penggalan “falyughayyir biyadih, ubahlah dengan tangan” dipekikkan dengan begitu lantang –seolah itu belaka makna utuh ajaran Rasul Saw tersebut.
Lebih terasa mantap lagi, sikap keras dan tegas ini ditashih sebagai ekspresi “iman yang kuat, tinggi, dan paripurna” (berbeda dengan sikap diam atau sekadar berdoa dalam hati yang disebut “selemah-lemahnya iman”). Lebih-lebih terasa heroik lagi, sikap ini dikorelasikan dengan “jihad fi sabiliLlah”. Sempurnalah sikap ini diidolakan tanpa tedeng aling-aling. Catatan aksi-aksi keras sejumlah ormas Islam menjadi bukti nyata postulasi tersebut.
Secara metodologi Ushul Fiqh, keberadaan hadis tersebut jelas bisa diposisikan sebagai mekanisme tafsir al-Qur’an bi al-hadis (ini pun bagian dari kaidah ilmu Ushul Fiqh). Umum kita menyebutnya tafsir bi al-ma’tsur –termasuk mekanisme pertama tadi, tafsir al-Qur’an bi al-Qur’an.
Kini mari kita kaji lebih mendalam hadis tersebut di hadapan ayat 104-105 dari Ali Imran tadi.
Pertama, adanya lafal “minkum” (sebagian dari kalian) pada ayat dan hadis tersebut menandakan bahwa tugas amar ma’ruf nahi munkar seyogianya selalu didudukkan sebagai kewajiban bagi sebagian kita saja yang tepat memikul amanat hukum atau kompetensi keilmuan yang pantas. Ia karenanya bersifat fardhu kifayah.
Orang mungkin saja cenderung menakwilnya tetap sebagai “semua kita” (berhenti di lafal “waltakun”), dengan dalih bahwa ayat dan hadis tentulah diturunkan kepada semua orang dan berlaku begitu pula. Mustahil ajaran Islam berlaku tebang pilih. Belum lagi bila dipahami sebagai cerminan dari komitmen imani hamba kepada Allah Swt dalam menjalankan perintahNya. Bagaimana mungkin komitmen imani bersifat tebang pilih?
Pandangan demikian pada dasarnya bisa saja kita terima. Bisa saja memang seseorang yang pada hakikatnya belum punya kompetensi untuk menjadi bagian dari “minkum” itu (sebutlah secara keilmuan), lalu demi senarai iman di hatinya, ia memanggil dirinya untuk merapat ke dalam barisan aksi amar ma’ruf nahi munkar itu. Sikap begini bisa kita pahami.
Hanya saja, berikutnya, sikap rohani personal tersebut tetap wajb untuk mematuhi dengan saksama syarat praksis berikutnya: jangan memicu perpecah-belahan dan permusuhan.
Sebagai analogi, kita tahu bahwa sedekah itu amal yang utama. Semakin banyak semakin baik. Akan tetapi, dalam praksisnya, kita pun tahu bahwa kewajiban menafkahi keluarga lebih utama dan mesti didahulukan ketimbang dorongan bersedekah sebanyak-banyaknya. Bila asas kedua ini diabaikan, lalu timbul kezaliman kepada anggota keluarga, amal sedekah itu bisa berakhir dengan ketercelaan. Bukan sedekahnya yang tercela, tetapi dampaknya yang tidak dikelola dengan bijaksana.
Persis sekali dengan dorongan untuk memikul amanat amar ma’ruf nahi munkar itu; jika dampaknya meletuskan perpecahan dan permusuhan, maka gerakan amar ma’ruf nahi munkar tersebut menjadi tercela.
Kedua, lalu, bagaimana korelasi hal tersebut (penerapan syarat kedua) dengan maksud hadis “hendaklah ubah dengan (1) tangan, (2) lisan, dan (3) hati yang selemah-lemahnya iman”?
Sebelum melanjutkan ulasan ini, saya ingin mengajak Anda mencermati tuturan lawas G.W.F. Hegel perihal dialektika. Bukan, mohon maaf, bukan maksud saya menukil Hegel di sini untuk meng-Hegelian-kan kajian dalil ini. Bukan!
Saya hanya bermaksud untuk menunjukkan dua pilar yang dimaksudkan Hegel dalam mekanisme proses dialektika tesis-antitesis-sintesis itu yang saya pikir koheren untuk kita jadikan dasar pertimbangan, yakni: (1) dilekatika mestilah dijalankan dalam mekanisme rasional, dan (2) dialektika mestilah dipahami sejak dini akan selalu berdenyar dalam “pusaran konflik”.
Mari kini kita coba pakai “nasihat Hegel” ini pada konteks amar ma’ruf nahi munkar dari ayat dan hadis tadi.
Pilar rasional sungguh menjadi sangat vital untuk digenggam selalu dalam memikul amanat amar ma’ruf nahi munkar. Ya, selalu!
Aspek rasionalitas ini dengan sendirinya menuntut kita untuk menakar dan menimbang dengan teliti dan saksama potensi risiko-risikonya, baik atau buruknya. Pemahaman rasional yang detail terhadap suatu gerakan amar ma’ruf nahi munkar niscaya bersitaut dengan usaha pengikisan paling dalam terhadap potensi risiko negatifnya dan pula pengerekan paling tinggi terhadap potensi kebaikannya. Ini pertama.
Berikutnya, yang kedua, suatu praktik hidup, sebutlah kemungkaran dan kemaksiatan, yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang tentu saja akan bersikap resisten terhadap gerakan apa pun yang menyergahnya, mengantitesisnya, termasuk amar ma’ruf nahi munkar yang notabene baik –mau secara lisan, apalagi aksi tangan.
Konsekuensi resisten ini adalah khittah “pusaran konflik” yang mesti dipetakan dengan jernih secara rasional untuk dihitung sedetailnya hingga khittah “risiko konflik” dari antitesis Anda (amar ma’ruf nahi munkar) terhadap tesis kemungkaran itu bisa bermuara pada sintesis yang paling maslahat –secara rohani dan sosial pada tujuan amar ma’ruf nahi munkar maupun pihak yang dimasuki gerakan tersebut.
Berdasar peta Hegelian ini, kini kita bisa memahami dengan lebih jernih bahwa prinsip “jangan memicu perpecah-belahan dan permusuhan” sebagai “batas tertinggi yang tak boleh dilampaui agar kita tak menjadi golongan yang melampaui batas yang dilarangNya” dalam suatu gerakan amar ma’ruf nahi munkar mestilah dikalkulasikan secara rasional dalam tiga opsi langkah yang disenaraikan hadis tersebut: (1) dengan tangan, (2) dengan lisan, atau (3) dengan hati atau doa.
Menegakkan kebaikan untuk mengubah kemungkaran dan kemaksiatan melalui tangan hanya paling rasional untuk dipangku oleh para pemegang otoritas kekauasaan. Alias ulil amri. Sebab hanya merekalah yang memiliki hak hukum legal-formal dan sekaligus alat paksa yang lengkap yang dilindungi hukum.
Simbol “tangan” kiranya tepat betul untuk dimaknai “penguasa/pemimpin” legal-formal. Sebutlah polisi di negeri ini. Jika ada praktik perjudian, polisi berhak secara hukum dan kekuasaan untuk menindaknya dengan tegas sesuai undang-undang yang berlaku. Sikap tegas, bahkan keras, polisi ini sahih secara hukum formal dan tidak akan memicu perpecah-belahan dan permusuhan, tentu saja.
Tapi akan lain cerita bila ormas yang melakukan penindakan itu. Tiadanya hak hukum legal-formal pada dirinya bisa berakhir dengan kekacauan, perkelahian, kerusakan, dan pertikaian. Tindakan “pakai tangan” yang tidak pada haknya ini dalam konteks syarat amar ma’ruf nahi munkar di atas dengan sendirinya menjadi tak dibenarkan.
Kaidah Ushul Fiqh telah meletakkan nasihatnya: “la yuzalu al-dharar bi al-dharar, tidak boleh suatu keburukan diubah dengan cara keburukan lainnya” dan “dar-ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih, menghindarkan risiko suatu keburukan harus didahulukan daripada mengejar tercapainya suatu kebaikan.”
Bisa ditambahkan di sini bahwa amar ma’ruf nahi munkar dengan tangan ini juga relevan dilaksanakan di dalam rumah kita sendiri dengan asumsi sederhana “dalam genggaman kekuasaan” kita –misal dalam mendidik anak-anak. Namun, tentulah, praktik “dengan tangan” di dalam rumah pun mestilah dijalankan dengan spirit kebijaksanaan pula. Niscaya kita semua bisa memahaminya dengan sangat baik.
Lalu amar ma’ruf nahi munkar dengan lisan alias nasihat (al-Qur’an menyebutnya mau’idhah hasanah). Orang yang memberikan nasihat-nasihat baik wajib menyumberkan kepada fondasi keilmuan yang luas dan mendalam, sekaligus kejernihan hati. Ia mesti rasional dan rohaniah sekaligus. Tujuannya tiada lain adalah agar nasihat-nasihatnya bertahta kebijaksanaan. Kebijaksanaan inilah yang akan menggerus risiko-risiko “pusaran konflik” amar ma’ruf nahi munkar-nya.
Maka, peran “amar ma’ruf nahi munkar dengan lisan” ini kiranya hanya pantas diampu oleh para alim, saleh, ulama, guru, dan tokoh masyarakat –dengan asumsi semua kelas sosial dan agama ini memang memiliki kompetensi ilmu yang mumpuni dan pula kebijaksanaan.
Ironisnya, kita hidup di zaman yang makin abu-abu begini. Ada begitu banyak orang yang berpenampilan guru agama, kiai, ulama, fasih betul menukil ayat dan hadis serta qaul ulama, bahkan secara struktural menduduki jabatan organisasi keislaman yang luar biasa, akan tetapi gagal mementaskan sikap dan nasihat bijaksana dalam syiar-syiarnya.
Saya kira berharga sekali di sini untuk merenungkan ayat ini: “Innama yahsyaLlaha min ‘ibadihi ulama, sesungguhnya yang akan takut kepada Allah Swt dari hamba-hambanya adalah para ulama.”
Rasa takut kepada Allah Swt, di antaranya, berlandas kepada keyakinan yang hakiki di dalam hati bahwa Allah Swt Maha Tahu apa pun yang berdenyut di dalam hati. Keyakinan yang haq begini otomatis akan menghantar sosok tersebut kepada sikap murni, tulus, dan semata lillahi ta’ala. Ia steril dari tendensi-tendensi nafsu politis, ekonomis, sosial apa pun.
Ini letak krusialnya.
Di tangan orang yang ahli ilmu, tapi hatinya tidak takut kepada Allah Swt, boleh jadi senarai ilmunya malah dijadikan kendaraan politis untuk meruahkan ambisi-ambisinya. Pengalaman politik elektoral di negeri ini kiranya telah memperlihatkan dengan telanjang adanya praktik-praktik politisasi agama yang adiluhung ini hanya untuk merebut suara-suara politik ambisius itu. Ayat-ayat Allah Swt dan hadis-hadis Rasul Saw dipelintir sedemikian teganya tanpa rasa takut sama sekali kepada hukum Allah Swt sampai pada derajat yang sangat mengenaskan dan menyesakkan dada….
Gerakan amar ma’ruf nahi munkar dengan lisan ini, sekali lagi, hanya layak diampu oleh para alim saleh ulama yang benar-benar lillahi ta’ala belaka. Melalui keluasan dadanya, kita akan menyaksikan senara-senarai nasihat yang sejuk, teduh, luhur, ngemong, bijaksana, sehingga risiko ketegangan sosial dari “pusaran konflik” amar ma’ruf nahi munkar-nya menjadi sangat terantisipasi dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, ceramah amar ma’ruf nahi munkar apa pun oleh siapa pun, sekalipun diuraikan dengan lidah berkumur-kumur takbir, ayat, dan hadis, jika mengobarkan perselisihan dan perseteruan, tanda tiadanya nilai bijaksana di dalamnya, ia seketika dapat dinyatakan bukan amar ma’ruf nahi munkar yang haq selayaknya seorang ulama yang otoritatif.
Berikutnya, amar ma’ruf nahi munkar dengan hati (doa). Inilah kiraya ruang terluas yang bisa kita miliki bersama, semuanya. Inilah kiranya ruang amar ma’ruf nahi munkar yang bisa dinyatakan sebagai kewajiban semua muslim (fardhu ‘ain).
Ruang pertama (dengan tangan) dan ruang kedua (dengan lisan) yang khusus, yang bukan hak dan milik kita, biarkanlah tetap di sana; jangan dipaksa untuk kita genggam agar tak menjerumuskan kita kepada kezaliman baru. Cukuplah kita menggenggam ruang hati ini –kecuali bila pada suatu masa kita beranjak dengan pantas dan rasional ke ruang pertama atau kedua tadi.
Tapi, bukankah itu selemah-lemahnya iman?
Betul. Maksud “selemah-lemahnya iman” tersebut kiranya bisa saja kita pahami sebagai “motivasi rohani” untuk mengikhtiarkan diri kita bisa beranjak ke jenjang dakwah dengan lisan atau dengan tangan. Kita yang sekarang awam begini bila di suatu masa depan tampil ke panggung khutbah bisa saja menjadikan “panggung publik” tersebut sebagai jalan amar ma’ruf nahi munkar kita –tentulah jangkauanya lalu menjadi lebih luas lagi. Itu isyarat bahwa kita telah beranjak dari “selemah-lemahnya iman” tadi. Sudah pasti, ini pun mestilah dibingkai dengan spirit ilmu dan kebijaksanaan tadi.
Saya teringat doa terkenal Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri Mazhab Hanbali, ketika beliau rahimahuLlah menyaksikan suatu kemungkaran dan kemaksiatan di depan mata: “Allahumma kama farrahtahum fi al-dunya farrihhum fi al-akhirat, ya Allah sebagaimana Engkau membahagiakan mereka di dunia, bahagiakanlah mereka di akhirat.”
Mustahil Anda akan berani mengatakan kualitas iman dan komitmen rohani beliau rahimahuLlah adalah “selemah-lemahnya iman”, apalagi lalu dibandingkan dengan iman Anda sendiri yang menggerakkan amar ma’ruf nahi munkar dengan lisan ataupun tangan, bukan?
Cara beliau memilih mendoakan (amar ma’ruf nahi munkar dengan hati) terhadap suatu praktik kemungkaran dan kemaksiatan yang tidak dijalankannya dengan “tangan dan lisan” mengisyaratkan betapa dalamnya kebijaksanaan beliau dalam mendudukkan amar ma’ruf nahi munkar di hadapan “jangan berpecah-belah dan bermusuhan” itu. Tentulah doa dan kebijaksaan itu telah mengalir melalui mekanisme nalar ilmu yang rasional dan kesadaran atas “pusaran konflik” yang sedemikian rupa. Siapa meragukan kompetensi keilmuan beliau?
Lalu coba perhatikan lagi dengan saksama bunyi doanya. Ya, sekali lagi. Terlihat jelas pilihan doa adiluhung penuh cinta dan welas asih tersebut memaklumkan kedalaman rohaninya yang luar biasa; jauh dari nuansa kebencian dan kesombongan.
Seyogianya memang mesti demikianlah amanat amar ma’ruf nahi munkar kita jalankan di antara tiga bentuk cara yang dituturkan Rasul Saw tersebut: tidak boleh ada rasa kebencian, kejijikan, apalagi kesombongan diri.
Maka boleh jadi pada suatu titik mendoakan suatu praktik kemaksiatan dan kemungkaran agar nanti dikembalikanNya ke jalan kebaikan sesuai syariatNya dengan rohani munajat yang tulus, bening, dan penuh cinta dapat dinyatakan sebagai isyarat bagi kualitas kejernihan iman, ilmu, dan amal diri kita. Dengan perspektif demikian, bisa saja suatu praktik kemaksiatan yang terjadi di depan mata, yang tak terjangkau oleh tangan dan lisan kita, menjadi termaknai sebagai ilhamNya kepada rohani kita: seberapa kita menuai hikmah dari peristiwa tersebut dan seberapa kita tetap mampu berakhlak selayaknya hambaNya yang karim.
Semoga bermanfaat.
Wallahu a’lam bish shawab.
Jogja, 30 Agustus 2019