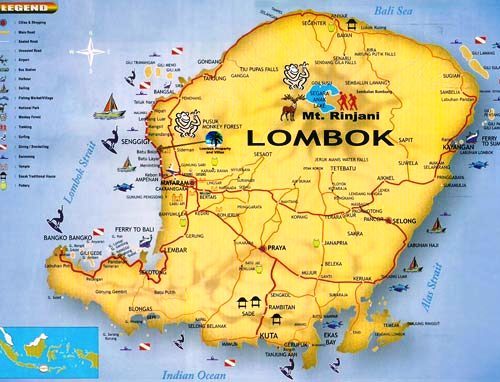Oleh Edi AH Iyubenu, Esais dan Wakil Ketua LTN PWNU DIY. @edi_akhiles FB: Edi Mulyono
Salah satu tema perbedaan pendapat di antara kita perihal amaliah keseharian ialah dzikir (doa) berjamaah usai shalat. Apakah boleh atau tidak?
Di suatu pengajian Nuzulul Qur’an beberapa tahun lalu, saya mendengar langsung ustadznya menanyakan kepada jamaah, apakah masjid ini telah melakukan dzikir sendiri-sendiri secara sirr (tersembunyi, diam)? Jamaah menjawab, “Iya.”
Ustadz tersebut menyahut dengan senang, “Alhamdulillah, itulah yang sesuai tuntunan Rasulullah Saw.”
Ia lalu menukil sebuah hadits: Rasulullah Saw keluar rumah dan menuju para sahabat yang sedang berkumpul lalu bertanya, “Kenapa kalian duduk-duduk?” Mereka menjawab, “Kami duduk untuk berdzikir dan memuji Allah Ta’ala.” Beliau Saw berkata, “Sesungguhnya Jibril mendatangiku dan mengabarkan kepadaku bahwa Allah membanggakan kalian kepada malaikat.” (HR Muslim).
Lalu ustadz tersebut juga mengutip ucapan (atsar) Abdullah bin Mas’ud yang mendatangi sekelompok orang di masjid yang sedang berdzikir bersama dan beliau berkata, “…Demi Dzat yang jiwaku ada tanganNya, kalian ini berada di atas agama yang lebih baik dari agama Muhammad ataukah kalian sedang membuka pintu kesesatan?”
Kesimpulannya ialah dinyatakan bahwa dzikir (doa) bersama-sama tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Saw sehingga siapa yang melakukannya jatuh pada bid’ah, salah, dosa, maka ia haram. Maka harus dihindari.
Sebagai peserta pengajian, tentu saja tak etis saya protes. Saya diam, meski tak setuju.
Begini, mari kita uraikan.
Soal dalil pertama yang dinukil tersebut, jelas bahwa hadits tersebut sama sekali tidak memberikan keterangan adanya larangan dzikir (doa) bersama. Tidak ada petunjuk khusus di dalamnya.
Soal ucapan Abdullah bin Mas’ud yang menerakan larangan jelas dzikir bersama itu, telah banyak penyampaian yang memperlihatkan bahwa riwayat atsar tersebut ternyata lemah.
Lepas dari kendala periwayatan tersebut, di sini saya nukilkan dua dalil saja, yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim: Dari Ibnu Jarir Ra ia berkata, ‘Amr telah berkata kepadaku bahwa Abu Ma’bad mengabarkan kepadanya bahwa Ibnu ‘Abbas Ra berkata, “Mengeraskan suara pada dzikir setelah shalat wajib telah ada di masa Nabi Saw.” Ia terus mengatakan, “Aku mengetahui bahwa shalat telah selesai dengan mendengar hal itu.”
Dalil kedua juga dari riwayat sahih Bukhari dan Muslim, “Kami dahulu mengetahui berakhirnya shalat Rasulullah Saw melalui suara takbir.”
Saya juga pernah membaca bantahan atas kebolehan dzikir (doa) berjamaah yang didasarkan pada ayat: “Berdzirkirlah (ingatlah) kepadaKu, niscaya Aku akan mengingatmu….” Ayat tersebut menggunakan dhamir jama’, artinya ‘Berdzikirlah kalian”. Pembantah itu menyatakan bahwa dhamir jama’ tersebut sama sekali tak terkait dengan makna boleh bagi orang-orang yang secara sengaja berkumpul, berjamaah, lalu berdzikir bersama. Ayat tersebut bukan berarti memerintahkan jamaah muslimin untuk berdzikir bersama-sama.
Pembantah itu menganologikan bantahannya dengan perintah dalam ayat “Janganlah kalian mendekati zina….” yang tidak logis untuk diasumsikan larangan zina berjamaah –lalu boleh zina sendiri-sendiri.
Baiklah, bantahan tersebut masuk akal. Memang dalam ayat al-Qur’an banyak sekali ayat yang berifat seruan jama’ yang boleh jadi makna yang ditunjuknya ialah kaum muslimin bukan dalam artian suatu jamaah di suatu masjid. Ayat tersebut memang tidak menunjuk pada perintah untuk berdzikir berjamaah. Tapi ingat, ayat tersebut pun tidak menunjuk pada larangan untuk berdzikir berjamaah.
Dan tepat dengan logika yang sama, hadits tentang para sahabat yang berkumpul di atas itu juga tidak berarti relevan dijadikan landasan perintah bagi dzikir sendiri-sendiri. Artinya, tidak adanya keterangan jelas dalam dua dalil tersebut (ayat dan hadits) tidak bisa serta merta diklaim sebagai pembenar bagi kebolehan dzikir berjamaah atau sebaliknya. Keduanya berada di posisi yang terbuka kemungkinan pemahaman.
Justru pada dalil kedua yang diriwayatkan Bukhari Muslim tentang pernyataan Ibnu ‘Abbas Ra itulah yang paling terang maksudnya. Dari riwayat tersebut, sebenarnya telah jelas bahwa sah-sah saja dzikir berjamaah itu. Ia memiliki rujukan yang sahih dari penyampaian Ibnu ‘Abbas Ra tersebut. Namun, mari kita bijak pula pada saudara-saudara yang menafsir sebaliknya, ya.
Dan mohon maaf, di sini saya tak juga berfokus pada adu dalil.
Saya lebih memilih untuk menggunakan pendekatan rasional, yakni pandangan-pandangan yang lebih mendalam lagi yang saya kira penting betul untuk dinyatakan dan dipertimbangan di sini dalam menimbang amaliah dzikir sendiri-sendiri atau berjamaah yang akan kita lakoni.
Pertama, hukum (yang ghairu mahdhah) itu mestinya tidak semata kita pahami sebagai hal-hal yang ada dalil sharihnya (terang). Jangan tergesa mengklaim pandangan ini bid’ah, lalu divonis jelek, dosa, dan haram. Sebentar.
Saya bandingkan dengan cara begini: bolehkah berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia?
Jelas boleh. Apa masalahnya?
Nampak sekali bahwa apa-apa yang sekalipun tidak ada dalil sharihnya (terang) sepanjang tidak terkait dengan ibadah-ibadah mahdhah, bersifat mubah. Ia boleh dilakukan dengan pelbagai cara. Hukum dzikirnya tetap sunnah, namun cara berdzikirlah yang kemudian memiliki kebebasan.
Kedua, pembandingan dzikir sirr macam yang dilakukan para sahabat (umpama benar demikian, dengan mengikuti atsar Abdullah bin Mas’ud) dengan kita yang muslimin Indonesia yang sama sekali ‘asing’ dengan ruh bahasa Arab jelas tidak bisa disejajarkan begitu saja. Para sahabat yang bahasa ibunya adalah bahasa Arab jelas berbakat-nyambung betul pemahaman, pemaknaan, dan perasaannya pada bahasa doa yang dilantunkan. Sekalipun secara sirr.
Bandingkan dengan kita yang kesehariannya berbahasa Indonesia, atau pun bahasa Jawa, dapat dibayangkan bagaimana berjaraknya kita dengan ruh bahasa Arab itu. Ketika seorang Jawa berdoa dengan bahasa Jawa, misal, sudah pasti resapan ucapan, makna, dan rohaninya terangkut semua.
Sedikit saya singgung tentang makna bahasa pada kehidupan kita, betapa kita tahu bahwa bahasa bukanlah sekadar alat komunikasi. Bahasa adalah dasein kita, yang dengannya dan di dalamnya kita hidup. Bahasa adalah cermin dari cara kita memaknai dan sekaligus mengekspresikan keberadaan hidup kita dengan keseluruhan esensinya.
Sebagai bukti, orang Jawa seketika mendapatkan feel yang mendalam di dalam batinnya ketika menyebut temannya dengan kata ‘Lur’ (dulur). Ini beda betul situasi batinnya jika orang Jawa menggunakan kata ‘bro’ atau apalagi ‘akhi’. Bahasa sungguh benar-benar adalah dasein kita dan sekaligus cara ungkap kita pada dasein kita.
Maka, sekali lagi, menyejajarkan feel kita dalam berbahasa Arab dengan para sahabat jelas tak setimbang. Bagai langit dan bumi. Ini tak berarti lalu saya mengenyahkan kesahihan berdoa dengan bahasa Arab, ya. Buat saya, cara ungkap itu bebas saja.
Dengan logika ini, layak betul demi menggiring feel bahasa yang sebatin (minimal bermakmum) dengan dzikiran sang imam, dzikir (doa) dilakukan secara bersama-sama.
Ketiga, dalam tujuan edukasi. Faktanya, berapa banyak dari jamaah masjid kita yang fasih berdzikir (doa)? Lebih banyak mana antara yang fasih dengan kurang fasih atau bahkan tak tahu?
Lihatlah, misal, kelompok anak-anak kita. Jika mereka tak pernah diperdengarkan dzikir-dzikir dengan keras dan berjamaah, dari mana mereka akan tahu bahwa sehabis shalat mestinya dzikir subhanallah, lalu alhamdulillah, lalu allahu akbar sekian kali? Boleh tambahkan, bagaimana cara mereka tahu dan apalagi suatu saat bisa hafal Asmaul Husna jika tak pernah mereka dengarkan, yang di antara medianya potensial ialah dari masjid?
Keempat, dalam tujuan harmoni sosial para jamaah. Keragaman pengetahuan jamaah atas dzikir-dzikiran jelas tak terbantahkan. Ada yang tak tahu apa-apa. Ada yang tahunya hanya membaca subhanallah, lalu alhamdulillah, lalu allahu akbar, dan selesai. Ada lagi yang tahu dengan tambahan la ilaha illallah dan shallallah ‘ala Muhammad dan astaghfirullahal ‘adhim.
Jika di suatu jamaah masjid, katakanlah seusai shalat jamaah Maghrib dan Isya’, lalu dilantunkan dzikiran bersama dengan bacaan yang dipimpin oleh seorang imam, niscaya semua jamaah akan mendapatkan jenis dan jumlah dzikir minimal yang sama. Setidaknya, lalu terbentuklah hal itu sebagai pengetahuan berdzikir. Boleh jadi itu menjadi bekal baginya saat dzikiran di rumah, sawah, warung, perjalanan, dan sebagainya.
Soal ada orang yang menambahkan sendiri dengan Asmaul Husna seusai dzikir berjamaah, misal, itu lain hal.
Demi menimbang begitu banyaknya manfaat yang dihasilkan oleh dzikir (doa) jahr (keras) dan bersama itu, saya cenderung memilih dzikir dengan suara keras dan berjamaah.
Pandangan saya ini kiranya dicukupkan sampai di sini, tidak perlu ditarik lagi ke penyimpulan rawannya keriya’an pada suara-suara dzikir yang dilantunkan atau dilagukan atau, sebutlah dengan esktrem, dikhusyuk-khusyukkan. Anggapan curiga semacam ini tak bisa sedikit pun dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena perkara kemungkinan riya’ dan sejenisnya berdenyar di dalam hati, bukan di suara ataupun tampilan.
Maka penyimpulan saya akan begitu pentingnya melazimkan dzikir (doa) berjamaah dan keras sama sekali tak masuk akal untuk dikait-kaitkan dengan kemungkinan-kemungkinan gangguan batin tersebut.
Saya pribadi tidak lantas memandang bahwa dzikir sirr, sendiri-sendiri, negatif. Tidak. Ini tidak relevan untuk dimaknai atas-bawah, benar-salah, halal-haram. Kebiasaan menyalah-nyalahkan dan mengharam-haramkan amaliah pihak lain yang berbeda adalah sikap su’ul adab dalam ajaran agama kita. Dan mari kita tinggalkan.
Semua bentuk dzikir, mau dilakukan sendiri maupun bersama, keras atau tidak, saya pandang sama sahihnya, sama baiknya, sama bernilai kemuliaan di sisi Allah. Insya Allah.
Wallahu’a’lam bis shawab.