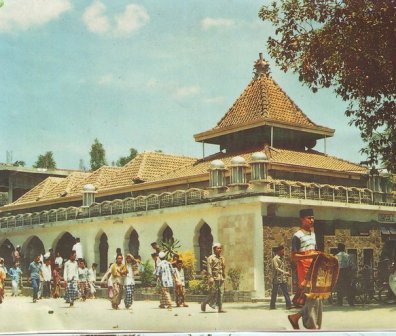“…..sudah masanya pesantren mendirikan dan memiliki kampus-kampus besar sebab bila pertumbuhan dan perkembangan pesantren ini dibiarkan mengikuti garis evolusi sejarah, besar kemungkinan pesantren merupakan embrio dari universitas tertua di Indonesia.”
Oleh : M. Ikhsanudin, MSI., Dekan Fakultas Ushuluddin IIQ An-Nur, Ustadz PP. Al-Munawwir Krapyak.
Awal mula berdirinya pesantren masih menjadi perdebatan diantara para peneliti pesantren. Jika menilik sejarah masuknya Islam di Indonesia, khususnya di Jawa, maka asal muasal pesantren tidak dapat dipisahkan dari peran “Wali Songo” pada abad XV-XVI. “Walisongo” berarti sembilan orang wali. Mereka yang di-ijma’i adalah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Dradjad, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, serta Sunan Gunung Jati.
Para wali ini tidak hidup pada saat yang persis bersamaan, namun satu sama lain mempunyai keterkaitan erat, baik dalam ikatan darah-geneologi atau pun hubungan guru-murid. Disisi lain, ada peneliti yang menyatakan bahwa “walisongo” itu tim dakwah yang terbagi dalam tiga generasi, generasi pertama, melakukan Islamisasi di wilayah Jawa bagian utara (pantura). Walisongo generasi kedua, melakukan Islamisasi di Jawa bagian tengah. Sedang walisongo generasi ketiga seperti Sunan Bayat Klaten, Maulana Maghribi Parangtritis melakukan Islamisasi untuk wilayah Jawa bagian selatan.
Menurut masyarakat santri Jawa, Maulana Malik Ibrahim (wafat 1419, di Gresik Jawa Timur) dipandang sebagai master of masters di lingkungan para wali dan pesantren Jawa. Akan tetapi terjadi perdebatan secara definitif, siapa yang pertama kali membangun sebuah pondok pesantren, sebagian kalangan menyebut “sunan Ampel” di daerah Ampel Denta Surabaya, sebagaian peneliti mengatakan bahwa yang pertama mendirikan pesantren adalah ‘Sunan Gunung Jati” di Cirebon”. Sedang, pesantren yang paling lama eksis di Indonesia adalah Pesantren Tegalsari di Ponorogo Jawa Timur yang didirikan pada akhir abad ke-18 oleh Ki Ageng Muhammad Besari.
Dari Pesantren Tegalsari inilah kemudian muncul beberapa pesantren dan pujangga Jawa, diantaranya pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri, Pesantren Darussalam Gontor, Pesantren Darul-Huda Mayak, Pujangga Surakarta Ronggowarsito, Kerajaan Islam Selangor Malaysia, dan lainnya. Pesantren tua lainnya yang masih eksis hingga sekarang adalah Pesantren Sidogiri yang didirikan tahun 1718 M oleh Sayyid Sulaiman dan Pesantren Miftahul Huda di Gading Malang yang didirikan oleh KH. Hasan Munadi tahun 1768.
Booming pendirian Pesantren di Jawa khususnya terjadi pasca perang sabil Jawa melawan Balanda yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Pasca Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan oleh Belanda oleh Letjen. Hendrik Maerkus De Kock pada tahun 1830, maka para ulama’ yang menjadi panglima perang Pangeran Diponegoro masuk ke pedalaman untuk mendirikan pesantren sebagai pusat tafaqquh fiddin sekaligus sebagai basis perlawanan terhadap penjajah. Diantara pesantren tua yang muncul pasca perang sabil Jawa adalah Pesantren Termas Pacitan yang didirikan pada tahun 1830 M, Pesantren Tambak Beras yang didirikan oleh Kyai Abdushomad, Pesantren Takeran yang didirikan oleh Kyai Kasan Ngulama’, Pesantren Begelan Purworejo yang didirikan oleh tiga veteran perang sabil Jawa yaitu Kyai Nur Qoiman, Kyai Nur Iman dan Kyai Ya’kub, Pesantren Kapurejo Kediri yang didirikan oleh Kyai Hasan Muhyi dan lainnya.
Menurut catatan Peter Carey yang meneliti naskah Jawa dan Belanda, bahwa pengikut Pangeran Diponegoro ada 108 Kyai, 31 Haji, 15 Syaikh, 12 Penghulu Kraton, dan 4 guru. Diantara tanda pesantren atau masjid yang satu barisan dengan Pangeran Diponegoro adalah adanya Pohon Sawo yang dimaknai sebagai sawwu (satu shof barisan dari pangeran Diponegoro)
Pesantren di Indonesia mulai muncul sebagai fenomena masif pada akhir abad ke-19 dan abad 20. Pesantren-pesantren induk yang sekarang ada rata-rata muncul pada abad-abad tersebut, seperti Pesantren Tebuireng Jombang didirikan oleh KH. Hasyim Asy’ari pada tahun 1899 M, Pesantren Al-Munawwir Krapyak didirikan oleh KH. M. Moenawwir pada tahun 1911, Pesantren Kempek-Cirebon didirikan oleh KH. Harun pada tahun 1908 M, Pesantren Cipasung didirikan oleh KH. Rukhiyat pada tahun 1931 M, Pesantren Salafiyyah Syafi’iyyah Situbondo didirikan oleh KH. Syamsul Arifin pada tahun 1908 M dan lainnya.
Sejarah telah menunjukkan bahwa sejak zaman kerajaan Islam Jawa, Pesantren memiliki pengaruh besar dalam urusan pendidikan, sosial, politik dan kenegaraan. Pemberlakukan ”desa predikat” bagi desa yang ditempati pesantren menunjukkan posisi strategis pesantren dalam peta tata laksana pemerintahan dan juga sebagai bukti pengakuan dari kerajaan. Peran kyai ini terus berkembang, dari menjadi guru agama, cultural maker, mengatasi pelbagai persoalan umat hingga peran strategis yang bisa mempengaruhi kebijakan Para kyai zaman dahulu adalah contoh yang paling baik dalam masalah transformasi sosial. Seorang kyai biasanya memilih tempat-tempat yang masih “mundur” peradaban masyarakatnya.
Kyai Hasym Asy’ari memilih tempat di daerah Cukir, Tebuireng untuk memulai kiprahnya. Pada awalnya, daerah ini dekat dengan pabrik Gula Pasir milik Belanda. Di daerah ini terjadi eksploitasi pekerja penuh waktu dengan gaji yang minim dan juga tumbuh praktek pekat (penyakit masyarakat) seperti prostitusi, judi, dan madat. Kyai Hasyim Asy’ari memulai dengan da’wah untuk pembebasan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan warisan beliau sekarang, Jombang menjadi daerah tumbuhnya pesantren dan budaya pesantren.
Hal serupa juga seperti yang dilakukan oleh KH. As’ad Syamsul Arifin, KH. Zarkasyi, KH. Siraj, dan lainya. Hal tersebut cuma sebagian contoh dari santri-santri yang berhasil melakukan transformasi keumatan, hingga akhirnya para kiai dan pesantren dinyatakan sebagai sub-kultur yang mampu membangun budaya tanding (cultural balance) baik dengan kerajaan maupun penjajah, agen perubahan sosial (cultural maker) dan perantara budaya (cultural broker).
Jika ditelusuri dari sejarah perpolitikan nasional, pesantren juga ikut menentukan dalam perjuangan politik dan kebiajakan nasional. Sejak awal kemerdekaan sudah banyak orang pesantren yang terlibat dalam kegiatan perpolitikan nasional seperti K.H. Abdul Wahid Hasyim (1914-1953) yang ikut menyusun “Piagam Jakarta” (yang kemudian menjadi mukadimah UUD 1945), bersama Soekarno, Hatta, Moh. Yamin, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Kahar Muzakir, Abikusno Cokrosuyoso, A.A. Maramis.
Selanjutnya K.H. Wahid Hasyim menjadi Menteri Agama pada Kabinet Hatta, Kabinet Natsir dan Kabinet Sukiman (antara 1949-1952). Diikuti K.H. Idham Khalid (lahir 1921), yang menjadi Wakil Perdana Menteri Kabinet Ali Sastroamijoyo II (1956-1957) dan pada Kabinet Juanda (1957-1959), Wakil Ketua MPRS (1960-1963), Menko Kesra (1967-1970), Menteri Sosial ad interim (1970-1971), Ketua DPR/MPR (1971-1977), Ketua DPA (1977-1983), K.H. Masykur (1902-1992) yang pernah menjadi Menteri Agama empat periode kabinet tahun 1950-an, K.H. Saifuddin Zuhri (Menteri Agama 1962-1966), K.H. Ahmad Dahlan (Menteri Agama 1967-1973), K.H. Ahmad Syaikhu (Ketua DPRGR 1965-1972), dan lain-lain.
Dalam bidang sosial ekonomi, kyai-kyai pesantren adalah para penggerak ekonomi kerakyatan seperti pernyataan KH. Hasyim Asy’ari:
“Wahai para santri putra bangsa yang cerdik pandai dan para kyai yang mulia, mengapa kalian tidak mendirikan saja suatu badan usaha ekonomi yang beroperasi, dimana setiap kota terdapat satu badan usaha otonom.”
Pernyataan Hadratusy Syaikh Hasyim Asy’ari diatas dikatakan para awal abad XX sebagai refleksi kritis atas situasi sosial ekonomi saat itu. Beliau melihat realitas kemiskinan, kemelaratan dan hidup serba kekurangan yang dialami oleh komunitas muslim tradisional. Para petani miskin, para nelayan miskin, dan para santri yang terjepit langkah ekonominya. Kenyataan inilah yang menyayat hati dan mengalirkan air mata para kyai. Akhirnya Kyai Hasyim Asy’ari menyerukan betapa pentingnya sebuah organisasi perekonomian guna merapatkan barisan melawan penindasan dan monopoli para pelaku ekonomi besar. Sebuah organisasi yang kokoh yang mampu mengkoordinasikan para petani, pedagang, nelayan miskin dan kaum tani agar hidup mereka tertolong dari gilasan dominasi pedagang besar dari kota.
Potret sosial inilah yang mendorong munculnya nahdhotut tujjar, sebuah organisasi perdagangan yang dirintis oleh para kyai pada awal abad 20, tepatnya pada tahun 1916 M. Inilah bentuk organisasi berbasis pada kesadaran ekonomi yang pertama kali didirikan oleh kaum muslim tradisional/kalangan pesantren. Pada perkembangan selanjutnya Nahdhotut Tujjar kemudian mendirikan Badan Usaha ”Syirkah al-‘inaan” dan hingga tahun 1937 dibentuklah ”syirkah mu’awanah”, sebuah koperasi yang mempunyai jaringan lebih luas dibanding ”Syirkah al-‘inan”.
Koperasi ini tetap bergerak meladeni masyarakat kecil seperti hasil pertanian, perdagangan, batik, hasil laut, rokok, sabun dan lainnya. Perwujudan badan usaha sejak syirkah al-‘inaan hingga syirkah mu’awanah tidak lain merupakan bentuk nyata kepekaan para kyai atas realitas ekonomi saat itu yang menyakitkan masyarakat pada umumnya yang ditopang dengan politik adu domba kolonial yang menginginkan adanya kemerosotan ekonomi bangsa Indonesia.
Upaya yang dilakukan oleh Kyai Hasyim Asy’ari, Kyai A. Wahab Hasbullah, Kyai Bisri Syansuri, Kyai Hasan Besari dan lainnya adalah upaya mengapliasikan secara serius ajaran-ajaran Islam melalui perdagangan serta membela rakyat kecil (petani, padagang kecil, nelayan) dari kooptasi, eksploitasi dan dominasi para pedagang besar dan kolonial Belanda. Pembacaan terhadap semangat memberdayakan ekonomi masyarakat bawah dan memproteksi dari berbagai kepentingan ekonomi dominatif ini tentunya harus menjadi inspirasi bagi kaum santri pada masa sekarang untuk melakukan upaya serius memperjuangkan ekonomi masyarakat bawah di era perdagangan bebas dan model ekonomi liberal.
Di era sekarang, kita masih menyaksikan kyai sepuh seperti KH. Maimun Zubair Rembang, KH. Musthofa Bisri Rembang, KH. Nawawi Sidogiri Pasuruan, KH. Dimyati Rais Kendal, KH. Basith Madura, Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin Jakarta, KH. R. Najib Abdul Qodir Krapyak, KH. Miftahul Akhyar Surabaya, KH. Sholihun Magelang, KH. Mukhlasin Temanggung, dan lainnya adalah kyai-kyai yang konsen dengan perjuangan keilmuan dan keumatan.
Walaupun ada diantara para kyai itu yang terjun ke dunia politik seperti KH. Maimun Zubair (Dewan Syariah PPP) dan Prof. Dr. Ma’ruf Amin (Wakil Presiden Peridoe 2019-2024), tetapi kita bisa lihat bahwa konsistensi beliau untuk gulo wentah santri dan masyarakat tetap beliau lakukan dengan baik. Begitu juga dengan kiai yang bergerak diranah pendampingan masyarakat. KH. Abdul Muhith dan KH. Abdul Hakim tetap konsisten mengadvokasi petani tembakau di Temanggung, KH. Heri Kuswanto konsen mendampingi Petani dan pengembangan eco-pesantren, KH. Chasan Abdullah dan KH. Imam Aziz yang tetap komit mendampingi gerakan pendidikan alternatif di Yogyakarta dan lainnya. Ini artinya orientasinya politik dan gerakan sosial pesantren bukan untuk kekuasaan ansich, tetapi pencapaian kekuasaan dalam lini strukturar ini hanya sarana untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan.
Orang pesantren selalu siap bermain didalam maupun diluar kekuasaan dengan gerakan untuk merubahan kondisi sosial kearah yang lebih baik atau dalam bahasa al-Mawardi disebut dengan li tahqiqi masholih al-Ummah. Oleh karena itu arah gerakan politik kyai dan pesantren diarahkan— paling tidak– dalam tiga tataran besar yaitu:
a). Gerakan politik pesantren telah dibuka dalam arti luas, yang meliputi berbagai gerakan politik baik dalam gerakan siyasah dusturiyyah (politik legislasi), siyasah maliyyah (politik anggaran), siyasah Qodhoiyyah (politik peradilan), siyasah dauliyyah (politik hubungan internasional) dan lainnya.
b). Gerakan politik pesantren yang diarahkan untuk meneguhkan hukum-hukum syara’ sebagai norma etika kehidupan publik ke dalam sistem hukum dan perundang-undangan, melalui prosedur legislasi (siyasah dusturiyyah) yang secara nyata yang berpihak kuat kepada kepentingan rakyat banyak (mashalih al-raiyyah).
c). Pesantren terus aktif melakukan kritik etik terhadap sistem sosial politik mana pun yang tidak memihak umat, khususnya kelompok mustadl’afin dan melakukan advokasi untuk perubahan kebijakan tersebut. Pesantren perlu mengambil inisiatif untuk melakukan ethical review, menguji semua aturan main dari perspektif etik agama. Islam harus menjadi pengawal etika sosial agar mampu menyelesaikan ketimpangan struktural di tengah masyarakat.
Berkaitan dengan dampak negatif globalisasi ekonomi (ekonomi neo-liberal), pesantren secara bertahap telah melakukan gerakan untuk mencegah bahaya atau dampak negatif dari globalisasi sebagai aplikasi dari konsep syadzu dzari’ah (preventif sebab/perantara). Menerima globalisasi seperti apa adanya jelas bukan merupakan pilihan yang bijak. Demikian pula sebaliknya, menolak globalisasi tanpa memberikan alternatif sama saja dengan menyodorkan keputusasaan atau lari ke gunung dengan melakukan uzlah nafsiyyah sama dengan melarikan diri dari medan perjuangan yang hukumnya dosa besar (al-firoru min az-zakhfi dzambun kabirun).
Oleh karena itu, ada beberapa pesanren telah membuat alternatif dari skenario globalisasi ekonomi yaitu:
Pertama, melawan gerakan eksploitasi ekonomi perusahaan-perusahaan multinasional atau transnasional dengan mengembangan konsep ekonomi keumatan berbasis masyarakat lokal seperti yang telah dilakukan Pesantren Sidogiri, Pesantren al-Mu’awanah, Sunan Drajat dan lainnya.
Kedua, membuat jaringan ekonomi masyarakat kecil seperti yang pernah dirintis oleh para pendahulu kita dengan membentuk koperasi al-inan, koperasi mu’awanah dan lainnya. Ketiga, mengkritisi dan mengadvokasi kebijakan negara dari pusat hingga daerah hingga peraturan desa untuk membuat kebijakan yang melindungi para fuqoro’, masakin dan dhu’afa’ seperti petani, nelayan, pekerja pabrik dan lainnya.
Kempat, menolak beroperasinya perusahaan multinasional dan transnasional di daerah dengan mengembangkan perusahaan daerah atau badan usaha yang dikelola oleh koperasi masyarakat setempat.
Dari uraian diatas dapat ditarik benang merah bahwa, pertama, dari perspektif pendidikan sudah masanya pesantren mendirikan dan memiliki kampus-kampus besar sebab bila pertumbuhan dan perkembangan pesantren ini dibiarkan mengikuti garis evolusi sejarah, besar kemungkinan pesantren merupakan embrio dari universitas tertua di Indonesia. Ia bisa menjadi bentuk awal dari Oxford (abad ke-12), Harvard (1636), Yale (1701) dan universitas dunia tertua lainnya ‘ala Indonesia, yang universitas-universitas tersebut berasal dari sekolah teologi yang kemudian menjelma menjadi universitas terkemuka di dunia. Kedua, pesantren harus tetap dinamis sebagai basis gerakan sosial, politik dan ekonomi keumatan. Wallhu a’lam bi showab.