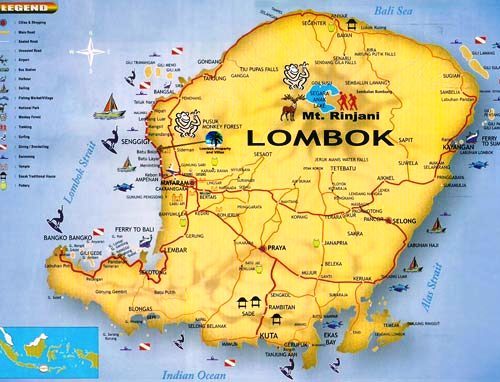Oleh: Edi AH Iyubenu, esais dan wakil ketua LTN PWNU DIY. @edi_akhiles.
Ideologi takkan pernah mati, begitu pameo yang kita dengar sejak jauh lama. Betul, sebab ideologi bersumber dari pemikiran yang telah menancap hingga ke tulang sumsum, segala bentuk cegahan dan larangan padanya takkan pernah mampu menghentikannya. Sekalipun ia diancamn dengan pidana apa pun!
Tepat di posisi demikian pulalah “ideologi Islam radikal”–meskipun istilah ini problematis, ya—menempati kursi yang sama. UU boleh melarangnya, putusan pengadilan boleh menjustifikasinya terlarang, bahkan tatanan-tatanan sosial boleh membelenggunya, tapi sebuah ideologi tetap akan berdenyar dan menyala di dalam dada para jamaahnya.
Jika didekati sebagai hak bebas tiap manusia, pada dasarnya ideologi apa pun yang dipikirkan, dikembangkan, lalu diajarkan oleh siapa pun merupakan hak yang tak boleh dilarang-larang. Hanya saja, kita semua sepenuhnya memahami betapa hak bebas dalam suatu tatanan sosial politik yang paling liberal sekalipun, terbatasi secara intrinsik oleh hak bebas orang lain, tatanan sosial besar yang disepakati, dan lazim dijustifikasi dalam bentuk suatu regulasi.
Begitupun segala macam ideologi yang lahir dari rahim Islam. Sudah pasti kita sepakat bahwa Islam bukanlah ideologi. Islam adalah agama samawi, berbasis wahyu dan sunnah Nabi Saw. Menganggap Islam sebagai suatu ideologi jelas merupakan suatu masalah yang negatif-sensitif, baik secara paradigmatik, apalagi keyakinan umatnya.
Namun faktanya dari tubuh umat Islam sendiri telah lahir begitu banyak aliran, paham, mazhab, bahkan sekte yang lalu mengideologisasi para pengikutnya dan kemudian sempurna berdenyut persis ideologi-ideologi sekular lainnya.
Khawarij, misal, yang kita tahu meletup dari konstelasi kritis politik umat Islam di era kekhalifahan Ali bin Abi Thalib lantas berkembang menjadi sebuah ideologi. Meski vulgar, relevan kita menyebutnya “ideologi takfir”. Kenapa? Sebab Khawarij sepenuh-penuhnya mengklaim siapa pun yang bukan jamaahnya adalah kafir, sesat, melanggar hukum Allah, al-Qur’an, tuntunan Rasul Saw., bahkan halal darahnya. Ali bin Abi Thalib merupakan sosok sahabat terkemuka yang meninggal di tangan kerasnya ideologi Khawarij.
Pada masa kita kini, konstelasi ideologis di antara umat Islam jelas makin meruah. Kompleksitas hidup, kepentingan, tujuan, positioning, hingga integritas pemahaman, penggalian makna, dan penafsiran dari sumber-sumber utama hukum Islam yang makin jauh membentang dari masa Rasulullah Saw menjadi pemicu utama bagi lahirnya jubelan ideologi di antara umat Islam itu. Salah satunya yang kini sangat menyedot perhatian kita semua ialah ideologi Islam radikal yang meruah di mana-mana.
Jika dirunut secara paradgmatis, radikalisasi Islam yang terideologisasikan –maksud saya: telah menjelma suatu ideologi di pikiran dan hati penganutnya—sejatinya memiliki dua kemungkinan pemicu utama:
Pertama, dipicu oleh keawaman pada ilmu-ilmu Islam sendiri.
Di titik ini, kita semua mengerti bahwa pola kehidupan kita hari ini yang metropolis menjadikan aktivitas keseharian kita semua–utamanya dalam bidang ekonomis—menyedot dengan sangat luar biasa segala peluang, waktu, energi, dan fokus kita pada aspek keagamaan kita (rohani). Makin lama aktivitas ini makin menghabiskan waktu kita. Lalu seiring jalannya masa, khittah religiusitas di hati kita, yang telah sangat lama kita pinggirkan, menyeruak ke permukaan, ke alam sadar kita, menjelma kerinduan-kerinduan pada ajaran-ajaran keagamaan. Baik yang sifatnya ritual maupun pengetahuan.
Kurangnya latar pengetahuan sebagian muslim metropolis (urban, kelas menengah) plus menyeruaknya kerinduan-kerinduan spiritul itu–dan kita tak bisa melupakan fenomena rawan stres dan depresi di kalangan mereka—lantas mempertemukan mereka dengan kantong-kantong atau tokoh-tokoh agama yang beraliran ideologis demikian. Tepat pada titik ini, dapat dipastikan benarnya pandangan bahwa seseorang akan menjelma seperti apa gurunya atau jamaah yang diikutinya.
Jika Anda berjumpa dan berguru kepada seorang agamawan yang ideologis A, pasti Anda akan menjelma A pula. Jika B, akan menjelma B pula, dan seterusnya.
Kurangnya pengetahuan keislaman dan bertemunya seseorang dengan agamawan yang ideologis menjadi simbiosis paling empuk untuk di kemudian waktu menciptakan sosok-sosok yang ideologis pula. Ini terus berbiak, meluas, meruah, dan menyebar. Fase paling awalnya tentu personal murid dari guru ideologis itu, kemudian keluarganya, kemudian teman-temannya, dan terus menyebar.
Kita telah menyaksikan dengan mata telanjang, misal, fenomena perumahan syar’i yang menggeliat di sejumlah kota, termasuk Jogja. Tentu bukan syar’inya yang problematis, tetapi eksklusivitas yang mereka bangun sehingga terkotakkan dari lingkungan sosial majemuknya itulah yang rawan persoalan.
Bagaimana fenomena itu bisa terjadi?
Tidak lain adalah telah terideologisasikannya sejumlah orang yang rindu agama itu dalam suatu indoktrinasi Islam–padahal itu tepatnya “hanyalah” sebuah pemahaman tentang Islam—sehingga sempurna tertabalkan jadi suatu paradigma kesalehan, keselamatan, dan berikutnya kebenaran. Jika sudah demikian posisinya, dapat dipastikan mereka akan menjadi corong narasi dan sekaligus pelaku nyata bagi gerakan-gerakan ideologis itu.
Ideologisasi tersebut sulit benar untuk mampu menembus kelompok muslim yang memiliki landasan atau latar pengetahuan Islam yang lebih luas dan dalam, misalnya para akademisi muslim atau kaum santri. Ini faktanya.
Maka, sampai di sini, betapa sangat pentingnya aspek pengetahuan Islam yang luas dan mendalam–atau usaha personal untuk memasuki maqam tersebut—dalam rangka melindungi diri dan keluarga dari ideologisasi itu.
Kedua, dipicu oleh suatu kepentingan (entah sosial, ekonomi, politik, hingga ukhrawi) yang mengideologis.
Kita telah menyaksikan pula dengan mata telanjang betapa di panggung politik nasional kita ada sejumlah orang yang menjadikan Islam sebagai “bargaining position”, baik di hadapan kursi kekuasaan pragmatis maupun khalayak calon pemilih gelaran pesta politik (pemilu). Demi mengeduk suara sebanyaknya, telah vulgar betul kenyataannya para “calon pemimpin” itu “menjual” ikon-ikon Islam sedemikian rupa. Di hadapan orang pragmatis demikian, tak usahlah kita heran lagi bila ekspresi-ekspresi berikutnya bisa sebegitu mencengangkan kasarnya, absurdnya, dan (maaf) kejinya.
Mengapa diksi-diksi negatif tersebut layak disematkan?
Begini. Semua kita ngerti betul bahwa Islam adalah rahmatan lil ‘alamin. Islam mengajarkan kedamaian, keselamatan, kesejukan, dan tatanan harmonis yang civilized. Itu esensi ajaran Islam, kata Rasulullah Saw, liutammima makarimal akhlaq.
Karena suatu selubung politis pragmatis-instan-partisan, populasi umat Islam yang luar biasa di negeri ini–plus sebagian besarnya mudahnya dipukau oleh simbol-simbol formalistik, sebutlah deraian ayat, hadits, dan kostum-kostum—menjadi sumber suara politik yang tak boleh dilewatkan. Ia harus dikelola, bahkan dengan cara-cara yang sejatinya bertentangan dengan ajaran prima akhlak karimah.
Saat Islam sudah dieksploitasi sebegitu rupa, jadilah Islam yang Anda dengar, lihat, dan tangkap adalah Islam yang mesti begitu dan itulah yang saya maksud “Islam ideologis” –paham, pandangan yang selain begitu, Anda anggap salah, sesat, bahkan kufur. Inilah tabiat ideologis yang telah meracuni pikiran dan rohani kita, akibat propaganda politik yang menjual ayat-ayat Allah itu. Naudzubillah min dzalik.
Lalu, siapa sebenarnya yang menderita kerugian dari fenomena ini?
Kita semua, kita sendiri, semua umat Islam sebagai suatu kesatuan negara-bangsa yang menjadi sulit sekali untuk bersatu, saling menguatkan, saling bertoleransi. Walhasil, secara sosial kita riuh benar, secara politik kita terpecah-belah, dan secara keadaban-peradaban kita terhambat benar untuk menggapai wajah Islam dan Indonesia yang maju, dinamis, dan positif.
Sangat disayangkan jika kita terus-menerus membiarkan diri menjadi bagian dari iklim berbangsa dan berislam yang memprihatinkan ini. Maka, tak perlu menunggu lebih rapuh lagi, mari kita mulai dari diri kita masing-masing, keluarga kita masing-masing, dan lingkungan sosial terdekat kita masing-masing, untuk menghidupkan lagi iklim beragama, berislam, dan bersaudara yang penuh persaudaraan, baik secara islamiyah, wathaniyah, maupun basyariyah.
Jogja, 22 Mei 2018