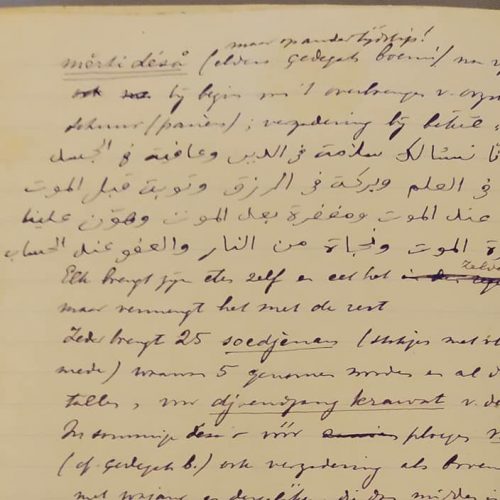Oleh KH Helmi Hidayat, dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Di malam ketika esok harinya Usman bin Affan wafat, khalifah ketiga itu bermimpi bertemu Rasulullah SAW yang mengajaknya berbuka puasa bersama. Esok pagi 17 Juni 656 M, Usman benar-benar bertemu Nabi yang dicintainya di alam barzah dalam kondisi masih berpuasa.
Ia tewas dibabat pedang beberapa orang pengecut yang mengendap-endap masuk ke rumahnya padahal saat itu ia tengah membaca kitab suci Al-Quran. Para pengeroyok hampir saja memenggal kepala lelaki tua itu jika saja istri Usman tidak segera menghambur lalu memeluk tubuh lelaki yang terkapar bermandikan darah di atas sajadah.
Sampai saat ini, belum ada satu sejarawan pun tahu pasti siapa orang-orang berdarah dingin yang mencabik-cabik tubuh Usman dengan pedang mereka. Jika pembunuh Umar bin Khattab satu orang dan gampang dikenali sebagai Abu Lu’lu’ah Fairuz dari Persia, dalam kasus pembunuhan Usman orang sulit mengenali pelakunya karena tindakan bejat itu dilakukan secara keroyokan. Apalagi saksi pembunuhan itu sangat minim, hanya istri Usman yang saat itu histeris menyaksikan suaminya jadi bulan-bulanan.
Sejarawan hanya mencatat, sambil menduga-duga, mereka adalah budak-budak Thalhah dan Zubair bin Awam. Tapi benarkah?
Dari tragedi Usman ini orang mestinya paham mengapa gerombolan dan kerumunan harus dipandang berbahaya. Dalam kerumunan, seorang pengecut sekalipun bisa jadi berani karena ia merasa gagah di antara banyak kawan. Dalam gerombolan, esksistensi seorang cerdas sekalipun menjadi lenyap karena kebesaran isi otaknya tenggelam dalam yel-yel dan teriakan-teriakan banyak orang. Dalam kelompok besar, eksistens diri menjadi lenyap, identitas diri menjadi tiada, karena kerumunan telah menelan jatidiri masing-masing individu yang ikut dalam kerumunan itu. Itulah sebabnya Jean Paul Sartre, tokoh eksistensialisme terkenal, mengatakan: ‘’hell is another people!’’
Sejarah Islam mencatat, di ujung kekuasaan Usman bin Affan yang memerintah antara 644 – 656 M, sebuah gelombang ‘’people power’’ berkumpul di Madinah menuntut Usman turun tahta. Mereka datang, atau sengaja didatangkan, dari berbagai daerah di luar Madinah — Mesir, Kufah, Basrah, dan lain-lain. Sebelum pembunuhan terjadi, mereka telah mengepung rumah Usman berhari-hari hingga sang khalifah tak bisa keluar rumah. Usman sengaja tak meminta bantuan militer dari para gubernurnya karena ia tak mau umat Islam saling bunuh dengan umat Islam lainnya.
Di hari nahas itulah segerombolan orang memanjat pagar rumah Usman lalu membunuh sang khalifah beramai-ramai. Ibnu Taimiyyah menyebut jumlah ‘’people power’’ itu 1000 orang, tapi sejarawan lain menyebut mereka yang datang dari Kufah saja sudah 1000 orang. Padahal, total jumlah umat Islam saat itu hanya 200.000 orang.
Apa yang membuat ‘’people power’’ itu terjadi? Alasannya ternyata remeh dan terkesan dicari-cari. Mari perhatikan.
Pertama, mereka menuduh Usman tidak adil mengangkat para pejabatnya. Khalifah mengangkat beberapa keluarganya jadi pejabat di samping menunjuk beberapa yunior menggantikan senior. Tapi ini dijawab Usman dengan mudah: Rasulullah SAW pernah pernah menunjuk Usamah bin Zaid sebagai panglima militer, padahal ada sahabat yang jauh lebih senior semacam Abu Bakar dan Umar. Usman juga ingin melakukan desentralisasi kekuasaan agar semua provinsi jadi mekar dan kuat. Itulah sebabnya ia memilih kerabatnya sebagai penguasa agar ia bisa percaya provinsi itu tak memisahkan diri.
Kedua, Usman dituduh melakukan tiga bid’ah sekaligus: ia mengumpulkan ayat-ayat Alquran dalam sebuah mushaf seraya membakar ribuan mushaf yang sudah ada; ia salat zuhur dan ashar empat rakaat saat berada di Mina dan tidak melakukan qashar seperti yang dilakukan Nabi SAW; terakhir ia menambah adzan jadi dua kali pada hari Jumat. Tapi ini dijawab dengan mudah oleh Usman: dengan mengodifikasi ayat-ayat Quran hanya dalam satu model mushaf, khalifah berarti telah melenyapkan benih-benih perbedaan dalam umat Islam soal tulisan Quran.
Saat berhaji, banyak orang badui berkumpul. Cara berpikir mereka pendek. Usman ingin menekankan pada mereka bahwa salat zuhur dan ashar itu empat rakaat. Soal azan Jumat dua kali, itu karena jumlah umat Islam lebih banyak dibanding jumlah mereka di masa Rasulullah, maka dirasa perlu dua azan dikumandangkan agar mereka tidak ketinggalkan salat Jumat.
Alasan ketiga adalah sejarah yang sudah usang. Usman dituduh tidak kapabel jadi khalifah karena dulu dia tidak ikut dalam Perang Badar dan ikut lari dari peperang Uhud ketika umat Islam terkepung musuh. Soal ini, Abdullah bin Umar menjawab semua tuduhan itu sebagaimana dicatat baik-baik oleh Al-Imam Al-Bukhari.
Kata Abdullah bin Umar, Usman dan semua yang menyelamatkan diri dalam Perang Uhud sudah dimaafkan oleh Allah dalam QS: Ali-Imran: 155. Saat Perang Badar berkecamuk, istri Usman yang juga putri Rasulullah sedang sakit keras, lalu Nabi melarang Usman ikut perang.
Di zaman itu belum ada handphone, grup Whatapps atau media sosial lainnya. Tapi, ketiga isu yang sebenarnya punya jawaban itu dikapitalisasi sedemikian rupa oleh orang-orang yang tak bertanggungjawab dan haus kuasa, hingga banyak umat Islam saat itu termakan hoax. Akibatnya fatal: Usman tidak dibunuh oleh pasukan Byzantium atau tentara Persia, tapi dibantai oleh rakyatya sendiri yang termakan hoax padahal mereka beragama Islam – agama dengan kitab suci yang mengajarkan umatnya agar melakukan verifikasi dan falsifikasi (tabayun) dulu setiapkali mereka mendapatkan satu berita, berita apa pun!
Nanti, ketika Ali bin Abi Thalib berkuasa menggantikan Usman bin Affan, khalifah keempat ini pun dirongrong oleh isu-isu politik yang menghalangi langkah pembanguan nasional yang dipimpinnya. Semuanya bermuara dari satu tuntutan: siapa sebenarnya yang membunuh Usman?
Jika sebuah negeri ingin maju, semua warga seharusnya kembali pada hukum, percaya pada penegakan hukum, dan jangan sekali-kali membuang supremasi hukum ke tempat sampah. Sekali hukum diinjak, Barbarianisme akan menggantikannya. Di situ kaum Barbar yang kuat akan berdendang riang di tengah kesengsaraan rakyat yang lemah dan tak terbela.