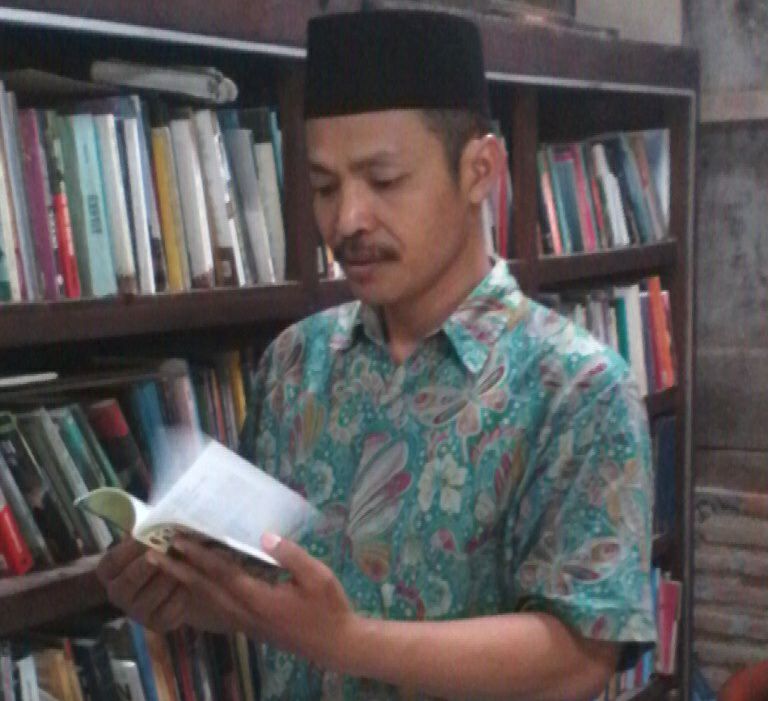Nur Kholik Ridwan, Pengajar STAI Sunan Pandanaran, Yogyakarta
Gus Dur melanjutkan tulisannya begini: “Sehingga prinsip al-Muhâfazhoh bil Qodîmish Shôlih wal Akhdzu bil Jadîdil Ashlah, tetap dipertahankan. Kitab “Al-Amtsilatu Tashrifiyah” yang digubah Kiai Maksum bin Ali, Jombang, merupakan contoh konkret dari penerimaan nilai-nilai baru; metodenya diambil dari luar, sedangkan isinya ya dari kitab-kitab seperti Nazhmul Maqshud dan semacamnya. Kitab ini, karena bagusnya metode penyampaian yang digunakan, sampai dikembangkan di Mesir (Al-Azhar).”
Penjelasan:
Gus Dur pada bagian ini mengemukakan prinsip yang selalu dipertahankan di pesantren, dan nantinya juga menjadi prinsip di kalangan NU. Kata “prinsip”, dalam KBBI dimaknai sebagai “kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya; juga bermakna dasar”. Prinsip al-Muhâfazhoh bil Qodîmish Shôlih wal Akhdzu bil Jadîdil Ashlah, bermakna menjaga/memelihara hal-hal lama yang baik dan mengambil/membuat hal-hal baru yang dipandang lebih baik”. Prinsip ini menjadi dasar dalam melakukan perubahan di kalangan pesantren dan Nahdlatul Ulama, yang berakar dari cara dakwah para wali dan penyebar Islam awal, dan jalan Islam rahmatan li`alamin yang dicontohkan Kanjeng Nabi Muhammad, para sahabat, dan para pengikutnya yang sholih-sholih.
Sebagai kata kerja dan nilai-nilai yang dilakoni masyarakat persantren, prinsip itu mendahului perumusan dalam bentuk kata-katanya. Di antara para wali yang paling genuine menggunakan prinsip itu dalam kerja-kerja dakwah islamnya adalah Sunan Kalijaga (murid Sunan Bonang), seperti terlihat dalam Kidung Rumekso ing Wengi atau Kidung Kawedar yang tetap memberi tempat bagi istilah-istilah lokal untuk menyebut Alloh ketika disampaikan kepada masyarakat; memanfaatkan wayang untuk tujuan dakwah; dan lain-lain.
Sementara dalam kata-kata perumusan di kalangan Nahdlatul Ulama, salah seorang tokoh yang mengemukakan prinsip itu, dalam sebuah karya, selain Gus Dur, adalah KH. Achmad Shidiq dari Jember (Rais Am PBNU, 1984-1989, 1989-1991), melalui karyanya berjudul Khittah Nahdliyyah; dan khutbah pada Muktamar NU pada tahun 1989 di PP al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta, pada 25 November 1989.
Dalam khutbah pada Muktamar NU ke-28 itu, KH. Achmad Shidiq mengemukakan prinsip itu, dalam rangkaian kata-katanya begini:
“Bagi kami mengadakan muktamar adalah suatu kewajiban organisatoris konstitusional. Kami tidak akan melebih-lebihkan penilaian sebagai muktamar yang lebih penting, apalagi paling penting. Semua muktamar adalah penting. Kalau menjelang muktakmar ini, demikian besar perhatian berbagai pihak terhadap NU dan muktamarnya, melalui pers, seminar, diskusi, dan lain sebagainnya, maka kami hanya dapat berkata “terimakasih atas perhatiannya dan semua kritik, saran dan koreksi, kami terima sebagai masukan sangat berharga, dan Insya Alloh, mana-mana yang baik dan cocok akan kami coba menerapkannya, sesuai dengan semboyan kami selama ini: al-Muhâfazhoh `alal Qodîmish Shôlih wal Akhdzu bil Jadîdil Ashlah. Nahdlatul Ulama rupanya menjadi organisasi transparan (tembus pandang). Orang luar dapat melihat segala yang ada di dalamnya, dan bahkan membicarakannya secara terbuka” (PBNU, Hasil-Hasil Muktamar NU ke-28, 1989, hlm. 198).
Sedangkan dalam buku Khittah Nahdliyyah, KH. Achmad Shidiq mengemukakan prinsip itu ketika menjelaskan karakter tawasuth dalam bidang kebudayaan, begini:
- Kebudayaan, termasuk di dalamnya adat istiadat, tatapakaian, keseniaan dan sebagainnya adalah hasil budidaya manusia yang harus ditempatkan pada kedudukan yang wajar, dan bagi pemeluk agama, kebudayaan harus dinilai dan diukur dengan norma-norma hukum dan ajaran agama.
- Kebudayaan yang baik, dalam arti menurut norma agama, dari manapun datangnya dapat diterima dan dikembangkan, sebaliknya, yang tidak baik harus ditinggalkan.
- Yang lama yang baik dipelihara dan dikembangkan; yang baru yang lebih baik dicari dan dimanfaatkan: al-Muhâfazhoh `alal Qodîmish Shôlih wal Akhdzu bil Jadîdil Ashlah.
- Tidak boleh ada sikap apriori, selalu menerima yang lama dan menolak yang baru, atau sebaliknya selalu menerima yang baru dan menolak yangt lama (Khittah Nahdliyyah, hlm. 67).
Dalam pandangan dan penjelasan KH. Achmad Shidiq itu, prinsip yang disebut oleh Gus Dur itu, atau dengan kata semboyan oleh KH. Achmad Shidiq, merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai tawasuth di dalam kalangan Ahlussunnah Waljamaah. Sumber dari nilai dan bersikap tawasuth adalah surat al-Baqoroh yang menyebut kata ummatan wasathon, demikian: “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang wasath agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu…” (QS. Al-Baqoroh [2]: 143).
Setelah menyebutkan prinsip al-Muhâfazhoh bil Qodîmish Shôlih wal Akhdzu bil Jadîdil Ashlah, Gus Dur kemudian menyebutkan soal Kitab “Al-Amtsilatu Tashrifiyah” yang digubah Kiai Maksum bin Ali, Jombang, sebagai contoh dari penerimaan nilai-nilai baru di dalam ilmu shorof, yang menurutnya: metodenya diambil dari luar, sedangkan isinya berasal dari kitab-kitab seperti Nazhmul Maqshud dan semacamnya. Tampaklah dengan demikian ada pemeliharaan dari yang sudah ada di komunitas masyarakat pesantren dan apa yang datang dari luar.
- KH. Ma’shum bin Ali, adalah menantu dan murid dari Hadhrotusy Syaikh Hasyim Asyari. Bersama istrinya yang merupakan anak dari gurunya itu, bernama Ny. Khoiriyah Hasyim sang kyai mendirikan Pesantren Seblak. Lahir pada abad ke-19 di Gresik, seperti disebutkan dalam Ensiklopedi Nahdlatul Ulama (III: 50-51), merupakan cucu dari KH. Abdul Jabbar al-Maskumambangi. Pesantren Seblak sendiri, jaraknya sekitar 300/400 meter dari Tebuireng.
- KH. Ma’shum bin Ali ini, dikenal ahli ilmu falak dan ilmu nahwu shorof. Dia menulis kitab berjudul Fathul Qodir yang membahas ukuran-ukuran timbangan; dalam ilmu perubahan kalimat bahasa Arab, dia menulis al-Amtsilatu at-Tashrifiyah; dan dalam ilmu falak menulis dua kitab: ad-Durusul Falakiyah dan Badi`atul Mitsal. Kitab paling terkernalnya adalah al-Amtsilatu at-Tashrifiyah, yang lebih dikenal Shorof Jombang atau Tashrifan Jombang.
Ilmu Sorof adalah ilmu yanga masuk dalam lingkup mengkaji bahasa Arab, khusus pada perubahan bentuk kata-kata kerja. Ilmu Sohrof mempelajari, bentuk kata lampau (madhi), bentuk sekarang (mudhori’), bentuk perintah (amar), dan lain-lain.Dalam Tashrifan Jombang, KH. Ma’shum tetap menggunakan pembagian kata fi`il mujarrod (kata-kata dalam fi`il itu asli, tidak ada tambahan) dan fi`il mazid (kata kerja yang ada tambahannya, sehingga memiliki makna tertentu dengan tambahan itu). Hal ini sama dengan pelajaran-pelajaran bahasa Arab di luar. Metodenya, menggunakan cara yang berbeda dari yang sudah ada, diambil dari luar pesantren, atau berbeda dalam cara penyajiannya. Kitab-kitab dari dalam pesantren saat itu menggunakan nazhoman, baik yang nahwu atau yang shorof; sedangkan Shorof Jombang menggunakan pemisahan-pemisahan dalam bentuk kotak-kotak yang dikategrikan dalam kategori-kategori tertentu, misalnya Tsulasi Mujarrod (kata yang salnya terdiri dari 3 kata), dan lain-lain, yang merupakan cara baru.
Dalam mengemukakan perubahan kata kerja itu, dibuat menjadi 10, seperti diungkapkan dalam Ensiklopedi NU (IV: 110) dan kitab Al-Amtsilatu Tashrifiyah, yaitu dengan mengambil contoh kata kerja fa`ala, dibuatlah begini: madhi (fa`ala), mudhori’ (yaf`alu), masdar (fa’lan), masdar mim (wa maf`alan), isim fa`il (fahuwa fa`ilun), isim maf`ul (wadzaka maf`ulun), fi`il amar (if`al), fi`il nahi (la taf`al), isim makan (maf`alun-maf`alun, dan isim zaman (mif`alun). Dalam memberikan contoh-contoh, KH. Ma’shum selalu menggunakan 6 kata-kata yang penting, yaitu: nashoro-yanshuru, dhoroba-yadhribu, fataha-yahtahu, `alima ya’lamu, hasuna-yahsunu, hasiba-yahsibu.
Penyebutan 6 kata yang sering dijadikan contoh itu, menurut Ensiklopedi NU memiliki filosofi begini, dengan beberapa penjelasan yang saya tambah:
- Nashoro-yanshuru, maknanya pada awalnya seorang santri ditolong orang tuanya, karenanya dia harus berbakti kepada orang tuanya;
- Dhoroba-yadhribu, maknanya sesampainya di pesantren santri dididik/dipukul oleh seorang guru, untuk menanamkan kedispilinan dan nilai-nilai seorang santri dan pengetahuannya.
- Fataha-yaftahu, maknanya setelah dia dididik/dipukul, maka dia merasa tersakiti, lalu timbul semangat dan terbuka pintu hatinya untuk terhadap pengetahuan dan nilai-nilai yang ditanamkan mancep;
- Alima-ya’lamu, maknanya santri itu kemudian menjadi alim, pintar terhadap pengetahuan agama, tahu kewajiban-kewajibannya, juga larangan-larangan, dan apa yang mesti dilakukan di masyarakat.
- Hasuna-yahsunu, maknanya setelah pintar dia akan dan diharapkan berbuat baik, berakhlak baik kepada sesama, siapa saja dan di mana saja.
- Hasiba-yahsibu, makananya santri itu bila nanti dihisab dia berharap bisa lolos memperoleh rahmat Alloh di surga.
Pada awalnya kitab itu terbit tahun 1920-an ketika beliau masih hidup oleh penerbit Salim bin Nabhan. Gus Dur juga menyebutkan, isi dari Tashrifan Jombang itu, juga berisi di antaranya dari khazanah Nazhmul Maqshud. Ini adalah satu kitab berisi nazhom-nazhom atau syi’iran-syirian tentang ilmu shorof dalam bahasa Arab yang dikarang oleh Syaikh Ahmad bin Abdurrahim. Kitab Nazhmul Maqsud ini telah disyarahi, di antaranya oleh Ulaish al-Maliki berjudul Hallul Ma’qshud min Nazhmil Maqshud; Abdurrahman Ibrohim berjudul `Aunul Ma’bud Syarah Nazhmil Maqshud.
Dalam Nazhmul Maqshud itu dibahas, tentang fi`il tsulasi mujarrod dan mazid (yang asalnya dari 3 huruf); fi`il ruba`i (yang asal katanya 4), masdar, madhi, amar, hamzah wishol, isim fa`il, maf`uf, huruf ilat dan hukumnya, dan lain-lain. Kitab Nazhmul Maqshud ini, juga menjadi bahan dari penyusunan Tashrifan Jombang, yang disebut Gus Dur dengan istilah “sedangkan isinya ya dari kitab-kitab seperti Nazhmul Maqshud dan semacamnya.” Sedangkan kata “semacamnya”, menegaskan ada kitab-kitab lain yang membahas itu selain kitab Nazhmul Maqshûd.
Dalam mengaplikasikan Ilmu Shorof, tidak akan bisa bunyi kalau tidak mempelajari Ilmu Nahwu. Sebabnya, letak dari fi`il atau perubahan kata kerja yang dipelajari dalam Ilmu Shorof itu, ada di dalam susunan kalimat, dan karenanya diperlukanlah Ilmu Nahwu, ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab, kedudukan dan perubahan kalimat-kalimat, kenapa dibaca fathah, dhommah, sukun, dan yang berhubungan dengan itu.
Dari Ilmu Shorof dapat diketahui perubahan kata-kata kerja, yang menunjukkan kata-kata yang ada tambahannya (mazid), akan mempengaruhi maknanya. Dalam hidup, seseorang yang dalam dirinya bertambah umur, pengetahuan, dan kearifan, akan mempengaruhi makna dalam melihat hidup, perjalanannya, dan kejadian-kejadian yang dialaminya. Sedangkan dari Ilmu Nahwu, dapat diketahui, kedudukan itu mengubah bagaimana dia dibaca (dhommnah, fathah, sukun), tergantung apa yang memasukinya dan posisinya. Maka seorang santri, tidak boleh menjadi kagetan, karena dalam hidupnya ia ditempa untuk bisa memaknai apa yang dilihat, yang telah dipelajarinya dari Ilmu Nahwu, dimana kedudukan dan posisi itu bisa mengubah seseorang; akan tetapi perubahan itu tidak boleh mengubah esensinya.
Kitab Tashrifan Jombang yang disebut Gus Dur itu banyak dipakai di Pondok Pesantren di Jawa Timur dan sekitarnya. Akan tetapi sebagian pondok juga ada yang memiliki tashrifan sendiri, seperti Tashrifan Krapyak, Tegalrejo, dan Kempek. Bahkan Tashrifan Jombang itu kemudian, kata Gus Dur juga dibaca dan dipelajari di al-Azhar. Wallohu a’lam.