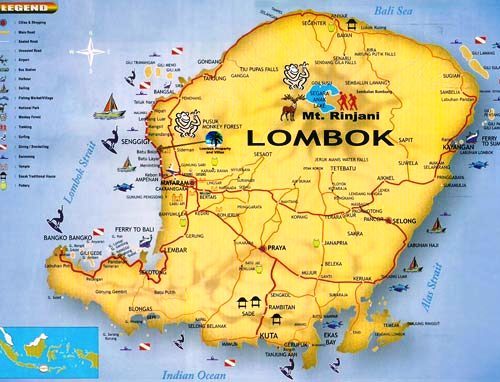Oleh Edi AH Iyubenu, Wakil Ketua LTN PWNU DIY
Sengaja saya sematkan tanda petik pada kata “terlaranganya” di judul ini, sebab hukum dan wacana kafir memang benar ada dalam al-Qur’an dan hadits Nabi Saw, juga di kalangan para ulama. Para teolog dari zaman lawas betul juga telah mendiskusikan dan meperdebatkannya sedemikian mendalamnya. Tegasnya, pada dasarnya, sebutan “kafir” memang dikenal dalam akidah Islam.
Hanya saja, istilah tersebut mesti diketahui begitu sangat sensitif, rumit, pelik, berat, kecil bagaikan lubang jarum, sehingga ia tergolong suatu masalah yang harus diwaspadai tinggi, penuh kehati-hatian, mesti berlandaskan ilmu yang mendalam, serta kebijaksanaan hati yang cemerlang. Saking beratnya masalah tersebut, banyak ulama besar yang cenderung meninggalkan bahasan tersebut atau berusaha “menutupinya” demi semata maslahat umat. Dalam bahasa sederhana saya, ia sungguh layak untuk dinyatakan “terlarang” (dengan tanda petik) dari jangkauan tangan kita. Sebab kita sungguh bukan siapa-siapa secara ilmu dan rohani di hadapan kerumitan masalah ini. Ini semata dimaksudkan untuk menghindarkan kerawanan madharatnya yang luar biasa, dengan mendahulukan sikap khusnuddan, serta mencegah orang-orang di luar ahli ilmu dan bijak untuk ikut-ikutan mengeluarkan ungkapan tersebut –yang notabene hari ini begitu entengan didampratkan.
Imam Ghazali, misal, mengatakan bahwa umpama seseorang telah memiliki 99 jenis kemungkinan kekafiran, tetapi ada satu hal pada dirinya yang memungkinkannya untuk mukmin, maka tariklah ia ke dalam kemukminan. Begitu khusnuddan dan hati-hatinya beliau.
Ada riwayat spektakuler perihal sangat wajib hati-hatinya terhadap masalah kafir (takfiri) ini. Cucu angkat Rasul Saw, Usamah bin Zaid bin Haritsah mengejar seorang musuh yang telah terdesak dalam sebuah peperangan. Ketika telah kepepet, musuh tersebut tiba-tiba mengucap kalimat tauhid. Usamah gamang. Ia sungguh khawatir ucapan tauhid itu hanya siasatnya agar tak dibunuh. Usamah akhirnya meneruskan tebasan pedangnya ke leher musuh tersebut.
Kejadian tersebut kemudian didengar oleh Rasulullah Saw. Betapa marahnya beliau Saw! Berkali-kali beliau Saw bertanya dengan nada marah dan kecewa kepada Usamah bin Zaid, “Apakah kau tetap membunuhnya padahal dia telah mengucapkan kalimat tauhid?” Usamah sampai tiga kali mesti menjawab pertanyaan kecewa Rasul Saw tersebut, dengan mengatakan bahwa ia khawatir musuh tersebut hanya bersiasat mengucvap tauhid agar tak dibunuh.
Rasul Saw akhirnya mengatakan tegas, “Apakah kau hendak membelah dadanya untuk mengetahui apakah di hatinya ada iman atau tidak? Bagaimana kau akan mempertanggung jawabkan kalimat tauhid itu kelak di akhirat….”
Saking kecewanya Usamah kepada sikapnya sendiri, ia sampai mengatakan kemudian: andai saja aku baru masuk Islam hari ini, tentulah segala keluputanku di masa lalu terampunkan, termasuk membunuh musuh yang telah mengucap kalimat tauhid itu.
Apa yang terjadi hari ini, utamanya di sosial media, sungguh kebalikan dari kesemestian untuk tidak gampangan atau bahkan ikut-ikutan menuding liyan sesat dan kafir. Kita menyaksikan betapa ringan lidahnya sebagian saudara muslim kita mengatakan saudara muslim lain sesat dan kafir hanya karena berbeda pendapat hukum, pilihan politik, bahkan organisasi. Sungguh itu sikap yang melampaui batas, tercela benar, dan dibenci oleh Allah Swt dan RasulNya Saw. Na’udzubillah min dzalik.
Al-Allamah al-Imam al-Sayyid Ahmad Masyhur al-Haddad, sebagaimana dinukil Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki, mengatakan: “Telah ada konsensus (ijma’) ulama untuk melarang memvonis kufur ahlul qiblat (umat Islam), kecuali akibat dari tindakan yang mengandung unsur meniadakan eksistensi Allah, kemusyrikan yang nyata yang tidak mungkin ditafsirkan lain, mengingkari kenabian, prinsip-prinsip ajaran Islam yang harus diketahui umat Islam tanpa pandang bulu (ma ‘ulima minal din bi al-dharurat), mengingkari ajaran yang telah dikategorikan mutawatir atau yang telah mendapat konsensus ulama dan wajib diketahui umat Islam tanpa pandang bulu.”
Beliau melanjutkan lebih rinci, “Adapun ajaran-ajaran yang dikategorikan wajib diketahui umat Islam (ma ‘ulima minal din bi al-dharurat) ialah seperti masalah keesaan Allah, kenabian, diakhirinya kerasulan dengan Nabi Muhammad Saw, kebangkitan di hari akhir, hisab, balasan, surga dan neraka, bisa mengakibatkan kekafiran orang yang mengingkarinya dan tidak ada toleransi bagi siapa pun umat Islam yang tidak mengetahuinya. Kecuali orang yang baru masuk Islam, maka ia diberi toleransi sampai mempelajarinya kemudian sesudahnya tidak ada toleransi lagi. Adapun yang dimaksud mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok perawi yang mustahil melakukan kebohongan kolektif dan diperoleh dari sekelompok perawi yang sama. Memvonis kafir seorang muslim di luar konteks tersebut adalah tindakan fatal.”
Kini mari bayangkan. Berdasar fatwa tersebut, di mana letak kebenarannya bagi kita untuk memvonis kafir saudara sesama muslim (ahlul qiblat) yang malah begitu entengan dikoarkan belakangan ini?
Secara umum, niscaya dapat dinyatakan dengan hati besar bahwa semua umat Islam di negeri ini adalah ahlul qiblat, meyakini keesaan Allah, kenabian, Nabi Muhammad Saw adalah nabi terakhir, hari kebangkitan, surga neraka, dll (sebagaimana syarat fatwa di atas). Hal-hal prnsip umum yang wajib diketahui oleh umat Islam tanpa pandang bulu pun telah dipahami dan diamalkan dengan luas, meriah, dan antusias.
Kita saksikan dengan mudah bahwa tiap waktu shalat tiba, adzan bergema di mana-mana. Bila Jumatan, masjid-masjid penuh. Bulan Ramadhan pun disambut dengan semarak. Hari kelahiran Nabi Saw pun dirayakan dengan suka cita. Dan sebagainya.
Tetapi mengapa di detik yang sama justru pekik-pekik kafir kepada khazanah keberislaman yang begitu semarak tersebut semakin gampang kita dengar dihentakkan?
Ini sungguh aneh, sebuah anomali.
Apa gerangan yang sedang menghinggapi hati kita hingga (sebagian) kita bisa entengan saja melanggar hal yang sangat prinsip –bahkan “terlarang” begitu? Bagaimana mungkin, dalam pertanyaan reflektif yang kritis, seseorang yang rajin shalat dan mengaji al-Qur’an enteng hatinya mengklaim muslim lain yang juga shalat dan mengaji al-Qur’an kafir hanya karena berbeda pandangan hukum dan politik dengannya? Serta, satu lagi, bagaimana bisa amaliah-amaliah tertentu entengan dituding sesat dan kafir oleh muslim lain yang “kebetulan saja” tak punya tradisi amaliah-amaliah tersebut, ditafsirkannya sendiri begitu rupa untuk meneguhkan klaim sesatnya tanpa mau menyimak tafsiran-tafsiran liyan, padahal berjubel tafsir lain yang positif mukmin sangat terbuka untuk diutamakan?
Sungguh aneh, ganjil sekali.
Kiranya kini kita wajib berbesar hati semua dalam berislam dan beriman untuk senantiasa mengedepankan prinsip husnuddan kepada sesama ahlul qiblat yang lain, sebagaimana ajaran fatwa di atas. Berbesar hati ini akan menjadi penanda utama bagi diri kita sendiri untuk selalu tahu diri atas hak dan derajat rohani dan keilmuan kita sekaligus dan untuk mencegah ego diri (hawa nafsu) dari melibatkan kepada perkara-perkara yang bukan otoritas kita. Bukan sebaliknya, malah gemar menceburkan diri dalam segala perkara yang bukan hak dan wewenangnya, sehingga dampaknya hanya memicu kekacauan, keriuhan, dan kefatalan tersendiri antarkita.
Mari selalu ingat ajaran ini: dari Abu Hurairah dikatakan Rasul Saw bersabda, “Jika seseorang berkata kepada saudaranya ‘kafir’, maka vonis kufur tersebut bisa jatuh benar pada salah satu dari keduanya.” (HR Bukhari).
Bayangkan, betapa mengerikannya “main-main” dengan klaim kafir atau takfir tersebut. Untuk apa kita bermain-main dengan barang berat tanggung jawabnya tersebut?
Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki mengatakan, “Vonis kafir tidak boleh dijatuhkan kecuali oleh orang yang mengetahui seluk-beluk keluar masuknya seseorang dalam lingkaran kufur dan batasan-batasan yang memisahkan antara kufur dan iman dalam hukum syariat Islam. Tidak diperkenankan bagi siapa pun memasuki wilayah ini dan menjatuhkan vonis kafir berdasar prasangka dan dugaan tanpa kehari-hatian, kepastian dan informasi akurat. Demikian pula tidak diperbolehkan menjatuhkan vonis kafir terhadap tindakan-tindakan maksiat sepanjang keimanan dan pengakuan terhadap syahadatain tetap terpelihara.”
Beliau lalu menukil sebuah hadits: “Tiga hal yang menjadi pokok iman: menahan diri dari orang yang menyatakan tiada Tuhan kecuali Allah. Tidak boleh memvonis kafir akibat dosa dan tidak mengeluarkannya dari agama Islam dengan perbuatan dosa; jihad berlangsung terus sejak Allah mengutusku sampai akhir umatku memerangi Dajjal. Jihad tidak bisa dihapus oleh kezaliman orang yang zalim dan keadilan orang yang adil; dan meyakini kebenaran takdir.” (HR Abu Dawud).
Persis “lubang jarum” yang benar ada tetapi sangat kecil, pelik, rumit, berat, dan mesti berhati-hati dengan sepenuh jiwa dan usaha untuk memasukinya, begitulah posisi masalah takfir dalam akidah Islam. Ia ada, tapi jangan mudah diadakan. Ia nyata, tapi jangan gampang dinyata-nyatakan.
Ia hanya medan para ahli, dalam ilmu dan rohaninya, sehingga fatwa-fatwanya senantiasa arif bijaksana, bukan hanya ihwal benar yang niscaya debatable. Orang Jawa menyebutnya “bener lan pener”.
Semoga kita semua makin bisa menjaga hati dan lisan dari terseret kepada masalah yang sangat berat dan serius ini. Amin.
Wallahu a’lam bish shawab.
Jogja, 23 Desember 2019