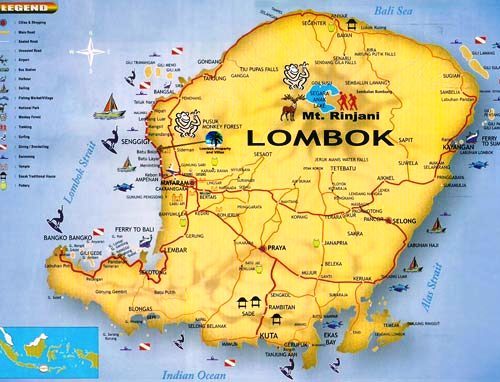Oleh Edi AH Iyubenu, wakil ketua LTN PWNU DIY.
Saya sungguh risih kepada saudara seiman yang mengomentari pakaian dan segala atribut orang lainyang niscaya dipilih, dibeli, dan dikenakannya dengan sadar diri. Tidak boleh pakai rok, tetapi yang benar adalah jubah; tidak boleh pakai celana jins, tetapi yang benar adalah gamis; tidak boleh jilbabnya berwarna-warni, tetapi yang benar adalah warna-warna hitam atau kelabu tak mencolok; tidak boleh di bawah mata kaki, tetapi yang benar di atas mata kaki; tidak boleh lengan bagian bawah terlihat sedikit pun, tetapi yang benar adalah dilengkapi kaus tangan; dan sederet tidak boleh dan tetapi yang benar lainnya. Miris lagi bila telah dilabel-labelkan dengan klaim sesuai syariat atau syar’i.
Apa-apaan ini?
Di detik yang sama, saya pun risih sama orang-orang muslim yang juga mengomentari sebaliknya kepada orang-orang yang dengan sadar memilih, membeli, dan mengenakan pakaian yang ia rasa cocok dan yakini benar. Gamis disebut baju ninja, jubah disebut sarung, niqab disebut masker, jilbab panjang disebut krukupan, dan sebagainya. Yang golongan ini seringnya melekatkan dirinya dengan pangkat-pangkat kemauan peradaban, seperti muslim moderat, modern, terbuka, dan transformatif.
Apa-apaan ini?
Kepada keduanya, saya menyimpan rasa miris yang setara: sama-sama merasa aneh, tak masuk akal, dan kenapa bisa reseh begitu sama pilihan hidup orang lain.
Apa gerangan yang menjadi soal perkaranya bagi kedua belah pihak itu?
Pertama, soal paham berislam. Aslinya, fikih. Hanya, menjadi sering sumir dan ambyar karena digampangkan dengan menyebutnya “syariat”. Syariat dan fikih dibuyarkan begitu saja dengan dianggap sama, padahal keduanya jelas-jelas mutlak beda. Ini kesalahkaprahan yang kadung mendarah-daging.
Kelompok pertama cenderung mengatakan bahwa paham Islam yang sesuai syariat (lagi-lagi aslinya fikih) ialah sesuai bunyi teks dalil. Ketika ayat berkata “ulurkanlah jilbabmu”, maka ditangkapnya bahwa baju muslimah haruslah panjang sebenar-benarnya panjang. Maka dipanjangkanlah bukan hanya jilbabnya, tapi juga bajunya. Agar lebih mantap lagi, ditambahkan pula kaus kaki dan kaus tangan. Juga mngkin niqab, cadar.
Ketika ada hadis yang mengatakan salat perempuan lebih baik di rumahnya, bukan dimasjid sebagaimana kaum lelaki yang “wajib” di masjid, dijadikanlah bunyi teks ini sebagai “kewajiban” perempuan bertinggal di rumah. Logika yang sering dipakai begini: kepada salat saja diperintahkan lebih utama di rumah, apalagi selain salat.Tentulah wajibnya wajib bagi kaum perempuan untuk tinggal di rumah saja.
Lalu lebih meruah pemahaman sejenis dijadikan “ideologi hidup” untuk tidak bekerja di luar rumah bagi para perempuan. Menjadi ibu rumah tangga saja, perempan domestik saja, itu lebih utama dibanding perempuan keluar rumah untuk bekerja yang niscaya akan bersinggungan dengan lawan jenis non mahram.
Pada varian lainnya, muncul kelompok yang mengharamkan parfum dan segala jenis wangi-wangian bagi perempuan. Bahkan pernah saya menemukan sebuah postingan yang mengatakan bahwa aroma kurang sedap tubuh perempuan yang meninggalkan parfum dan segala wangi-wangian kelak akan dibalas dengan wangi surga yang luar biasa. Tepat di waktu yang sama, pandangan minor kepada perempuan lain yang pakai parfum melesak brutal tak terbendung. Bahkan, yang parah, dikait-kaitkan dengan julukan yang tak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya, seperti “perempuan penggoda”. Bagaimana mungkin kita merayakan suatu keyakinan dengan sekaligus menancapkan fitnah ke sana sini?
Kerumitan ini meruah lagi ketika para lelaki muslim pun meriuhkannya dengan mengatakan bahwa perempuan yang keluar rumah, apalagi pakai parfum, dan pakaiannya tak berjubah begitu rupa, tidak boleh menyalahkan para lelaki bila terjadi insiden pelecehan seksual. Sebab itu risiko sosial perempuan yang tidak menjaga martabat dirinya. Ini sungguh mencengangkan!
Sebaliknya, di golongan kedua, pandangannya mengumbul ke langit luas ruang publik dengan moncernya. Ada yang mengatakan bahwa pakaian hanyalah hal lahiriah, sementara Allah Swt hanya memandang batiniahnya. Jadi, soal mau berpakaian bagaimanapun, tak usah diributkan. Bunyi teks dalil menjadi kurang diindahkan lagi.
Mereka juga berpandangan bahwa Islam sangat memuliakan kaum perempuan, termasuk di antaranya dengan menyejajarkan relasi lelaki dan perempuan. Sehingga tak ada kelogisan untuk memetakan perempuan mesti di rumah, jadi ibu rumah tangga saja, menjadi manusia domestik. Lebih gahar lagi, kondisi demikian dinyatakan sebagai “perempuan dijadikan manusia kelas dua” atau “perbudakan perempuan di era milenial”. Ilmiahnya: kolonialisasi perempuan.
Maka lalu muncul gerakan “mengembalikan perempuan kepada kesejajarannya dengan kaum lelaki”, seolah-olah selama ini kaum perempuan hidup terjajah.
Betul memang, pada derajat tertentu, saya pun tak memungkiri praktk-praktik patriarkal yang merugikan peran dan posisi kaum perempuan. Termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Hal demikian seyogianya diperbaiki, didudukkan dengan lebih baik. Perempuan adalah sama makhlukNya yang sama potensialnya dengan kaum lelaki. Begitu banyak perempuan yang berprestasi moncer dan berpengaruh hari ini. Dan seterusya.
Dalam pelbagai candaan, saya kerap mengatakan: umpama perempuan yang salehah mendapatkan pasangan yang saleh, otomatis praktik-praktik diskriminasi perempuan di dalam rumah tangganya takkan pernah terjadi; klaim penjajahan oleh para lelaki menjadi tak relevan lagi. Sebab lelaki saleh yang hatinya takut kepada Allah Swt mustahil akan sanggup menyakiti perempuan, istrinya, anak-anaknya, karena itu bukan hanya dilarang oleh Allah Swt, juga bertentangan dengan ajaran Rasul Saw yang mengatakan: “Sayangilah keluargamu, akulah orang yang paling menyayangi keluargaku….” Juga nasihat terkenal Ali bin Abi Thalib, “Takkan memuliakan perempuan kecuali lelaki yang mulia dan takkan merendahkan perempuan kecuali lelaki yang rendah.”
Bagaimana mungkin lelaki saleh melakukan keburukan-keburukan sikap begitu rupa kepada istrinya sendiri? Mustahil.
Jadi, praktik hegemonik lelaki kepada perempuan ya hanya mungkin dilakukan oleh lelaki rendah itu tadi saja. Lelaki rendah jelaslah bukan lelaki saleh. Selesai, bukan? Hal sebaliknya tentu berlaku kepada kaum perempuan.
Sayangnya, pemahaman golongan kedua yang brilian ini, memperjuangkan keadilan hidup yang beradab, kerap terjatuh kepada sikap negasi, untuk tak dikatakan “hebat-hebatan sendiri”, kepada golongan pertama tadi.
Untuk hal-hal yang sifatnya substantif, seperti melarang perempuan ke masjid, bekerja di ruang publik, tak boleh berdandan dan pakai parfum, serta berkreasi dengan ilmu dan inovasi, saya sepakat paradigma tersebut untuk diperbaiki, diperjuangkan ke arah yang lebih terbuka. Tetapi ketika telah reseh kepada hal-hal artifisial seperti pilihan personal pakaian jubah dan hijab serta niqab, saya pikir kok hal begitu melampaui batas, ya.
Jika ada seseorang yang dengan keyakinan paham berislamnya menganggap jubah dan niqab itu wajib buat dirinya, masalahnya buat orang lain apa? Tentu tak ada masalah, sebagaimana kaum perempuan yang meyakini jilbab yang sesuai syariat telah cukup dengan pakai celana atau rok dan kemeja lalu jilbab yang bermodel rupa-rupa juga tidak masalah.
Jadi, masalahnya adalah tidak ada masalah sama sekali sejatinya.
Hanya, lalu seolah menjadi masalah karena telah terseret kepada “menang-menangan, benar-benaran, pinter-pinteran, saleh-salehan”, dan sekaumnya. Jika sudah begitu, keduanya seketika sama saja lah. Sama irrasionalnya dalam memahami Islam dan egoisnya dalam meletakkannya dalam kehidupan yang majemuk ini.
Bukankahpada konteks ruang publik kita sepanjang suatu pilihan hidup, sikap, dan apalagi cuma pakaian, tak bertentangan dengan hukum negara, normaletik sosial, dan tak merugikan orang lain, ya mestinya tak ada masalah apa-apa, tho?
Tak ada masalah. Selesai.
Kedua, soal mindset. Sayangnya, pandangan clear pertama tadi kerap tak sesederhana itu belaka ruahannya. Sangat sering saya jumpai ruahannya pada klaim mindset. Wataknya lalu menjelma hina-menghina, leceh-melecehkan, dan bodoh-membodohkan. Bahkan, sesat-menyesatkan: entah sesat secara spiritual ataupun sesat secara human-sosial.
Yang kelompok pertama menuding golongan kedua kaum liberal, kebablasan, mabuk dunia, sekular, bahkan Yahudi dan Syiah. Pada kata “Yahudi dan Syiah” ini saya merasakan kegelian yang amat puncak. Aneh-aneh saja orang yang saking semangatnya sombong diri sampai melontarkan kata-kata yang tak masuk akal begitu itu, ya….
Dan, lazimnya, seluruh tudingan itu mengerucut pada penghinaan bahwa imanmu lemah, takwamu buruk, dan Islammu hanya permukaan formalitas akal-akalan. Bagaimana kita memahami dengan jernih dan rasional korelasi iman, takwa, dan ihsan dengan hal-hal yang begitu rupa artifisialnya, ya? Tak masuk akal.
Bagaimana kita meyakini dengan rasional bahwa orang yang bersarung lebih gempal imannya dibanding mereka yang bercelana jeans? Mereka yang bergamis lebih kekar imannya dibanding mereka yang pakai sarung?
Aneh-aneh saja ini.
Golongan kedua kerap tak mau kalah kualitas resehnya. Pilihan pakaian yang diyakini oleh golongan pertama lalu dijadikan parameter bagi mindset sempit, ilmunya cupet, kurang jauh main, fanatikan mati-matian, ketinggalandinamika zaman, dan ahistoris bagai batu bahkan.
Ini pun tak kalah ganjilnya. Bagaimana mungkin ilmu pengetahuan sebagai sumber mindset kita dipatok-patok pada soal pilihan pakaian? Apa jaminannya orang yang berniqab mindsetnya lebih cupet dan terbelakang dibanding mereka yang mengenakan pakaian terbuka? Apakah semakin terbukanya pakaian seseorang mengindikasikan dengan otoritatif makin terbuka pikirannya? Apa korelasi logisnya perempuan yang meyakini menghindarkan salaman dengan lawan jenis non mahram untuk dinyatakan lebih cupet mindsetnya dibanding perempuan yang bercipika-cipiki dengan lawan jenis non mahram?
Kepada kedua golongan ini, saya rasanya ingin meletakkan telunjuk di ujung bibir dan berbisik bergiliran: “Ssssttttt, diamlah, kalian sesungguhnya sama tak masuk akalnya….”
Ketiga, soal lingkaran pergaulan. Saya kira semua kita akan dipengaruhi di antaranya oleh lingkar pergaulan kita. Circle. Di sosial media, diistilahkan sistem algoritma.
Jika lingkaran pergaulan kita A, kita akan cenderung menjadi A, bukan? Jika lingkar pergaulan kita cah ambyar, kita akan cenderung begitu pula, kan?
Mau berkarakter apa pun lingkar pergaulan kita, sejatinya ia tetaplah sebuah public sphere. Di dalamnya banyak kepala, pikiran, hati, perasaan, konteks dan kepentingan, maka musykillah tak terjadi dialektika di dalamnya.
Belum lagi bila dialektika kita bersinggungan atau beririsan dengan lingkar-lingkar lainnya yang berkarakter tak sama. Walhasil, logis saja bila kita lalu suatu saat berubah, bergeser, berdinamika, atau malah berganti lingkaran, yang pada derajat berikutnya juga mengubah perspektif kita tentang hidup, orang lain, dan pula agama beserta seluruh emblemnya.
Menyatakan lingkaran pergaulan A dengan label-label begini rupa sebagai lebih adiluhung dan berperadaban dari segi keimanan, ketakwaan, dan pemikiran tentulah sekadar klaim aleman yang menggelikan. Bagaimana mungkin akal sehat membenarkan superiorisasi pada diri dan lingkarannya sendiri sembari di detik yang sama menegasi lingkar-lingkar pergaulan yang tak sama dengannya? Bagaimana mungkin dunia ini hendak diringkus dalam satu warna dan karekter pemahaman, keyakinan, dan pilihan?
Tragis lagi bila lingkar pergaulan itu adalah semata angka-angka mesin algoritma ala sosial media. Aneh! Bagaimana bisa marwah kemanusiaan kita, keluasan pemikiran kita, adiluhungnya keadaban kita diserahkan kepada mesin-mesin kaku, beku, dan hitam-putih algoritma begitu?
Keempat, soal klaim kebenaran. Lalu membuhullah klaim-klaim benar kepada pihak diri dan sebaliknya, salah, kepada pihak-pihak lain yang tak sama.
Pada konteks kritisisme ilmu, kita memahami pentingnya peran sikap kritis yang mungkin saja melesakkan narasi-narasi bantahan, antitesa, yang argumentatif kepada suatu paham atau pemikiran. Sah. Itulah sumber dialektika rasional kita. Tesis-antitesis-sintesis kita paham selalu bekerja. Tentu, pada maqamnya saja.
Tetapi, pada derajat kemanusiaan, pun kemajemukan pemahaman berislam, setiap sikap ekspresi benar kepada diri sembari menegasi salah kepada pihak lain adalah sama thagut-nya. Sama menyembah berhalanya. Celakanya, berhala itu bukanlah kritisisme ilmu, dialektika narasi-narasi, melainkan semata keangkuhan, bahkan kebebalan, yang jelas-jelas merusak khazanah luhung kemanusiaan kita.
Kepada praktik demikian, tinggalkan sajalah. Mau dalam wajah selebat apa pun kutipan ayat dan hadisnya maupun narasi-narasi akademis ilmiahnya, keduanya sama tidak sehatnya. Sama-sama tak menghormati asas mulia kemanusiaan dan dinamika luas ilmu pengetahuan –apalagi otoritas mutlak Allah Swt.
Tinggalkan sajalah….
Semua kita, dalam paham, pemikiran, dan keyakinan apa pun, di antara kemajemukan fikih Islam, jelas sama bebasnya untuk memilih dan mengenakan jenis pakaian yang kita sukai atau yakini. Membatas-batasi orang lain dalam hal begitu, serupa belaka dengan merendahkan hak asasi manusia, marwah ilmu pengetahuan, dan watak rahmatan lil ‘alamin Islam.
Sepanjang tidak melanggar hukum, normal sosial, adat setempat, dan merugikan orang lain, ya sudahlah. Segala kekurangannya, bila benar ada, biarlah menjadi urusan pribadinya dengan Tuhan.
Jogja, 23 Oktober 2019