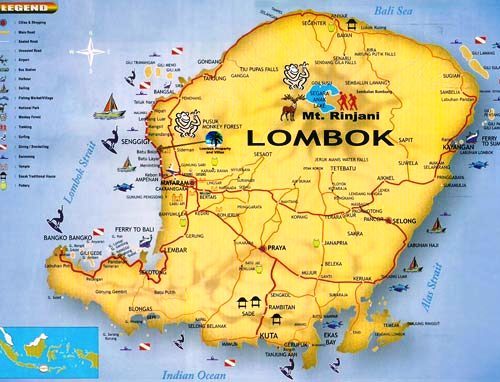Oleh Edi AH Iyubenu, wakil ketua LTN PWNU DIY
Hanifan Musliman
Kata “hanif” dalam al-Qur’an disebutkan sebanyak 12 kali dalam sembilan ayat. Secara harfiah, ia berarti “lurus”.
Dalam beberapa ayat, kata hanif ini dijejer nyambung (na’at) dengan kata “muslim”, yang arti harfiahnya adalah “berserah diri”. Jadi, keduanya berarti harfiah “kondisi yang lurus, tegak, dan berpasrah diri”. Yang dimaksudkan ialah berjalan lurus dalam hidup ini dengan sumber rohani berpasrah diri sepenuhnya kepada Allah Swt.
Nabi Ibrahim As dijadikan prototip bagi hanifan musliman ini. Ditegaskan dgn paparan ayat “dan dia (Ibrahim As) bukanlah bagian dari orang yang menyekutukan Allah Swt”.
Jadi, secara episteme, dengan merujuk pada figur Ibrahim As, sosok yang pantas mendaku sebagai hanifan musliman ialah mereka yang berjalan dengan ajaran Allah Swt dengan lurus, tegak, dan istiqamah, yang bersumber kepada imannya kepada Allah Swt yang diyakininya sebagai rujukan, tujuan, dan penghadapan hidupnya dalam seluruh aspek. Tidak ada nilai kepasrahan yang lebih kokoh, dalam, dan hunjam dibandingkan kemusliman tersebut.
Kemudian, iman yang menisbatkan kepasrahan total ini mengawalnya untuk senantiasa berjalan lurus dalam payung ajaranNya. Ini kita kenal sebagai ketakwaan: kepatuhan amaliah kepada perintah-perintahNya dan meninggalkan segala laranganNya.
Ayat yang berbunyi “ittaquLlah haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun” merupakan representasi paling lengkap perihal diri yang hanifan musliman tersebut.
Mudah kita mafhumi kini bahwa derajat awal kehanifan-kemusliman musykil digapai oleh orang yang rendah, apalagi bolong, lelaku syariatNya. Gagal berjalan lurus adalah sekaligus gagal dalam berpasrah diri total.
Perlu didedahkan segera di sini, berikutnya, bahwa buah dari sikap hanifan-musliman tentunya tidak hanya berdenyar ke dalam diri personal, tetapi juga melimpas ke luar dirinya, ke ranah sosial majemuknya dalam pelbagai bidang kehidupan, dalam rupa keluhungan perilaku atau akhlak karimah. Semakin kokoh hanifan-musliman dalam hati, niscaya semakin luhung ekspresi akhlaknya. Dan seterusnya. Begitu khittah logisnya. Inilah yang kita kenal sebagai derajat sang bajik bijaksana.
Gerak selaras ke dalam dan ke luar tersebut adalah suatu kesatuan yang niscaya, tak terpisahkan. Apalagi berkebalikan.
Jika umpama ada orang yang nampak luar biasa bagaimanapun amaliah takwanya secara lahiriah, namun akhlak sosialnya terlihat kerap jatuh pada ketegangan dan konflik, tak selaras dengan nilai-nilai adab keluhungan dan kerendahan hati, niscaya ia sedang mengidap gangguan “keterputusan rohani” antara hati dan amaliahnya. Amal-amal takwanya tidak tembus ke ruang hatinya; nilai-nilai takwa tak merembes ke relung jiwanya. Dalam sebuah hadis sahih, kondisi ini terwakili dalam gambaran: “Mereka membaca al-Qur’an namun hanya sampai kerongkongannya saja….”
Ini sangat mungkin dipantik oleh adanya hijab rohani pada hatinya, yang menandakan masih kurangnya hunjaman nilai hanifan-musliman dalam hatinya atau terbelokkannya dari jalan yang semestinya, sebutlah tauhid.
Prof. Quraish Shihab dalam Al-Misbah membuat ilustrasi sangat menarik terhadap hanif ini. Beliau mengandaikannya sebagaimana telapak kaki kanan yang cenderung ke sisi dalam (kiri) dan telapak kaki kiri yang cenderung ke sisi dalam pula (kanan). Kerjasama keduanya dengan kecenderungan yang selalu sama dan selaras seimbang menyokong kita untuk bisa selalu berjalan dengan lurus dan tegak.
Patut kita renungkan di sini bahwa boleh jadi sikap sejajar moderat yang seimbang dan selaras antara “kaki kanan” dan “kaki kiri”, sebutlah kehidupan duniawi dan ukhrawi, hablun minaLlah wa hablun minannas, merupakan pesan moral yang sangat berharga buat kita kini. Dengan kata lain, kualitas kehanifan-kemusliman bisa saja untuk kita ukur sebagai muhasabah melalui cermin keseimbangan keselarasan yang moderat antara rohani diri dan relasi sosialnya.
Ini searas dengan tuturan sebelumnya bahwa sungguh terasa sangat musykil untuk memahami adanya praktik ketidakselarasan dan ketidaksinambungan antara amal-amal takwa nan saleh di satu sisi dengan adiluhungnya amal sosialnya nan elok bestari di sisi lain. Musykil untuk kita bisa berjalan dengan lurus dan tegak bila “kaki kanan” dan “kaki kiri” tidak saling berkecenderungan menguatkan satu sama lainnya, bukan?
Marilah kita refleksikan diri masing-masing: seberapa kualitas hanifan-musliman kita (rohani yang personal) adalah seberapa kualitas akhlak karimah kita (sosial yang komunal).
Wallahu a’lam bish shawab.