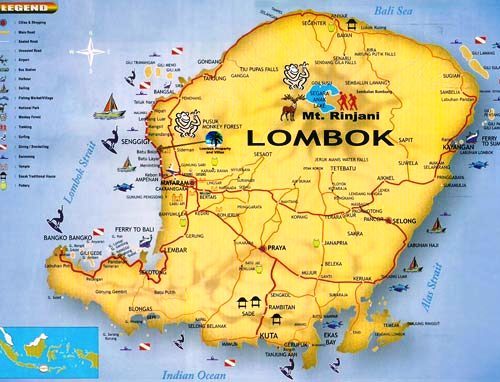Ramadhan tahun ini memang istimewa. Tahun ini, Ramadhan datang dengan keistimewaan konstitusional. Alasannya, Ramadhan kali ini datang setelah perhelatan hajat besar bangsa Indonesia, Pemilu Serentak. Pemilu merupakan agenda konstitusi untuk melangsungkan pemerintahan yang berdaulat dengan mekanisme suksesi secara demokrasi langsung. Pemilu diatur paling dasar dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945. Selanjutnya, turunan dari konstitusi tersebut mengatur lebih rinci dengan dikeluarkannya UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Membicarakan hal yang satu ini memang tidak pernah berakhir. Perjalanan tahapan Pemilu masih berlangsung sampai detik ini. Meski masih berjalan sesuai rencana, sepertinya, Pemilu kali ini jalannya tampak terseok-seok. Ada beberapa catatan yang menjadikan penilaian sementara terkait penyelenggaraan suksesi ala demokrasi langsung ini.
Pemilu, menyisakan riak-riak yang belum tenang. Sudah sejak lama riak-riak tersebut bergemericik. Jika harus dihitung mundur, tonggak pertama yang paling monumental adalah sejak adanya gerakan 4 November dengan segala anak turunannya. Termasuk 2 Desember. Acara yang lebih akbar sebulan kemudian. Bahkan, jika harus ditawarkan dengan istilah riak, ini memancing perdebatan yang sama seperti saat setelah dihelatnya 2 Desember kala itu. Acara tersebut bukan sebagai riak atau buih.
Tulisan ini tidak akan membahas tentang hal tersebut. Tentang gelaran aksi 2 Desember dan turunannya itu. Sekarang, riak-riak itu jauh lebih kompleks. Alasannya, polarisasi yang kemudian menjadi efek gerakan-gerakan tersebut kian tidak terkendali dengan hadirnya suksesi kepemimpinan nomor wahid di negeri ini.
Masyarakat menjadi terbelah tidak karuan. Polarisasi terjadi dengan menawarkan kompleksitas yang begitu tinggi. Menjadikan agama sebagai komoditas politik memang telah menjadi agenda dalam hal ini. Meski sebenarnya, tanpa harus membawa persoalan agama, polarisasi yang terjadi akibat kondisi sosial, ekonomi dan budaya sudah membawa efek yang besar. Tetapi kali ini, agama menjadi bumbu lain yang kian menyedapkan polarisasi di dalam masyarakat.
Menempatkan agama sebagai bumbu micin tentu saja hal tersebut salah kaprah. Tetapi harus bagaimana lagi? Ketika tanpa bumbu penyedap tersebut, konflik yang terjadi kurang begitu memiliki gairah. Terlebih kali ini yang disinggung adalah agama, sebuah frekuensi keyakinan seorang manusia. Hal yang paling dasar dari manusia untuk mengenali Tuhannya. Ketika hal ini diusik, sudah barang tentu menjadi sebuah harga lain bagi seseorang tersebut.
Polarisasi yang terjadi inilah sampai sekarang belum kembali merekat seperti sedia kala. Padahal secara jelas dan nyata sudah dibuktikan bahwa bangsa ini besar dengan pluralnya keragaman. Teramat sangat beragam bangsa ini dibangun, atas antar suku, golongan, ras dan agama. Dulu sekali, polarisasi tersebut mulai dipersatukan dengan Sumpah Pemuda. Kini semua itu seperti hanya dongeng saja.
Ramadhan hadir dengan penuh keutamaan. Salah satunya yang paling sejalan dengan berbagai persoalan polarisasi ini adalah saling memaafkan, jangan saling tidak bertegur sapa (jothakan). Dua hal tersebut memiliki keterkaitan tinggi dengan hadirnya Lailatul Qodr. Salah satu kriteria orang dapat menangkap kasyaf-nya Lailatul Qodr adalah dengan memperbaiki silaturahim atau menjalin persaudaraan. Dalam terminologi kebangsaan maka hal ini adalah rekonsiliasi.
Terdapat sebuah cerita dalam Kitab Dzurrotun Nashihin. Ketika terbit fajar sebelum Lailatul Qodr, Malaikat Jibril ditanya oleh para malaikat, “Duhai Jibril, apa yang akan dilakukan oleh Allah swt kepada umat Muhammad di malam ini?”. Atas pertanyaan tersebut, Malaikat Jibril menjawab, “Allah swt memandang mereka dengan kasih sayang dan mengampuninya, kecuali 4 golongan.” Para malaikat kemudian bertanya kembali, “siapa 4 golongan tersebut?”. Maka, Jibril menjawabnya, “Mereka adalah orang yang selalu meminum khamr (minuman keras), orang yang durhaka kepada orang tua, orang yang memutus tali persaudaraan, dan orang yang musyakhin (mendiamkan atau tidak bertegur sapa sesama muslim lebih dari tiga hari).”
Kitab Dzurrotun Nashihin merupakan sebuah kitab yang menyerupai kisah-kisah dongeng. Kebanyakan muatan materi dalam kitab ini adalah senjata ampuh para pendai lulusan pondok pesantren. Pendekatan yang dibawakan oleh Kitab Durrotun Nashihin lebih kepada aspek sosiologis dan antropologis masyarakat. Sehingga wajar, ketika mendakwahkan Islam kepada masyarakat dalam pengajian-pengajian maka kitab ini menjadi andalan.
Sedikit memberikan takwil terhadap kisah di atas. Polarisasi masyarakat memiliki kesinambungan dengan permasalahan memutus tali persaudaraan dan tidak bertegur sapa lebih dari tiga hari. Hal tersebut terjadi karena permasalahan berbeda pilihan. Begitu sangat wajar. Terlebih sudah dikemukakan bumbu-bumbu untuk memolarisasi masyarakat tadi.
Meski demikian, menarik kembali terhadap persoalan yang terjadi di masyarakat sekarang, pasca Pemilu Serentak. Dikaitkan dengan bulan Ramadhan yang memiliki keutamaan dalam Lailatul Qodar-nya. Maka, sudah selayaknya bulan ini adalah momentum untuk kembali merajut kembali persatuan dan persaudaraan sebangsa-setanah air atau rekonsiliasi. Limpahan maghfiroh bulan Ramadhan ini harus disambut secara berjamaah seluruh tanah air. Bahkan, sudah saatnya, bangsa Indonesia harus adhang-adhang Lailatul Qodr. Tidak hanya personnya, tetapi seluruh rakyatnya dan bangsanya sehingga Indonesia menjadi negeri yang Baldatun Thoyyibatun Warrobun Ghofur.