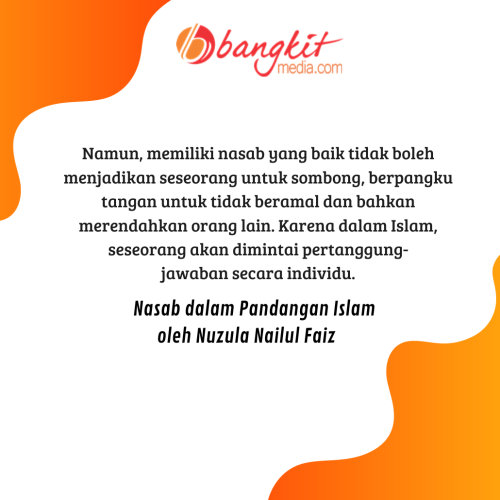Nur Khalik Ridwan, Pengajar STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta
Bismillâhirrohmânirrohîm.
Alhamdulillâhirobbil `Âlamîn.
Allôhuma sholli `alâ Sayyidinâ Muhammadin an-Nabiyyil Umiyyi Imâmil hudâ wa âlihi wa shohbihi wa sallim. Ammâ ba’du
Ngaji ke-8 di sini membahas hadits ke-4 dalam Kitab al-Adab, dan hadits No. 5973 dalam Kitab al-Jâmi`us ash-Shohîh karya Imam al-Bukhori. Haditsnya demikian:
عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ)). قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ: ((يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أَمَّهُ)).
Artinya: “Dari Humaid bin Abdurrahman dari Abdulloh bin Amr rodhiyallôhu berkata, Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya termasuk dosa paling besar di antara dosa-dosa besar, adalah seorang melaknat kedua orang tuanya.” Dikatakan kepada Rasululloh: “Wahai Rasululloh bagaimana seorang anak bisa mencaci maki kedua orangtuanya?” Rasululloh bersabda: “Dia mencaci maki bapak orang lain, maka orang itu balik mencaci maki bapaknya, dan dia mencela ibu orang lain, maka orang itu balik mencaci maki ibunya.”
Ada tiga maksud dari hadits di atas: Pertama, larangan melaknat, yang di dalamnya termasuk mencaci maki, menghina, dan melontarkan perkataan kotor, merendahkan, menyumpahserapah, dan sejenisnya, kepada kedua orang tua. Kedua, pertanyaan yang diajukan seorang sahabat, mengisyaratkan ragu, apa mungkin seorang anak mencaci maki kedua orang tuanya. Dan ini dijawab Kanjeng Nabi, yaitu mencaci maki orang tua orang lain, dan orang lain itu, bisa jadi balik mencaci ayah ibunya. Ketiga, murid perlu bertanya pada guru, manakala masalah yang diterimanya itu dirasa belum jelas dalam menuntut ilmu atau di majlis ilmu.
Makna pertama, menjelaskan bahwa mencaci maki orang tua kita adalah dosa besar atau disebut dosa paling besar di antara dosa-dosa besar. Perbuatan ini termasuk amal-amal dalam `Uqûqul Wâlidain, yang akan dijelaskan di dalam penjelasan hadits berikutnya, yaitu hadits soal `Uqûqul Wâlidain di No. 6 dalam Kitab al-Adab.
Sedangkan makna kedua dipahami Ibnu Bathol dalam syarahnya (IX: 191), dan Ibnu Mulaqqan dalam syarahnya (XXVIII: 244) sebagai “ashlun fî qath`idz dzarâ’i’, yaitu asal bagi kaidah untuk “menutup jalan menuju kerusakan”. Kaidah ini, menyebutkan bahwa perbuatan atau pekerjaan yang akan menghantarkan pada perbuatan yang dilarang Allloh, maka perbuatan itu tidak boleh dilakukan, atau dilarang dilakukan, walaupun perbuatan itu tidak dimaksudkan untuk itu.
Dari hadits itu, Kanjeng Nabi Muhammad memberi contoh, untuk menutup jalan agar tidak terjadi perbuatan atau pekerjaan mencaci maki orang tuanya sendiri, yaitu dengan larangan perbuatan mencaci maki orang tua orang lain. Dengan mencaci orang tua orang lain, dimungkinkan: orang lain tidak mencaci maki orang tua kita, tetapi juga dimungkinkan bahwa orang lain itu membalas dengan mencaci maki orang tua kita, dan kebiasaannya begitu. Maka Kanjeng Nabi Muhammad mengajarkan untuk menutup jalan itu, yaitu dengan cara tidak mencaci maki orang tua orang lain.
Kaidah soal perlunya menutup jalan menuju kerusakan ini, bersumber dari beberapa ayat Al-Qur’an, yang di antaranya:
“Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan” (QS. Al-An`am [6]: 108).
Ayat ini melarang mencaci maki sesembahan agama lain atau orang lain, karena dimungkinkan dari hal itu, orang lain atau pemeluk agama lain akan mencaci maki Alloh. Karenanya, jalan perbuatan ke arah itu disumbat atau ditutup, atau dilarang dilakukan. Dalam contoh yang lain, berbuat zina diharamkan, maka jalan untuk bisa mengarah ke situ juga ditutup, seperti melihat aurat orang lain, mengintip orang mandi, atau sejenisnya. Imam Mawardhi, seperti dikutip Ibnu Mulaqqan mencontohkan: “Dilarang menjual pakain sutera yang bisa digunakan untuk dipakai orang, yang itu tidak halal baginya” (XXVIII: 244).
Contoh lain, dalam soal kepemimpinan, adalah memilih pemimpin yang diketahui banyak berbuat fasiq, seperti melakukan korupsi, berbuat zina, dan yang lain, di dalam asalnya adalah tidak boleh, agar bisa melahirkan pemimpin yang amanah dan dapat dipercaya, sehingga tujuan memiliki pemimpin yang bisa memaslahatkan dan adil, bisa tercapai. Maka syarat kepemimpinan, harus diupayakan membatasi sekeras mungkin bagi lahirnya pemimpina fasik bisa muncul atau terpilih, dengan jalan menetapkan kriteria-kriteria tertentu.
Dari jalan asal untuk menutup kerusakan atau kemudhorotan ini, dalam kasus tertentu, berkembang dalam kaidah “menolak harus didahulukan daripada menghilangkan” kalau sudah terjadi. Kaidah ini berbunyi ad-daf`u aqwâ minar raf`i (upaya menolak lebih dulu –dalam hal-hal yang memungkinkan terjadi kerusakan- dipandang lebih kuat daripada menghilangkan kalau sesuatu sudah terjadi). Penerapannya, seperti di atas, menolak untuk memilih pemimpin atau wakil yang fasiq di atas adalah “ad-daf`u”, maka lebih baik dan lebih kuat; daripada kalau sudah terpilih dari pemimpin yang banyak berbuat fasiq, lalu terjadi kejahatan, maka menghilangkan kejahatan setelah dia terpilih, itu adalah “ar-raf`u.” Maka dalam hal itu, menolak lebih kuat untuk menutup kerusakan daripada menghilangkannya kalau sudah terjadi.
Sama dengan itu, adalah menghindari perselisihan harus lebih didahulukan, untuk menyumbat jalan terjadinya pertengkaran, perpecahan, dan kekerasan; daripada kalau sudah terjadi pertengkaran dan kekerasan, dan berupaya menghilangkannya. Maka dari sini, dapat dipahami bahwa memperhitungkan dengan cermat dan ditimbang secara matang dalam membuat UUD atau peraturan lain, harus lebih dadahulukan daripada ketika UUD lahir atau peraturan lahir, banyak cacatnya, direvisi berkali-kali; yang menghabiskan banyak energi dan biaya publik terkuras.
Akan tetapi hal itu tidak boleh semua digeneralisir dalam semua masalah. Dalam hal perbedaan misalnya, memutus jalan kerusakan dari kemungkinan lahirnya perbedaan, juga melahirkan kaidah ar-rujû’ minal khilâf mustahabbun. Keluar dari perbedaan, yang perbedaan itu mengarah pada kerusakan, pertengkaran dan sejenisnya, lebih utama. Akan tetapi ketika perbedaan itu, berkaitan dengan pandangan perbedaan antara yang sunnah dan yang wajib, di antara beberapa pendapat maka melaksanakannya lebih utama; dan dalam soal-soal perbedaan hukum suatu masalah, misalnya antara membaca basmalah dalam Fatihah sholat, maka masing-masing melaksanakan keduanya, sesuai dengan itjihad para imam yang diikuti, lebih utama. Contoh soal ini dijelaskan oleh Imam `Izzuddin bin Abdussalam dalam Qowâ’idul Ahkâm fî Mashôlihil Anâm (Darul Kutub al-`Ilmiyah, 1999, hlm. 168 dan seterusnya).
Makna ketiga, dari hadits itu juga dapat dipahami bahwa, para sahabat Nabi Muhammad, tidak segan-segan bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kalau kira-kira maksud dari perkataan beliau, masih dimungkinkan menurutnya belum jelas, atau perlu diperjelas. Hal ini, mengisyaratkan secara jelas, seorang murid, kata Ibnu Hajar al-Asqalani dalam syarahnya di Fathul Bârî: “Murid boleh menanyakan kembali kepada guru terhadap hal-hal yang belum jelas”; atau bertanya kepada yang lebih ahli untuk memperoleh penjelasan-penjelasan yang lebih baik daripada dipikir sendiri dan tidak ada kejelasan, dan supaya tidak kesasar. Hal itu juga mengisyaratkan pentingnya berguru dalam soal-soal belajar ilmu agama Islam, di mana para sahabat berguru kepada Kanjeng Nabi, dan para murid suluk berguru kepada ahli dan guru-guru suluk; dan pada saat ini, dasarnya dikembalikan pada hadits al-`Ulamâ’u warotsatul anbiyâ’.
Orang yang tidak segan bertanya, untuk memperoleh ilmu, dia juga berarti menghidupkan ilmu itu, untuk diajarkan seorang guru. Bahkan banyak hadits Kanjeng Nabi yang memuji orang-orang yang menghidupakan majlis ilmu dan ahli ilmu, seperti disebutkan Imam al-Ghozali dalam kitab Ihyâ’ di bab “Kitab al-Ilmu”. Para ahli ilmu yang ilmunya dibutuhkan untuk mendidik umat dan mengajarkannya, adalah lebih utama melakukan pendidikan dan mengajarkannya dari pada wirid dan sholat sunnah, baru setelah selesai mengajarkan ilmunya, dia bisa menjalankan sholat sunnah dan wirid, atau amalan lain selain amalan sholat rowatib.
Ilmu yang dimaksud di sini, ilmu yang mengajarkan adab-adab Kanjeng Nabi, yang mengajarkan kesadaran tentang tanggungjawab di dunia dan akhirat, dan kesadaran bahwa orang hidup di dunia ini tidak selamanya, dan karenanya, apa yang dilakukan selalu dicatat tidak dialpakan dalam buku catatan para malaikat pencatat; dan ilmu-ilmu untuk kehidupan dunia yang dihubungkan dengan tanggungjawab sebagai “kholîfah fil ardhi” dan perbuatan-perbuatan ketika ilmu itu dilakukan dan konsekuensinya di akhirat.
Dan, dalam hadits di atas, Kanjeng Nabi mengajarkan ilmu soal adab kepada orang tua, larangan mencaci maki, sebagai bagian dari dosa besar, adalah salah satu contoh bagaimana seorang guru berilmu yang mengajarkan kepada muridnya; dan murid tidak segan-segan bertanya kepada gurunya manakala dirasa belum faham dan belum jelas.
Arjû al-musyaffa’, ya Rabbi sholli `alâ Sayyidinâ Muhammadin. Walhamdulillâhi Robbil `Âlamîn wal Musta`ân. (NKR).