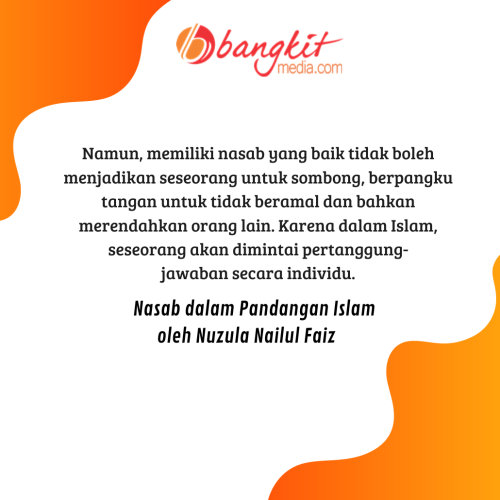Sering kali, kita melakukan sesuatu yang baik karena terpaksa. Jika keadaan berlangsung secara normal, kita kerap “leha-leha”, tidak melihat kemungkinan baru, atau tidak mampu mendeteksi ancaman yang datang.
Kalau pun “radar mental” kita bisa mendeteksi adanya ancaman yang segera datang, kita akan cenderung mengecilkan ancaman itu, dan tidak berbuat sesuatu untuk menghindarkan atau mengatasi ancaman itu.
Watak manusia selalu cenderung “kumanthil”, muttashil, melekat kepada kebiasaan-kebiasaan lama. Ini terjadi terutama dalam keadaan normal, “ikhtiyar”.
Hanya dalam keadaan terpaksa, saat terjadi “force majeur” kita mau meninggalkan kebiasaan lama; kita mau memisahkan diri, “munfashil”, dari wilayah nyaman.
Persis seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Malik dalam sebuah bait terkenal dalam kitab “Alfiyyah” (kitab berisi seribu bait tentang tata bahasa Arab alias nahwu/sharaf) berikut ini:
وَفِى اخْتِيَارٍ لاَ يَجِىءُ المُنْفَصِلْ #
إِذَا تَأَتَّى أنْ يَجِىْءَ المُتَّصِلْ
Jadi, berbahagialah mereka yang mengalami situasi sulit, karena, jangan-jangan itulah “berkah” yang dikirim Tuhan agar kita “munfashil”, berpisah dari kebiasaan dan cara-cara lama yang sudah tak sesuai dengan keadaan yang sudah berubah.
Maaf, sok bijak pagi-pagi. 😁
———
Keterangan tentang kutipan bait Alfiyyah:
Wa fi-khtiyarin la yaji’ul al-munfashil
Idza ta’atta an yaji’a al-muttashil
Secara harafiah dan gramatik, makna bait di atas adalah sbb:
Dalam keadaan normal, ikhtiyar, bukan darurat, tak boleh digunakan pronomina/dlamir atau kata ganti terpisah, “munfashil”, karena masih mungkin menggunakan kata ganti yang bersambung, “muttashil”. Misalnya: Kita tak boleh mengatakan “ضرب أنا”, melainkan harus “ضربتُ”.
Penulis: Gus Ulil Abshar Abdalla, Pengasuh Ngaji Ihya.