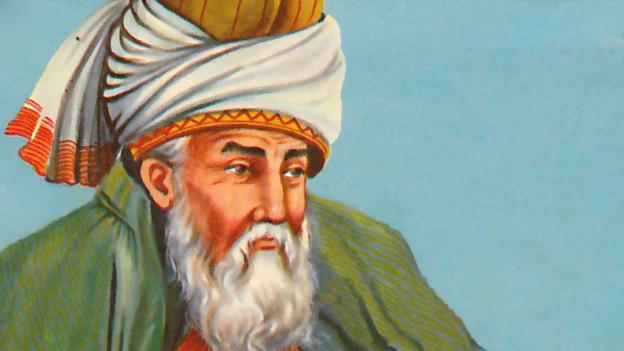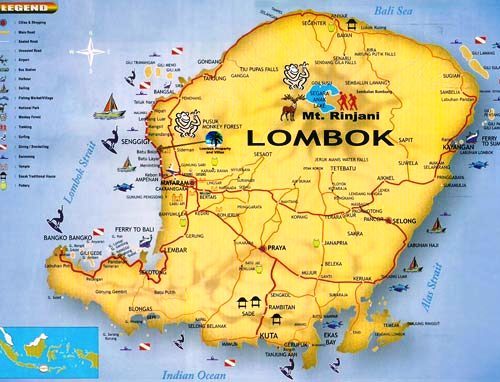Oleh Edi AH Iyubenu, esais dan wakil ketua LTN PWNU DIY @edi_akhiles. FB: Edi Mulyono.
Menajamkan esai sebelumnya, Kata Siapa Tasawuf itu Sesat?, di bagian ini saya ingin mengajak Anda untuk sejenak memasuki satu tema besar dalam jagat filsafat, yakni simbolisme. Penting diterangkan sejak awal bahwa pemahaman tentang simbolisme merupakan salah satu pilar yang diakui secara metodologis dalam tradisi tafsir dalil-dalil naqli, ayat-ayat al-Qur’an dan hadits, yang lazim diistilahkan semiotika (ilmu tentang tanda, simbol, disiplinnya Semiologi), melengkapi penggunaan metode lingustik (ilmu bahasa) dan hermeneutik (ilmu tafsir) –dalam istilah-istilah kontemporer.
Dalam konteks ikhtiar taqarrub ilallah, kaum sufi merupakan pemakai simbol-simbol yang luar biasa intensif.
Saya akan menggunakan teori simbolisme Karl Jaspers di sini. Filsuf Jerman ini berangkat dari pandangan filosofis tentang betapa sangat pentingnya Eksistensi –ya, tentu, selain Jaspers, banyak sekali filsuf Barat yang menjadikan Eksistensi sebagai lokus kajiannya.
Jaspers mengatakan bahwa eksistensi tidak memiliki dasar pada dirinya sendiri. Eksistensi tidak mungkin lahir begitu saja dari ruang kosong. Eksistensi merupakan ‘buah’ dari suatu proses transendensi. Ya, transendensi.
Sebagai contoh, tatkala Anda memandang malam yang jelaga tanpa bulan dan bintang, Anda lalu teringat pada legamnya alam kubur yang tempo hari baru dimasuki kawan dekat Anda, Anda lalu bergidik membayangkan betapa mengerikannya alam kubur yang juga akan Anda masuki suatu hari. Hati jadi gemetar, lalu lisan menggumam, “Astaghfitullahal ‘adhim, ampuni dosa-dosaku, ya Allah, ridhailah semua amalku, ampunilah semua khilafku.”
Inilah transendensi eksistensial yang Anda raih melalui simbolisasi langit gulita tanpa bulan dan bintang. Tepat pada detik di mana Anda mentransenden, Eksistensi rohani, spiritual, berdenyar kuat. Anda mengalami transformasi spiritual –dalam bahasa Islam bisa disebut kesalehan atau taqarrub ilallah.
Contoh lainnya ialah kala Anda sedang sujud di atas sajadah pada suatu malam Ramadhan, simbolisme sujud Anda yang secara pemikiran dihasratkan untuk meraih Lailatul Qadr, misal, merupakan transendensi yang menjadikan Anda ada. Mengeksistensi.
Sampai di sini, simbol-simbol apa pun yang membuat kita mampu mengalami suatu transendensi, kemudian dengannya kita menjadi Ada secara rohani-spiritual, lalu kita pun menjadi merasa memiliki makna dan orientasi dalam kehidupan profan ini, misal jadi rajin ngaji, shalat, atau sedekah demi taqarrub ilallah, itu semua jelas merupakan hadiah dari simbol-simbol yang berhasil ditransendensikan.
Kaum sufi, kita tahu, menjadi kelompok yang sangat intensif menggunakan simbol-simbol dalam lelampah rohaninya. Kesalikannya. Taqarrub ilallah.
Mengapa simbol?
Sebab, sebagaimana juga dinyatakan Jaspers, hanya melalui pengalaman simbol-simbollah kemahaluasan semesta rohani, spiritual, Ilahiah, atau dalam jagat sufisme disebut makfiratullah, memungkinkan diungkapkan sehingga menjadi suatu pemikiran, wacana, diskursus, atau ‘representasi pengalaman rohani’ yang terbahasakan. Ingat ya, kita adalah makhluk bahasa dan dengan dan di dalam bahasalah kita bisa menyatakan diri secara keseluruhan. Tujuannya tentu tak lain ialah untuk pembelajaran bagi orang lain, murid, dan jamaah suatu tarekat dan generasi berikutnya.
Di tarekat Sammaniyah, misal, ada dzikiran yang terdengar berbunyi “hu”. Jamaah tarekat itu membacakannya berulang kali banyak sehingga ritme suara “hu” terdengar bagai kidung yang menjeterah ke relung hati. Orang yang tak tahu, atau tak memiliki kedekatan pengalaman rohani dengannya, sehingga berjarak dari simbolisme “hu” tersebut, boleh jadi akan mengernyit ganjil atau bahkan mencemooh. Padahal sejatinya “hu” tersebut adalah dari kata “huwa”, dibaca sukun, dan tak lain yang dimaksud adalah “Allah”. Maka sesungguhnya yang sedang mereka seru dan resapkan di dalam hati ialah Allah, Allah, Allah.
Jelas kini betapa simbolisme “hu” pada amaliah tarekat ini tidak lagi bekerja sebagai suatu obyek diskursus, pemikiran, tetapi pengalaman subyek yang mentransendensi.
Lalu, di mana letak masalahya, melawan dengan syariat, apalagi diklaim salah, sesat, atau zindiq?
Letak persoalannya hanyalah semata soal “mengalami simbolisme” tersebut dan “tidak mengalami”. Keberjarakan memang kerap menjadi problem yang sentimentil bila tidak dikendalikan dengan bijaksana.
Jaspers –dalam suatu polemiknya dengan Rudolf Buttman yang menghasrati purifikasi (pemurnian) mutlak agama Kristen dari simbol-simbol mistis, persis yang juga terjadi dalam sejarah agama Islam—memberikan pembelaan kuat pada simbol-simbol rohani ini. Ia menyatakan simbol-simbol mistis sejenis itu sebagai bagian dari kehakikatan spiritual (agama). Jika ia dicerabut atas nama apa pun, termasuk purifikasi, maka agama akan kehilangan “pengalaman sakralitas”-nya. Bahkan lebih parah, agama lalu hanya akan menjelma tumpukan doktrin beku yang bergeliat di permukaan tetapi kering makna dan atsar di kedalaman batin.
Saya kutipkan satu saja dari ungkapan puitik Maulana Rumi di sini: “Duhai duka cita, jika kau punya nyali datanglah padaku.”
Pengalaman-rohani-personal-simbolik macam apakah gerangan yang hendak disenaraikan Rumi melalui puisi tersebut?
Jika ia diberantas dari semesta batin simbolisme, maka yang akan Anda tuai hanyalah “kegilaan sang arogan” atau “keputusasaan yang terlarang” atau “pengingkaran pada nikmat-nikmat Ilahi”. Soal ayat-ayat untuk mengukuhkan negasi ini jelas mudah disematkan di sini.
Tapi jika Anda mengakomodir pendekatan simbolis dalam menakwil puisi tersebut, akan terlihat bahwa simbolisme “duka cita” yang notabene merupakan kondisi yang paling dienggani oleh manusia manapun –termasuk kita yang muslim—yang ditantang oleh Rumi untuk mendatanginya “jika kau punya nyali”, sangat koheren dengan (misal) ayat 13 dari surat al-Ahqaf: “Sesungguhnya orang-orang yang berikrar Tuhanku adalah Allah dan beristikamah dengannya, maka takkan ada rasa takut dan sedih dalam hidupnya” dan (misal) surat Yunus: “Ketahuilah sesungguhnya para wali Allah (hamba-hambaNya) tak ada ketakutan dan kesedihan dalam hidupnya.”
Tatkala perasaan “berduka cita” yang niscaya lahir dari sekeping hati yang masih intim dengan hawa nafsu (misal khawatir harta berkurang bila disedekahkan) ‘diancam’ oleh Rumi untuk coba menggodanya dan Rumi menjanjikan tidak bakal tembuslah godaan-godaan hawa nafsu tersebut ke relung hatinya, bukankah itu adalah buah paling hakiki dan sejati dari iman yang mendalam kepada Allah Swt.?
Begitulah simbolisme pengalaman rohani diperagakan oleh para sufi dalam pelbagai bentuknya, entah itu puisi, musik, ataupun tarian. Aras yang dituju oleh semua medium simbolisme para sufi itu tak lain adalah taqarrub ilallah.
Lalu, bagaimana mungkin itu semua dinyatakan salah, sesat, bertentangan dengan syariat, atau zindiq?
Lihatlah ayat 27 dan 28 dari surat Az-Zumar: “Sesungguhnya telah Kami buatkan bagi manusia dalam al-Qur’an ini setiap perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran. (Ialah) al-Qur’an dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan (di dalamnya) supaya mereka bertakwa.”
Kita fokuskan pada dua frase ini: “Kami buatkan bagi manusia dalam al-Qur’an ini setiap perumpamaan” dan “supaya mereka bertakwa”.
Dengan melihat langit yang tanpa bulan dan bintang itu, kemudian kita berpikir tentang alam kubur yang gulita, hati kita bergetar dan takut pada azab Allah, bukankah itu bakal membuahkan percik-percik ketakwaan kepada Allah?
Ketika misal dalam surat al-Baqarah al-Qur’an menyimbolkan sedekah yang penuh riya tanpa iman kepada Allah bagai debu di atas sebuah batu yang kemudian turun hujan deras sehingga debu itu tak bersisa sedikit pun, bukankah itu adalah perintah berefleksi secara simbolis agar ibadah sedekah kita menghasilkan transendensi (bertakwa)?
Sewaktu surat al-Ankabut memberikan perumpamaan pada orang-orang yang tidak menyandarkan kehidupannya kepada Allah bagaikan laba-laba yang membangun sarangnya padahal serapuh-rapuhnya rumah adalah rumah laba-laba, bukankah itu adalah perintah berpikir dan merenung simbolis yang mendalam agar kita mampu menepis segala godaan non-Ilahi (seperti kepongahan rasionalisme murni) dan berlabuh kepada takwa kepada Allah?
Begitulah para sufi, para salik, dan pelaku tarekat merefleksikan simbolisme-simbolisme transendental dalam pelbagai bentuk amaliah maupun ungkapan-ungkapan yang jelas berarah semata kepada taqarrub ilallah.
Semoga bermanfaat.
Masjid An-Nur, Jogja, 30 Mei 2018