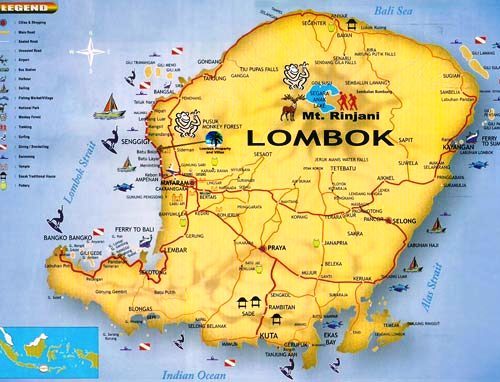Selama ini penanganan hoaks masih berpusat di produsennya, yaitu mereka yang sengaja menciptakan dan menyebarkan berita palsu. Ini telah benar, tetapi belum cukup. Dari berbagai kajian terlihat bahwa hoaks bisa laku di masyarakat yang satu tetapi bisa tidak laku di masyarakat yang lainnya. Mengapa ini terjadi?
Karena hoaks bukan sekadar siapa produsennya, tetapi juga konsumennya. Ada sekolompok orang yang lebih rentan terhadap hoaks daripada yang lain. Dan ini sangat terkait dengan kondisi psiko-kultural kelompok tersebut, selain juga tentu saja materi hoaksnya itu sendiri.
Misalnya hoaks mengenai kebangkitan PKI lebih laku di Jawa Barat daripada di Jawa Tengah. Sejauh yang saya pelajari, ini terjadi karena sentimen anti-PKI terus menerus dirawat oleh kalangan Islam modernis yang memang lebih kuat di Jawa Barat daripada di Jawa Tengah. Sentimen ini bekerja melalui ingatan kolektif yang diturunkan dari generasi ke generasi dengan penambahan di sana-sini.
Oleh karena itu, pemberatasan hoaks akan menghadapi kesulitan kalau hambatan psiko-kultural itu tidak diatasi terlebih dahulu. Hambatan ini sudah menahun, sehingga sudah dianggap sebagai kebenaran. Kampanye literasi yang lebih bersifat seremonial saja tidak cukup. Butuh intervensi terhadap kultur yang lebih radikal.
Selain itu, cukup pasti strategi pemberatasan hoaks harus diterapkan secara kontekstual. Strategi di Jawa Barat bisa berbeda dengan strategi di Jawa Tengah, tergantung hambatan psiko-kulturalnya masing-masing. Di sinilah para sejarawan dan antropolog, juga psikolog, mengambil peran. Mahasiswa filsafat seperti saya cukup menunjukkan kemana jalan untuk pergi, meski suka kebingungan kemana jalan untuk pulang.
Penulis: Amin Mudzakkir, Peneliti LIPI.