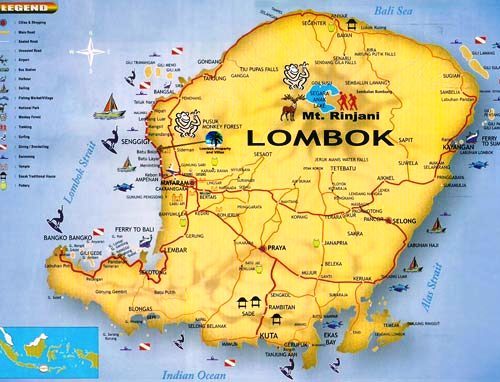Media Sosial Era Pandemi
Situasi tidak normal era pandemi covid ini memunculkan banyak fakta sosial yang selama ini tidak terlalu nampak secara nyata dan vulgar.
Bisa jadi, fakta sosial yang muncul saat ini, telah ada sebelum covid melanda, hanya saja, tidak terlalu signifikan dan fenomenal. “Berkah” covid, nampaknya fakta sosial ini menjadi fenomena.
Di antara fakta sosial yang paling dominan kemunculannya dan bisa jadi fenomena adalah, respon masyarakat beragama (islam) terhadap isu-isu fiqh yang nampaknya dilihat dengan sangat sederhana. Misalnya, suatu kesepakatan hukum yang diambil berdasarkan banyak pertimbangan dan sudut pandang oleh para pakar dari berbagai displin keilmuan, bisa didebat secara bebas oleh masyarakat umum (baca: awam) di media sosial.
Sepertinya, ini fakta lanjutan dari ungkapan “matinya kepakaran”, yang beberapa waktu lalu muncul sebagai sebuah istilah untuk merespon dan menamai sekelompok “masyarakat serba tahu” di dunia maya. Ini yang saya maksud sebagai fenomena, sebab luasannya melebihi kemunculan sebelumnya yang hanya sebagian kecil. Belum terlalu fenomenal.
Media Sosial Era Pandemi. Dalam pengamatan sederhana saya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi fenomena kemunculan “matinya kepakaran” dan “masyarakat serba tahu” ini. Di antaranya, tidak adanya sekat di ruang maya ini. Baik sekat geografis dan juga akademis.
Dalam ranah fiqh, keduanya memiliki peranan yang sangat penting. (Jika memposisikan fiqh sebagai perangkat memahami syariat secara prosedural). Dalam kajian fiqh, geografi atau kewilayahan itu menjadi (salah satu) pertimbangan suatu qaul difatwakan. Makanya muncul istilah qadim dan jadid dalam kajian fiqih syafi’iyyah. Atau bisa juga merujuk pada istilah “muqtadlo-l-hāl”. Istilah ini terkait tentang sekat (batas) geografis, atau di era covid lebih familiar disebut zona (hijau | merah). Itu yang pertama, sekat geografis.
Dalam konteks geografis ini, pelaksanan ibadah di masa pandemi ini kan beragam. Shalat di masjid misalnya. Dikarenakan interaksi media sosial ini membuat akses kita mudah, sekat wilayah ini sering dilupakan. Wah, daerah saya aman, kata seorang pengguna medsos, misalnya. Padahal, dia memang berada di daerah yang tidak merah. Tapi ya karena lupa sekat wilayah itu lah, akhirnya dia terpengaruh beranggapan sama. Padahal, setiap wilayah, bisa beda situasi dan kondisinya.
Nah, yang kedua, sekat akademis. (Istilah ‘sekat’ ini saya pakai dan maksudkan untuk kepentingan khusus di sini). Sekat akademis, dalam kajian fiqih, khususnya, dan umumnya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, itu lazim adanya. Dalam bidang fiqih misalnya, ada klasifikasi otoritas keilmuan dan pemfatwaan. Mujtajid mustaqil, mujtahid ghair mustaqil, mujtajid muqayyad, mujtahid tarjih, mujtahid fatwa, dll. Gelaran tersebut bukan gelaran yg dimunculkan secara asal, akan tetapi berdasarkan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki oleh ulama bersangkutan.
Terkait pertimbangan kompetensi akademis atau keilmuan ini, dalam sejarahnya, Nabi telah mencontohkannya. Misalnya dalam peristiwa kawin silang pohon kurma, beliau memberikan “ruang ijtihad” kepada para sahabat yang ahli di bidangnya, dalam kasus ini para petani kurma itu. Beliau mengatakan, kalian lebih faham dengan dunia (tani kurma) kalian.
Nah, selaras dengan semangat apresiasi dan pemberian ruang ekspresi kepada orang-orang yang memiliki keahlian sebagaimana dicontohkan oleh Nabi, Mbah Hasyim Asy’ari dalam Risalahnya mengutip kesepakatan mayoritas ulama mujtahid, tentang kewajiban bagi orang awam, orang yg tidak memiliki basis keilmuan yang cukup (dalam dunia fiqh; mujtahid) untuk mengikuti pendapat dan kebijakan para pakar dan ahli.
Syeikh Yusuf al-Qardhawi, dalam bukunya, Ijtihad Kontemporer, mengatakan secara tegas bahwa, kita butuh untuk berijtihad dan boleh melakukannya. Tetapi, kata al-Qardhawi, itu tidak bisa dilakukan secara serampangan. Dia menawarkan dua model ijtihad; intiqā’ī dan insyā’ī, sebagai (semacam) rambu-rambu.
Media Sosial Era Pandemi. Meski demikian, yang perlu diwaspadai adalah, semangat berijtihad yang tidak terukur seringkali mengabaikan prosedur yang benar dalam berijtihad. Sehingga, bukan solusi yang muncul, tetapi justeru polusi. Sebabnya, menurut al-Qardhawi, abai terhadap semangat zaman. Peristiwa pada zaman tersebut diabaikan begitu saja, sehingga pendapat yang difatwakannya justeru mempersulit hamba-hamba Allah, padahal Allah telah memberikan kemudahan bagi mereka.
Menghindari terjadinya kekhawatiran al-Qardhawi ini, Ijtihad era modern ini bisa dilakukan secara kolektif. Pelibatan para pakar di bidang keilmuan tertentu, untuk menjadi dasar dan bahan pertimbangan suatu pendapat atau fatwa diproduksi. Hal ini sebagaimana dikenalkan oleh Prof. Amin Abdullah dengan teori integrasi-interkoneksi bidang keilmuan. Supaya, sudut pandang terhadap suatu kasus, dapat dilihat secara luar dan mutli disiplin.
Yang pada akhirnya, pendapat yang difatwakan menjadi berbobot-berkualitas.
Nah, balik lagi ke konteks media sosial ini. Tidak adanya sekat di dunia maya, media sosial, membuat setiap orang tergoda untuk mengkritik, mengkonter, bahkan membuat “fatwa tandingan” terhadap pendapat yang muncul sebagai kesepakatan bersama para pakar. Bahkan, kadang dibumbui dengan narasi yang agak provokatif. Seolah ada ajakan untuk membangkang secara berjama’ah.
Padahal, terkait fiqh covid ini, para ulama secara global memiliki pandangan yang natabene sama. Sebab, fatwa yang disepakati ini sudah melalui kajian yang mendalam dan lintas disiplin ilmu pengetahuan.
Sayangnya, senampak saya, para pengusung gerakan “membangkang berjama’ah” ini tidak sadar sekat akademis. Lebih kepada perasaannya saja yang tentu sangat subjektif. Alasan rindu masjid misalnya yang mengemuka. Lah, yang rindu masjid bukan hanya dia dan mereka.
Simpulan sederhananya Media Sosial Era Pandemi, kesepakatan para ulama ini adalah, paling tidak, suatu keyakinan. Sebab ia muncul dari kajian yang komprehensif dan ilmiah. Sedangkan “fatwa tandingan” itu adalah suatu keraguan. Sebab muncul dari pandangan subjektif berdasarkan perasaan semata. Jika dikorelasikan pada qaidah ushul fiqh, al-Yaqin lā yuzalu bis Syak. Jadi, bermedia sosial jangan sampai membuat kita lupa diri juga. Tetaplah bertanya kepada yang ahli.
Barangkali demikian.
Penulis: Ustadz Tajul Muluk, M.Ag., Pengurus LDNU DIY.
Artikel terkait baca di sini
Tonton video tausiyah Ust Tajul Muluk. Tonton di sini