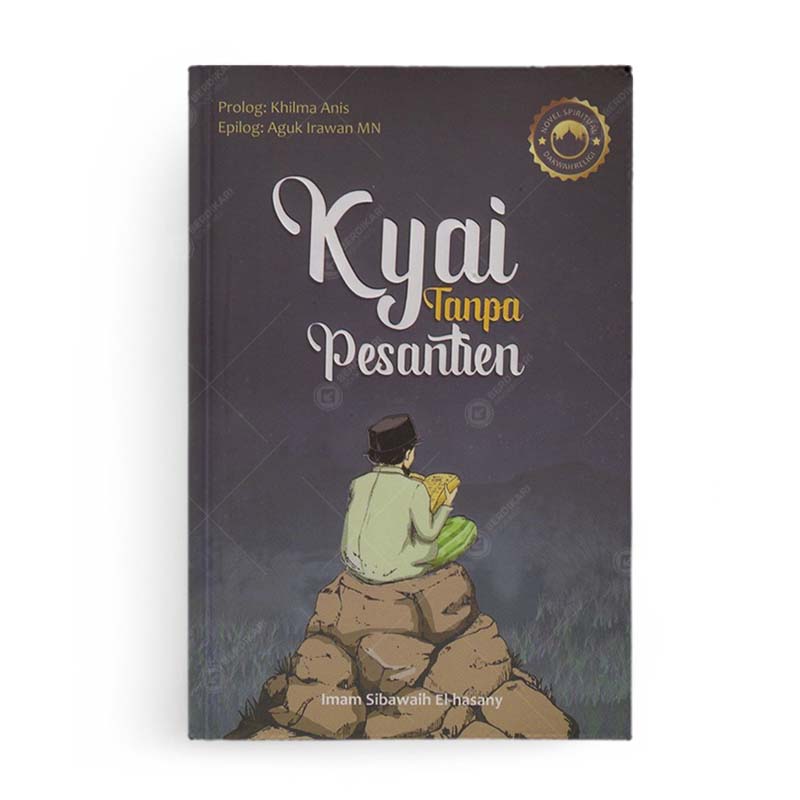Kyai Tanpa Pesantren, Laku Sufi dalam Sebuah Karya Fiksi
Belakangan ini, dunia novel Indonesia, terutama novel bernuansa keislaman sedang bergeliat. Beberapa novel muncul dan merebut hati penggemar. Salah satunya bertajuk “Kyai Tanpa Pesantren” atau biasa disebut KTP karya Imam Sibawaih El-Hasany.
Sebenarnya saya pernah salah sangka terhadap novel ini.
Saya tahu novel ini dari promosi yang dilakukan penerbitnya. Tepat di bawah promo tersebut, sebuah akun facebook, saya lupa nama akunnya, berkomentar mengenai judulnya. “Seperti judul essay”. Begitu kurang lebih bunyinya. Sebuah komentar yang tepat sekali menggambarkan pikiran saya ketika pertama kali, secara sekilas melihat promo buku ini. Judul buku yang serupa judul essay diperkuat dengan adanya prolog dan epilog dari dua penulis terkemuka.
Salah sangka kedua terbersit karena nama novelisnya yang kelewat beken. Di dunia Islam, terutama Islam klasik, nama Imam Sibawaih bukanlah sosok asing. Mereka yang pernah belajar ilmu gramatikal Arab, mininal pernah mendengar nama ini. Orang Persia, seorang ahli tata bahasa Arab. Karenanya, sempat terbersit, buku ini merupakan karya terjemahan atau saduran dari karya tokoh dunia tadi yang jarang diketahui orang. Memang, memiliki nama sama dengan orang baik dan terkenal memberikan barokah tersendiri, meski sering didahului salah sangka.
Alur Cerita
Buku ini bercerita tentang Gus Ainu. Putra pengasuh pesantren di Magetan, Jawa Timur. Bukan pesantren kecil namun tidak bisa dibilang istimewa juga. Menariknya, Gus Ainu telah memiliki pertanda akan menjadi sosok istimewa sejak kecil. Bahkan, sejak masih bayi.
Salah satunya terjadi ketika acara akikah. Kejadian menarik ini sampai membuat seorang tokoh Islam yang hadir, dalam novel ini bernama Habib Luthfan, menitipkan pesan, “tiap takdir ada tanda dan pertandanya, anakmu sudah memberi kita pertanda; dia bukan anak biasa.” (hal. 15)
Keanehan ini berlanjut ketika Gus Ainu, tokoh utama novel ini, beranjak dewasa. Saat mengantar para kiai berbaiat, Gus Ainu yang belum pernah mengikuti jalan tarikat justru dipanggil dan mendapat kehormatan sebagai satu-satunya tamu yang dibaiat oleh Kyai Mu’thi, Sang Mursyid Akbar. (hal. 147). Peristiwa yang disebut-sebut sebagai titik awal perjalanan spiritual Gus Ainu.
Kejadian tersebut terjadi beberapa saat setelah Gus Ainu pulang dari studinya di Yogyakarta.
Seolah membenarkan kesan pertama saya, cerita dalam novel ini, menurut saya, seolah sebatas media. Poin utama dari buku ini justru pesan-pesan tasawuf, terutama yang tertulis dalam kitab al Hikam. Pembaca diajak untuk menelusuri laku hidup para sufi dalam bentuk narasi.
Sebagai sebuah media pembelajaran tasawuf, menurut saya, buku ini sangat baik. Pembaca diajak untuk memahami apa itu tasawuf tanpa harus selalu mengerutkan kening. Kitab tasawuf yang, menurut saya, berat bisa disampaikan secara ringan dalam bentuk narasi. Cara penceritaannya juga mengalir lancar, membuat pembaca tidak mau meletakkan jika belum khatam.
Sayangnya, ada bentuk pengulangan yang membuat pembaca, khususnya saya, penasaran namun tidak dituntaskan. Seperti: urgensi angka empat belas. Angka ini sering disebut, baik dalam menyebut kegiatan mujahadah papatwelasan (empat belasan) karena rutin diadakan setiap tanggal empat belas, penulisan tanggal beberapa kejadian penting, maupun jam. Bahkan ada juga yang sampai menyebut menit. Contoh dalam novel: 14 Agustus, 14 menit sebelum check out dari hotel. (hal. 177).
Sikap kuat bagai karang seolah memang ingin ditonjolkan dalam karakter Gus Ainu, tokoh utama novel ini. Pun demikian, hal ini menjadikan pembaca tidak bisa larut dalam emosi tokoh-tokoh novelnya. Padahal, emosilah salah satu nilai lebih dari sebuah cerita.
Konflik batin tokoh protagonis, menurut saya, tidak teriris sempurna. Sebaliknya, tidak ada sosok antagonis yang membuat pembaca terbawa ikut memusuhinya. Sebenarnya ada sosok Kyai Zulkifli dan keluarga yang dinarasikan antagonis. Namun, klimaks peristiwa “kejahatan”-nya kurang terasa. Segala sesuatunya seolah mengalir begitu saja, tanpa terencana.
Pilihan ini mungkin karena rasa hormat sang penulis terhadap dunia pesantren. Selain itu, bisa juga untuk mengurangi kontroversi.
Sebagai karya fiksi, sebuah cerita tentu akan lebih mengena jika pembaca diajak untuk membayangkan peristiwa-peristiwa tersebut seolah nyata. Misalnya, memberikan penanda waktu dan tempat.
Peristiwa besar seperti reformasi untuk menandai tahun 1998, atau bisa juga peristiwa lain, jika tidak ingin menyebut langsung tahun. Setting tempat dan penamaan juga sebaiknya disesuaikan. Memang membutuhkan waktu dan tenaga untuk melakukan riset, tapi hal-hal kecil seperti ini diperlukan untuk mendekatkan cerita dengan pembacanya.
Beberapa salah ketik juga masih terjadi, bahkan salah menuliskan nama. Misalnya, salah menuliskan nama “Kyai Muhyidin”, padahal kalau melihat kronologi ceritanya, harusnya “Kyai Mu’thi” (paragraf 3 halaman 148).
Terlepas dari semua hal yang masih bisa terus diperbaiki dan ditingkatkan, novel ini memberikan kita khazanah baru. Mengajarkan tasawuf melalui cerita. Sejalan dengan kebutuhan kita saat ini yang menginginkan adanya moderasi dalam beragama. Beragama secara indah dan damai. Menunjukkan karakter mulia orang-orang beragama.
Beberapa tahun lalu, sekitar tahun 2009 kalau saya tidak salah, ada seorang teman yang ingin tahu tentang tasawuf secara ringkas namun tidak sanggup jika harus membaca buku tasawuf yang menurutnya susah dipahami. Jika ia bertanya saat ini, “Kyai Tanpa Pesantren” adalah buku yang akan saya rekomendasikan pertama kali.
Wakhid Hasyim, Guru SKI MAN 1 Yogyakarta
_______________
Semoga artikel Kyai Tanpa Pesantren, Laku Sufi dalam Sebuah Karya Fiksi ini memberikan manfaat dan barokah untuk kita semua, amiin..
simak artikel terkait Kyai Tanpa Pesantren, Laku Sufi dalam Sebuah Karya Fiksi di sini
kunjungi juga channel youtube kami di sini