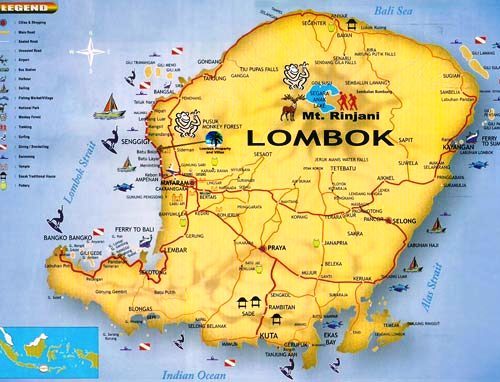Umat Islam pasti sangat mengerti tentang istilah “kafir”, karena kata kafir ini merupakan kata yang lazim diucapkan pada satu kelompok ke kelompok yang lain, terutama dengan niat untuk merendahkan, menyalahkan, atau menyesatkan.
Bagaimana sebenarnya kata kafir ini dikonseptualisasi dalam Alquran? kalau kita perhatikan secara semantik atau seluk-beluk makna mengenai kata kafir, kata kafir biasanya diartikan sebagai tirai dan tutup. Itulah sebabnya cover buku itu disebut dengan cover, karena cover itu menutupi isi dari buku tersebut. Sarung pedang juga disebut sebagai “kafir”, karena sarung itu berfungsi untuk menutup pedangnya.
Bahkan dalam Alquran, para petani juga disebut sebagai “kufar”, sementara kata kufar ini merupakan bentuk jamak dari kata kafir. Misalnya dalam surat al-Hadiid ayat 20, Allah berfirman, “…kamatsali ghaitsin a’jabal kuffaara nabaatuhu…” (seperti hujan, yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani). Kenapa para petani disebut sebagai kafir? Karena para petani itu menutup benuh dengan tanah.
Dengan demikian, boleh dikata bahwa kata kafir secara langsung merujuk pada makna tutup atau tindakan menutupi. Orang yang tertutup hatinya, artinya tidak bisa menangkap kebenaran, tidak bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah, maka ia juga bisa disebut sebagai orang yang kafir.
Tapi kalau kita memperhatikan ayat yang lain dalam Alquran, kita akan memahami bahwa kata “kafir” merupakan antonim dari “iman”. Yaitu orang-orang yang mengingkari Allah dan ayat-ayatnya. Allah berfirman “limatakfuruna biayatillahi wa antum tashadun” (mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, sementara kamu menyaksikan kebenaran ayat-ayat Allah itu).
Bahkan bila kita melihat ayat yang lain, kata kafir juga menunjuk kepada orang yang tidak mensyukuri terhadap rahmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah. Alquran menyebutkan “lainsyakartum laazidanaqum wa lainkafartum idha lasyadid”, (orang yang mengingkari ayat-ayat Allah adalah orang-orang kafir, yaitu orang yang tidak mengakui ayat-ayat Allah, bahwa alam semesta ini merupakan ayat-ayat Allah).
Lebih dari itu, ada juga ayat di dalam Alquran yang menyatakan bahwa orang yang berputus asa adalah juga bisa disebut sebagai orang kafir. Allah berfirman yang artinya “janganlah berputus asa, sesungguhnya orang yang berputus asa itu adalah orang-orang yang kafir”.
Di ayat yang lain disebutkan, bahwa orang yang kafir itu adalah orang yang dholim. Orang-orang yang melakukan ketidakadilan, atau orang-orang yang melakukan penindasan, juga orang-orang yang membiarkan orang miskin berada di garis kemiskinannya. Padahal dia seorang pemimpin.
Pertanyaan lebih lanjut, bagaimana cara kita menyikapi orang-orang kafir ini? Dalam Alquran juga disebutkan, “jangan sampai orang-orang yang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai para pemimpin mereka”. Jika kita mengartikan kata kafir ini sebagai orang yang mudah berputus asa, maka kita tidak boleh mengangkat seorang pemimpin yang pesimis, yakni seorang pemimpin yang tidak optimis dan mudah berputus asa, seorang pemimpin yang selalu mengirimkan pesan ke tengah masyarakat tentang keputusasaan dan bukan tentang sebuah pengharapan.
Bila kita mengartikan kata kafir adalah orang-orang yang dholim, maka orang-orang beriman tidak boleh mengangkat seorang pemimpin yang dholim. Yakni seorang pemimpin yang rekam jejaknya suka melakukan kekerasan, suka melakukan kedholiman, dan membiarkan ketidaadilan terjadi di tengah-tengah masyarakat.
Dengan demikian, kata kafir tidak merujuk pada satu individu secara terbatas, tetapi kata kafir dalam Alquran memiliki makna yang luas. Seperti kepada orang yang berputus asa, kepada orang yang dholim, kepada orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, siapa saja di antara mereka, maka sesungguhnya dia merupakan orang-orang kafir.
Kalau dia seorang pemimpin, kemudian dia dijadikan sebagai pemimpin, padahal dia kafir, maka pasti akan merugikan rakyatnya. Bukan hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga merugikan orang lain. Sehingga, kita harus mengangkat seorang pemimpin yang optimis, bukan pemimpin yang pesimis. Kita juga harus mengangkat seorang pemimpin yang adil, bukan pemimpin yang dholim. Seorang pemimpin yang memiliki kepedulian sosial, bukan pemimpin yang apatis terhadap problem-problem kemanusiaan yang ada di sekitar kita.
(Rohmatul Izad, Alumni Pascasarjana Ilmu Filsafat UGM Yogyakarta)