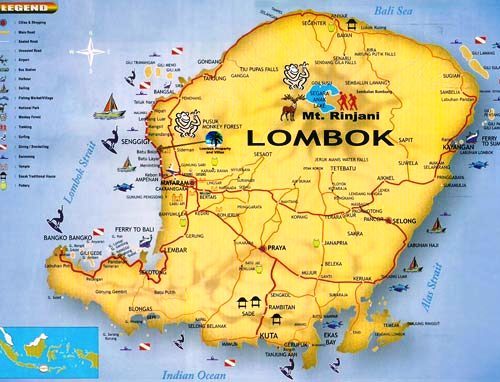Pertama kali saya ketemu Gus Dur tahun 1979 di Muktamar NU Semarang (Muktamar NU ke 26). Ketika itu Gus Dur belum masuk di pengurus NU, sedangkan saya sudah mewakili utusan NU Cabang Malang. Di dalam Muktamar ke 26 itu, Gus Dur diangkat menjadi wakil katib PBNU. Setelah pertemuan di Semarang, sangat sering Gus Dur ke Jawa Timur, karena memang Jawa Timur adalah pusat potensi NU, dan sering juga menginap di Malang karena Gus Dur mengajar Islamologi di Yayasan Kristen GKJW (Gereja Kristen Jawi Wetan) yang berlokasi di Sukun Kota Malang.
Saya mendampingi dan mengikuti Gus Dur selama 20 tahun penuh, mulai tahun 1979-1999, ketika Gus Dur menjadi Presiden Republik Indonesia. Setelah menjadi Presiden RI Gus Dur Fokus memimpin PKB dan saya menjadi Ketua Umum PBNU di Muktamar Lirboyo (Muktamar NU ke 30). Dalam waktu 20 tahun saya mengikuti betul jalan pikiran Gus Dur, baik masalah ke-NU-an, Ke-Islam-an Indonesia, Ke-Islam-an global dan situasi politik Internasional.
Menurut pandangan saya, di dalam membawakan Islam baik di Indonesia maupun di dunia, Gus Dur lebih mengetengahkan pendekatan filosofi religius, etika religi, kemanusiaan (humanity) dan budaya. Sedikit saja Gus Dur menggunakan Ilmu Fikih sebagai bagian dari syariat, karena yang diketengahkan bukan legal syariatnya tetapi “hikmatu al-Tasyri”-nya dan “maqhashidu al-Tasyri”-nya.
Dalam pendekatan etika religi, Gus Dur sangat egaliter menempatkan manusia dalam posisi yang setara, terlepas dari agama yang dipeluknya. Sehingga hubungan etis ini menjadi sangat cair antara Gus Dur yang Muslim dan non-Muslim bahkan yang atheis sekalipun.
Dalam hal pendekatan kemanusiaan, Gus Dur sangat mementingkan martabat dan kebutuhan asasi dari manusia itu sendiri, sebagai bentuk dari kasih sayang Allah kepada seluruh mahluknya. Dalam hal ini, kemanusiaan diletakkan pada “rahmaniah”-nya Allah sedangkan “rahimiah”-nya Allah dikhususkan untuk kaum Muslimin di akhirat. Adapun pandangan Gus Dur terhadap budaya dapat dikatakan sebagai wujud kongkrit dari filosofi, etika dan kemanusiaan itu sendiri.
Dari pola pemikiran dan pandangan keagamaan/keislaman seperti ini, pastilah akan membuat mayoritas umat islam di Indonesia menjadi kaget dan terheran-heran. Karena mainstream umat Indonesia bertumpu kepada masalah tauhid dan masalah fikih yang hitam-putih. Apalagi buat mayoritas umat Muslim Indonesia yang suka bertengkar di bidang furu’ akan semakin sulit memahami pola pikiran Gus Dur.
Ditambah lagi, semenjak tahun 2002 (pasca reformasi) banyak aliran keras yang tidak hanya bertikai sesama islam tetapi merembet kepada saling membid’ahkan dan saling mengkafirkan. Dalam fenomena ini akan semakin jauh jarak pandangannya. Tidak heran kalau kemudian secara parsial ada umat islam yang mengatakan bahwa Gus Dur sesat karena memang berbeda cara pandangnya. Gus Dur tidak pernah merasa keberatan apa-apa untuk dikatakan sesat, karena Gus Dur sangat mengetahui hal tesebut berangkat dari pemikiran legal formal yang hitam putih. Tetap saja Gus Dur bersilaturahmi kepada semua pihak bahkan tokoh tokoh yang tidak setuju pndptnya, karena menurut gus dur sendiri kelompok yang tidak setuju merupakan sesuatu yang logis saja sebagai akibat dari sistem pemikiran.
Posisi saya selama 20 tahun bersama-sama dan mendampingi beliau bertindak sebagai penjelas dari pikiran dan ucapan ucapan gusdur yang sulit difahami oleh masyarakat awam misalnya: tentang “Assalamu‘alaikum” diganti dengan selamat pagi, Gus Dur mengajar di lembaga pendidikan Kristen, menganggap semua agama sama saja serta toleransi budaya yang sangat tinggi dan sebagainya. Pada umumnya warga Nahdliyin mulai mengerti sekalipun kadang optimal dan kadang tidak optimal. Tetapi tetap saja masyarakat NU mencintai Gus Dur bukan semata karena pemikirannya tapi karena cucu Syaikh KH. Hasyim Asy’ari dan putra sulung dari KH. Wahid Hasyim. Hal ini tentu berbeda dengan orang yang berpendapat sama tetapi bukan trah Tebuireng.
Gus Dur sejak waktu yang lama sudah bercita-cita menjadi presiden RI dan Gus Dur yakin kalau itu akan terjadi. Oleh karenanya di dalam diri Gus Dur ada dua hal yang bisa dibedakan sekalipun tidak bisa dipisahkan. Pertama: Pemikiran keagamaan dan universalitasnya dan kedua: strategi politis untuk mencapai jenjang presiden.
Untuk pemikiran, sudah saya sampaikan di atas,dan untuk strategi menjadi presiden haruslah mempunyai dukungan dari kaum nasionalis Indonesia. Secara global diperlukan kedekatan ke dunai Katolik (Vatikan) dan beberapa tokoh yang dekat kekuatan Israel, misalnya: dengan masuk ke Yayasan Simon Peres dan sebagainya. Hal-hal yang strategis ini saya tidak ingin mencampuri Gus Dur terlalu dalam karena bisa mengganggu tujuan dan saya pun tidak pernah menjelaskannya kepada masyarakat Nahdliyin.
Gus Dur telah berjasa besar kepada Nahdlatul Ulama, utamanya di bidang perluasan wawasan sehingga dalam empat tahun menjabat sebagai wakil katib PBNU, Gus Dur mempersiapkan Khittah 1926 yang kemudian berhasil digolkan di Muktamar Situbondo tahun 1984. Khittah 1926 berisi:
a) Penyambungan wawasan keagamaan dan wawasan kebangsaaan. Hal ini diperlukan agar maqhasidu al-Tasyri yang diperjuangkan NU dapat dimasukkan dalam mengisi negara melalui bahasa nasional.
b) Pemisahan NU dari partai politik (ketika itu PPP), agar posisi NU murni pada civil society tidak terkooptasi dengan pemikiran politis yang berpijak kepada untung rugi, kekuasaan dan politisasi. Sehingga NU dapat secara murni berbicara tentang kebatilan dan kebenaran serta kemaslahatan umat tanpa memandang golongan-golongan politik.
c) Penetapan pancasila sebagai asas perjuangan negara dan akidah Ahlusunnah wal jamâ’ah (al-Nahdliyah) sebagai landasan keagamaan.
d) Menggalang persaudaraan muslimin seluruh dunia utamanya yang berfaham Ahlussunnah wal jamâ’ah.
e) Bergerak di bidang pengembangan sosial (Mabadi Khairo ummah) baik di bidang pendidikan, pesantren, ekonomi, budaya, serta politik kebangsaan bukan politik kepartaian.
Ide-ide strategis dari Gus Dur ini tidak gampang diterima oleh mainstream warga Nahdliyin pada waktu itu yang masih mempertetangkan antara Islam dan Pancasila. Sekalipun sudah dijelaskan bahwa strategi itu sangat perlu untuk Nahdlatul Ulama, tetap saja para ulama meminta justifikasi legal formal di dalam Qur’an dan hadis serta sirah nabawiah. Terjadilah perdebatan sengit antar ulama NU dalam Munas Alim Ulama setahun sebelum muktamar 1984.
Akhirnya, KH. Ahmad Siddiq yang menjembatani pemikiran strategis ini dengan pendekatan legal formal, utamanya dengan mengambil makna dari Piagam Madinah. Ternyata di Piagam Madinah tidak menyebut istilah Negara Islam tetapi kesepakatan (referendum penduduk Madinah). Yang terpenting dari isi Piagam Madinah tersebut adalah pengisian bentuk negara dengan prinsip ajaran agama Islam.
Misalnya: persaudaran di kalangan kaum muslimin, penegakan hukum secara adil, hubungan lintas agama, pemerataan ekonomi, memegang amanat dalam berpolitik, dan kepribadian Islam dalam kebudayaan. Akhirnya disetujui konsep Khittah itu tahun 1984. Sebagai penanggung jawab dunia dan ukhra terhadap semua keputusan muktamar ke 27 di Pondok Pesantren Sukorejo Situbondo adalah KH. As’ad Syamsul Arifin (yang sekarang ini telah menjadi pahlawan nasional).
Monash University, Sydney Australia
11 Desember 2016
Penulis: KH Dr A Hasyim Muzadi, Ketua Umum PBNU 1999-2010.