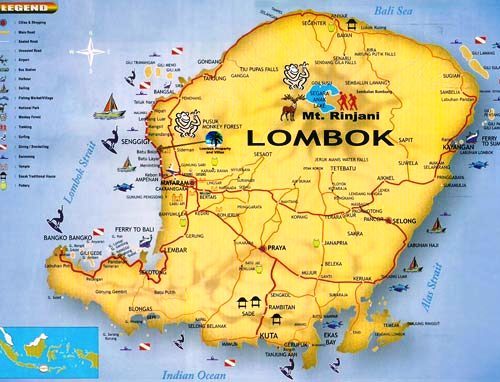Oleh Edi AH Iyubenu, wakil ketua LTN PWNU DIY.
Surat adz-Dzariyat ayat 56 sangat populer kita kenal, “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaKu.” Inilah tujuan kita diciptakan di dunia ini, sebelum dikembalikan lagi kepadaNya, untuk mempertanggung jawabkan segala amal perbuatan kita selama di dunia dan menerima balasan dariNya–termasuk tentunya peribadatan setiap kita.
Wajar saja, bahkan lazim dipandang keutamaan, bila sebagian kita berlomba-lomba dalam beribadah, dengan pelbagai caranya, dari yang wajib sampai sunnah. Ada yang menjadikan shalat pada waktunya (ash-shalatu ‘ala waqtiha) sebagai jalan lelakunya; ada yang menjaga shalat berjamaah di masjid lima waktu; ada yang melengkapi dengan shalat rawatib dan shalat-shalat sunnah lainnya; puasa sunnah Senin Kamis dan selainnya; dzikir-dzikir yang lama dan panjang; sedekah yang dahsyat; shalwatan; mengaji al-Qur’an; mendawamkan ngaji surat al-Mulk, al-Waqi’ah, al-Kahfi, dll., dll.
Semua itu adalah jalan-jalan yang memungkinkan untuk kita pilih dalam mendedikasikan diri menyongsong perintah ayat beribadah tersebut.
Mari, di bagian berikutnya, saya ingin menyodorkan refleksi yang barangkali berharga untuk seturut kita pahami terkait dengan ayat di atas.
Pertama, secara ilmu tafsir al-Qur’an, kita memahami bahwa al-Qur’an tidak tepat untuk ditakwil sebelah-sebelah, sepotong-sepotong. Al-Qur’an adalah sebuah kitab suci yang padu, utuh, holistik, dan komprehensif, sebab ia adalah pedoman hidup (hudzan lil muttaqin).
Kedua, memahami al-Qur’an secara sebelah-sebelah, sepotong-sepotong, berisiko membuat pemahaman kita bermodel “kacamata kuda” (mohon maaf untuk istilah ini). Mungkin saja model begitu tak salah, tapi dampaknya kepada cara pandang kita kepada realitas kehidupan, kemajemukan, kemanusiaan, keliyanan, amat tak sepele. Kita rawan terjebak pada pandangan satu arah belaka –serupa kacamata kuda yang tak memungkinkan sang kuda bisa memandang sisi kanan, kiri, dan belakang karena matanya hanya mengarah ke depan.
Ketiga, faktanya, al-Qur’an sebagai sumber hukum Allah memiliki begitu banyak dan luas tahap-tahap, fase-fase, hierarki-hierarki, pada suatu hukum (termasuk hukum beribadah), yang mencerminkan ketidakmanunggalan suatu hukum. Dengan kata lain, wujud tindakan kita terhadap suatu hukum al-Qur’an, seperti beribadah tadi, mengandung banyak kemungkinan pilihan bentuk ejawantahnya. Coba ayat tadi sandingkan dengan, misal, surat al-Haj 78: “Dan sekali-kali tidaklah menjadikan untuk kamu dalam agama sedikit pun kesempitan.” Juga surat at-Taghabun 16: “Maka bertakwalah kepada Allah menurut kemampuanmu.” Apa yang bisa kita rasakan kini?
Mari kita sodorkan satu pertanyaan mendasar di konteks ayat perintah beribadah tersebut: “Bagaimana ukuran kualitas beribadah yang dimaksudkanNya dari ayat tersebut?”
Seseorang mungkin akan menyatakan bahwa beribadahlah sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya, sedahsyat-dahsyatnya; jangan malas; harus meningkat dari tahun ke tahun. Ini pandangan umum yang lazim kita dengar dari para khatib dan penceramah, bukan?
Apa yang berdenyar di kepala kita menyimak taushiyah begitu? Tentulah setiap kita lalu memiliki citraannya masing-masing serta rencana-rencananya kemudian dan pula ejawantah-ejawantahnya lebih lanjut. Tak lupa, kondisi dan kahanan privat setiap kita.
Di antara sekian citraan, rencana, dan ejawantah tersebut, yang manakah yang paling sesuai dengan maksudNya dari ayat tersebut?
Saya ingin menyodorkan beberapa riwayat sahih ini dalam konteks pertanyaan tersebut.
Pertama, Sayyidah Aisyah Ra meriwayatkan: “Nabi Saw tidak diperhadapkan kepada dua pilihan kecuali memilih yang mudah selama itu bukan dosa.” (HR Muslim).
Kedua, Suatu ketika Rasul Saw memasuki rumah istri beliau, sayyidah Zainab Ra dan mendapati sebuah tali yang dibentangkan di antara dua tiang. “Tali apa ini?” tanyanya. Dijawab, “Ini tali milik Zainab yang digunakannya untuk pegangan ketika dia letih berdiri untuk shalat.” Rasul Saw lalu bersabda: “Tidak demikian seharusnya. Lepaskan tali itu. Hendaklah seseorang di antara kamu shalat dalam keadaan semangat, kalau dia jenuh (capek) hendaklah ia duduk (berhenti).” (HR Muslim).
Ketiga, Nabi Saw menyaksikan salah satu istrinya, Sayyidah Juwairah Ra, berdzikir sehabis shalat Subuh hingga Dhuha. Nabi Saw bertanya, “Apakah engkau terus dalam keadaanmu ini (duduk berdzikir di sini) semenjak kutinggalkan tadi?” Juwairah mengiyakan. Nabi Saw lalu bersabda, “Aku telah mengucapkan dzikir bersamamu tadi dengan empat kalimat sebanyak tiga kali. Seandainya itu ditimbang dengan apa yang engkau ucapkan hari ini, nscaya ia tertimbang setara dengannya….” (HR Muslim, Daud, Nasa’i, dan Ahmad).
Keempat, Sejumlah sahabat Nabi Saw telah merencanakan untuk berpuasa sepanjang tahun, beribadah sepanjang malam, dan enggan menikah demi mengejar intensitas dan kualitas beribadah, Nabi Saw menegur mereka dengan mengatakan, “Sungguh, demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan bertakwa kepadaNya, tetapi aku berpuasa di suatu hari dan tidak berpuasa di lain hari, aku bangun malam dan juga tidur, dan aku menikah. Siapa yang tidak menyukai jalan hidupku (sunnahku) maka dia bukan bagian dari golonganku.” (HR Bukhari).
Jika semua orang Islam ditanya, siapakah sosok yang paling otoritatif kebenarannya dalam menafsirkanal-Qur’an? Tiada lain semua akan serentak menjawab: Rasulullah Saw. Kita semua sepakat mutlak. Itu artinya pengejawantahan ayat-ayat al-Qur’an yang palng nyata dan benar untuk kita pelajari, pahami, dan ikuti ialah Rasul Saw.
Begitupun dalam ihwal praktik beribadah kepada Allah; ejawantah ayat di atas. Kini apa gerangan yang kita rasakan dari riwayat-riwayat sahih tersebut yang mencerminkan pandangan dan sikap Nabi Saw, sebagai sang penafsir al-Qur’an yang terbenar?
Walhasil, bisa saja ejawantah kesungguhan dan kedalaman kita dalam beribadah kepada Allah, dalam memenuhi panggilan ayat di atas, terekspresikan dalam pelbagai wujud yang amat luas, tak terbatas. Dan, spirit dan nilai yang paling penting, semuanya merupakan bagian dari cara kita meneladani ibadah ala Rasulullah Saw, bagian dari jalan hidupnya Saw, bagian dari sunnahnya. Inilah yang tadi saya maksudkan sebagai kenyataan bahwa “hukum Allah memiliki begitu banyak dan luas tahap-tahap, fase-fase, hierarki-hierarkinya”.
Jadi, ekspresi kepatuhan kepada hukum Allah dalam beribadah ini sama sekali tidak perlu dibakukan monoton, tunggal, sehingga rawan mendorong kita menegasi ekspresi-ekspresi liyan yang tak sama dengan diri kita. Mungkin saja seseorang istiqamah shalat jamaah lima waktu di masjid, sebagaimana mungkin pula seseorang lain bisanya istiqamah shalat jamaah di masjid waktu Maghrib, Isya, dan Subuh saja karena di siang hari ia berbisnis yang menyulitkannya untuk bisa on time ke masjid, atau mungkin pula seseorang lain tak selalu bisa begitu karena pekerjaannya sebagai driver atau marketing menyulitkannya untuk selalu siap sedia setiap jelang waktu shalat, atau mungkin pula seseorang sama sekali tak bisa jamaah di masjid karena menunggui ibunya yang sakit menahun, dan lain sebagainya.
Apa pun itu ejawantahnya, dalam kahanan kita masing-masing, sepanjang bersumber dari ketulusan iman di hati, insya Allah sama luhurnya, telah sama ittiba’ sunnahnya Saw.
Tentu narasi ini tidak tepat sama sekali untuk dijadikan pembenar bagi kemalasan kita untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Jangan dipelintir. Seyogianya, buat setiap kita, cukuplah “walahu ‘alimun bidatis shudur, Allah Maha Tahu apa yang ada di dalam hati” menjadi pengingat rohani terdalam untuk tidak membenar-benarkan segala yang tidak benar, sepertikemalasan diri. Allah Maha Tahu.
Narasi ini penting kiranya untuk dijadikan refleksi tiap kita dalam memandang kemajemukan manusia dan kahanannyamasing-masing, yang mustahil seragam sebagaimana ideal dan kahanan Anda sendiri. Sehingga segala ejawantah ibadah liyan yang tak sama dengan ejawantah ibadah Anda tak perlu dipandang sebagai kekurangan, kelemahan, apalagi kehinaan.
Biarkanlah liyan beribadah dengan maqam dan kahanannya, yang niscaya tak pernah benar-benar kita tahu kondisi khasnya, sebagaimana kita sendiri ingin dihargai dalam menjalankan cara dan ekspresi ibadah kita kepadaNya.
Lalu mari saling mendoakan saja: semoga semuanya bernilai benar di sisiNya, diterimaNya, dan dirahmatiNya. Amin.
Jogja, 22 Desember 2019