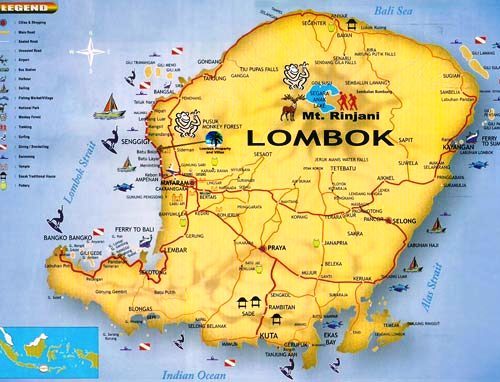Saat ini (lebih tepatnya sejak setahunan lalu) ramai perdebatan masalah “pemulangan” ISIS atau mengajak ISIS ke Indonesia. Di medsos tidak kalah ramai, apalagi setelah muncul video dari BBC News Indonesia yang berisi wawancara wartawan luar negeri dengan seorang wanita yang katanya “terseret” kasus ISIS.
Diskusi semakin hangat saat Jokowi secara pribadi tidak setuju mereka “dipulangkan”. Selanjutnya politisi PKS, Nasir Jamil dan politisi PKB Maman Imanulhaq berdebat di stasiun televisi ditambah para pengamat yang ikut memberi sumbangsih masukan. Bagi saya, mereka yang sudah “hijrah” (entah dari negara asal manapun) dan merasa “kaffah” karena sudah berada di kekhilafahan ISIS, tidak perlu dibawa ke asalnya lagi.
Dalam perspektif hukum, Hikmahanto Juwana menjelaskan, mereka yang tergabung dalam ISIS, sebenarnya telah kehilangan kewarganegaraannya. Berdasar pasal 23 UU tahun 2016 huruf (d) dan (f). Namun hemat saya, alasan Hikmahanto ini bisa dibantah karena tidak ada negara manapun yang mengakui bahwa khilafah ISIS adalah sebuah negara, apalagi masuk PBB. Walhasil, khilafah ISIS ini ilegal atau tidak diakui mirip Sunda Empire atau Kraton Agung Sejagat. Bedanya, ISIS tega membunuh, memperkosa dan berbuat sadis yang lain dengan lambaran pemahaman agama yang picik. Sedang yang kedua yang kita anggap guyonan saja.
Pertanyaan menggelitik, apakah benar yang sedang diramaikan dan diperdebatakan untuk dipulangkan itu betul ISIS yang WNI? Secara hukum, Indonesia menganut asas ius soli, yakni kewarganegaraan ditentukan dari tempat kelahiran. Kalau asas itu diterapakan, tentu butuh bukti sebagai penunjuk bahwa dia lahir di Indonesia. Kesulitan akan muncul kalau seseorang itu sudah di luar negeri (LN) lalu mengaku lahir di Indonesia, tanpa menunjukkan bukti. Demikian pula adalah ketergesaan, kalau ada seseorang yang ada di LN yang wajahnya mirip wajah ala orang Indonesia, lalu mengaku sebagai WNI, tanpa menunjukkan bukti. Asal tahu, ada orang Indonesia yang pindah kewarganegaraan, atau bisa jadi dia dari Malaysia atau Suriname. Demikian pula seseorang di LN yang berwajah ala Indonesia dan bisa ngomong dengan bahasa Indonesia, lalu mendaku sebagai WNI, tanpa menunjukkan bukti. Tentu semua pengakuan di atas tidak bisa dijadikan pegangan. Satu-satunya cara seseorang yang berada di LN dan mendaku sebagai WNI harus menunjukkan tanda bukti paspor.
Lalu kalau tidak punya paspor, karena telah dibakar dan dibuang di tong sampah sebagai wujud penghinaan, apakah imigrasi yang malah datang ke berbagai negara yang katanya ada WNI yang ISIS. Selanjutnya menanyai satu persatu identitas mereka dan seterusnya. Semoga saja dalam catatan imigrasi mereka memang bukan WNI. Tapi kok menjadi ribet, pergi dari negara asal karena benci bekelomoh (berbalut) agama dengan tatanan yang telah disepakati, lalu negara harus mengurusnya. Apa tidak lebih baik negara mengurus TKI yang ada problemnya saja. TKI jelas lebih bisa diperhatikan karena mereka pergi untuk membiayai keluarganya yang ada di Indonesia.
**
Ada “pejuang” HAM yang langsung komentar bahwa mereka harus dipulangkan. Padahal belum jelas siapa mereka itu, apakah WNI. Kalau masalah kemanusiaan secara umum, para “pejuang” HAM ini dengan alasan kemanusiaan bisa membantu material apa yang dibutuhkan mereka. Pun demikian, kalau alasan kemanusiaan, silakan bantu para pencari suaka yang ada di Indonesia. Terbetik dalam benak saya, kalau pencari suaka yang ada di Indonesia itu mengaku sudah menjadi WNI kira-kira bagaimana jawaban para “pejuang” HAM? Pasti akan meminta bukti, walhasil, bukti adalah penting.
Ada juga pengamat terorisme Al Chaidar yang mengatakan agar ISIS dipulangkan saja, karena kalau tidak dipulangkan akan lebih radikal dan akan menganggap pemerintah kafir dan zalim. Jawaban saya gampang saja, kalau ISIS mau lebih radikal yang silakan saja agar berurusan dengan negara yang ditempati. Kalau masalah cap kafir dan zalim, ya wajar, karena memang mereka pergi atau sowan ke daerah yang dikuasai ISIS karena menganggap negara asal adalah kafir dan taghut.
Sedangkan pengamat yang teman saya di HTI, Harits Abu Ulya (nama alias), Dia bilang bahwa pemerintah tak perlu khawatir untuk memulangkan ISIS untuk selanjutnya mengintegrasikan dengan masyarakat. Namun yang aneh di alinea selanjutnya Harits justeru bilang kalau pemerintah gagal mengintegrasikan, akan menjadi bom waktu. Kalau demikian kesimpulan Harits, ya lebih baik tidak dipulangkan saja. Karena memang “ngopeni” mereka sama dengan “ngopeni” anak kucing rimba atau anak serigala, sedikit yang bisa “lulut” atau “jinak”, tapi lebih banyak sulit diatur setelah besar.
“Nalar” orang ekstrem itu “bergradasi”, kalau asalanya teroris tukang ngebom, lalu sulit mengebom, dan ada sedikit kesadaran, maka jadinya dia meninggalkan hobi ngebom, lalu ikut yang lebih “lunak” tapi masih searah, semisal ikut HTI. Kalau ikut HTI tidak cocok, maka ikut kelompok lain yang masih sealur “nalarnya”. Sangat mungkin akan ikut aliran yang sangat suka mengkafirkan, membidahkan dan mensyirikkan. Sangat jarang yang “loncat gradasi” semisal dari teroris kemudian ikut kelompok moderat, apalagi ikut NU, kalau ada, pasti spesial. Apalagi meloncat ikut “abangan” adalah hampir mustahil.
Terakhir, teroris, bandar narkoba, dan koruptor kelas kakap adalah sejenis, tapi beda dalam hal tertentu. Semuanya membahayakan kehidupan berbangsa.
Tulisan ini sebagai masukan bagi yang berkepentingan, silakan dikritik dan diberi masukan….
Penulis: Ainur Rofiq Al Amin, dosen UIN Sunan Ampel Surabaya