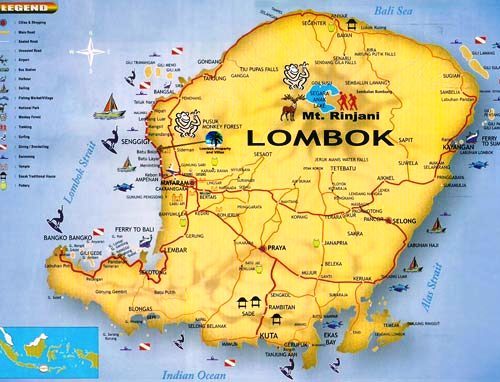Tiga hari sesudah meninggalnya ayahku, Mbah Sholeh Qosim rawuh ke rumah kami. Takziyah. Beliau minta maaf, tidak dapat hadir saat pemakaman karena ada udzur. Saya jadi jengah. Mbah Sholeh yang begitu sepuh memaksakan diri menempuh perjalanan jauh dari Sidoarjo ke Rembang hanya untuk menghiburku. Dan beliau minta maaf? Sedangkan aku sendiri tak tahu, bagaimana harus melahirkan rasa terima kasihku atas penghormatan dan kasih-sayang beliau kepadaku.
Aku masih galau berat, belum mampu bercakap-cakap secara normal. Dan Mbah Sholeh tahu. Beliau mamandangiku lekat-lekat dalam beberapa jurus keheningan.
“Susah, Gus?”
Aku mengangguk lemah,
“Inggih”.
Mbah Sholeh tersenyum. Dan, kau tahu, senyum –apalagi dari ruh seorang Mbah Sholeh Qosim– adalah kekuatan penghibur.
” Ya pantas… namanya kehilangan…”, kata beliau. Aku cuma menunduk memandangi gelas teh. Gambar-gambar di benakku mengerambang. Tak menentu.
“Tapi sampeyan siap-siap ya, Gus”, Mbah Sholeh melanjutkan, “kesusahanmu hari-hari ini belum kesusahan yang sesungguhnya. Aku dulu juga ngalami kok, waktu ditingal bapakku”.
Beliau menghela napas, seperti mengumpulkan kenangan.
“Susahmu hari-hari ini cuma susah karena kehilangan. Akan berlalu dengan waktu. Susah yang sesungguhnya baru akan datang nanti paling tidak setelah empat puluh hari. Yaitu saat sampeyan terpaksa harus mengurusi wadhifah-wadhifah (tanggung jawab-tanggung jawab) yang diwariskan abahmu”.
Lahumal Fatihah.
Penulis: KH Yahya Cholil Staquf, Katib Aam PBNU.