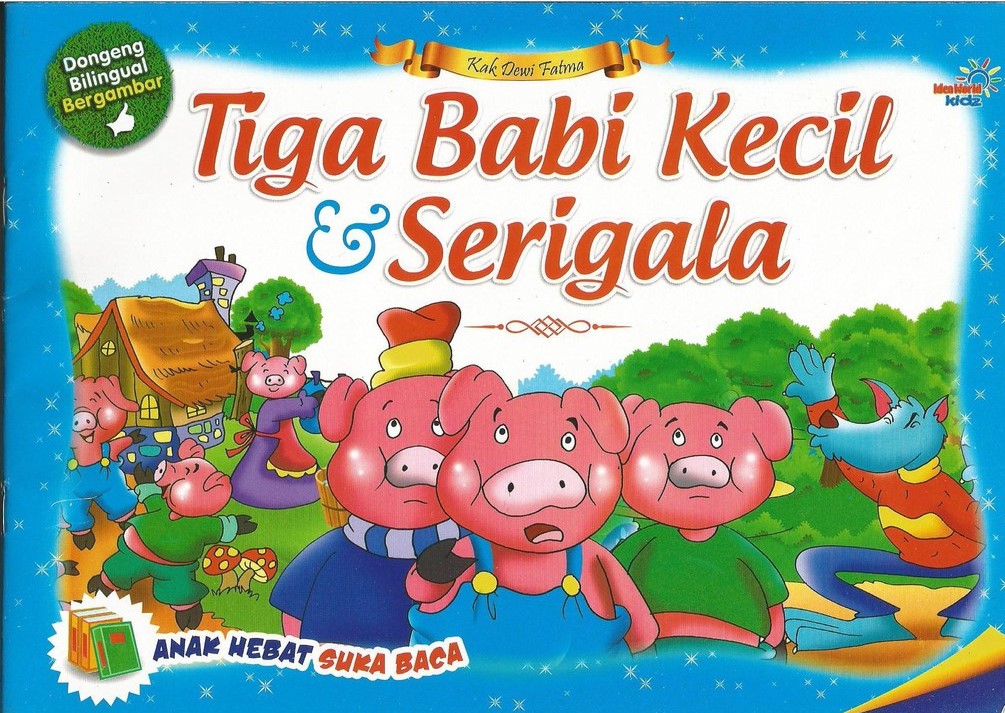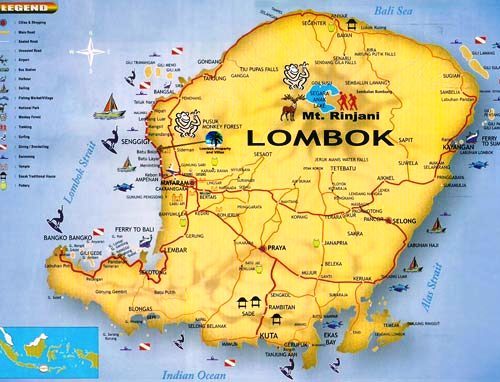Oleh Edi AH Iyubenu, Wakil Ketua LTN PWNU DIY.
Saya menyimak obrolan seorang kawan, Lya Fahmi, tatkala mengantar anaknya melihat-lihat buku anak di sebuah toko buku. Dilihatnya seorang bapak meyodorkan sebuah buku kepada anaknya yang sedang melihat-lihat buku-buku anak dan mengatakan bahwa itu buku bagus. Berselang detik kemudian, ia membatalkan ucapannya dengan mengatakan bahwa buku tersebut tidak bagus (baca: seketika menjadi jelek) karena di dalamnya ada gambar babi. Ya, babi.
“Babi itu haram,” ujarnya.
Sebagaimana Lya Fahmi yang terkesima, saya pun terperagah atas kenyataan tersebut. Gara-gara ada gambar babi di dalam buku bergenre anak tersebut, seketika remuklah kualitas seluruh kandungan buku itu. Betul, landasannya adalah babi haram (dalam Islam ada dalilnya). Sehingga ia lalu menganggap itu buku berbahaya bagi anaknya karena adanya fator kaharaman tersebut, walau hanya sebuah gambar.
Betapa malangnya menjadi babi; betapa malangnya mejadi buku yang ada gambar babinya. Maaf, bercanda.
Saya lalu membayangkan, bagaimana bila di suatu kelas Biologi, anak ini diajari tentang organ-organ reproduksi. Gambar-gambar kelamin pun akan dijembarkan sebagai bagian dari alat-alat reproduksi. Apakah itu pun akan didapuknya haram? Karenanya harus dihindari? Sebab berbahaya bagi anaknya? Tapi, apa betul kelamin itu haram? Gambarnya?
Anda renungkan sendiri saja.
Dalam riwayat nyata lain, ada seseorang yang mengatakan bahwa Ovo itu haram. Alasannya karena itu uang digital (tidak ada benda fisiknya semaca uang material) dan katanya lagi perusahaan Ovo mengoperasikan dananya, investasinya, dan sekaumnya, ke perusahaan-perusahaan yang tak terjamin kehalalannya. Mungkin perusahaan peternakan babi lagi ini yang dimaksud. Entah dari mana itu sumbernya hingga ia menyimpulkan demikian.
Tentulah Anda juga pernah mendengar atau memiliki kerabat atau sahabat yang mengharamkan bank, kartu kredit, hingga film, musik, dan bahkan buku puisi dan fiksi macam novel (taj peduli itu Kisah 1001 Malam maupun Laila Majnun). Betul, kan?
Pada dasarnya, saya menghormati semua pandangan hukum yang dikeluarkan oleh seorang ulama, ahli fiqh, beserta orang-rang yang menggugunya. Di YuoTube, berjubellah edaran link video tentang ceramah-ceramah begituan. Dan memang itulah yang paling enak, instan, cepat, praktis, tak merepotkan untuk mikir dan berusaha belajar, untuk dikases sebagian besar kita hari ini. Lalu, atas dasar link-link itu, kita menggugunya dan menjadikannya prinsip hukum dalam hidup kita, bukan? Bahkan, acap menyiarkannya kepada orang lain, luar diri, dengan begitu meyakinkan, bahkan bernada memaksa-maksa, bukan?
Penghormatan saya pada kamajemukan pandangan hukum itu sederhana saja landasannya: (1) pada dasarnya hukum Islam itu, yang ghairu mahdhah, memang elastis, fleksibel, dinamis, karenanya mejemuk, tak terbatas, (2) ihwal kebenaran hakikinya, tak ada satu pun di antara kita yang memahaminya dengan terjamin. Kelak, Allah yang akan mengadilinya di akhirat.
Tetapi, meskipun begitu memang sifat hukum Islam, kita paham bahwa pembuat fatwa-fatwa hukum Islam hendaklah hanya orang-orang yang berkompetensi khusus. Ahli ilmu. Juga ahli rohani. Mestinya. Bukan sembarang orang, apalagi semua orang. Agar buah fatwanya menjadi holistik, kontekstual, dan berwajah bijaksana. Ini prinsip yang seyogianya kita pun memahaminya. Bukan asal menyimpulkan, memfatwakan.
Imam Ath-Thusi, salah satu ulama besar Islam dari Iran, mengatakan bahwa yang semakin cenderung hilang dari khazanah hukum Islam kita ialah dimensi batiniahnya lantaran kita cenderung mendominankan dimensi lahiriahnya. Beliau lalu memetakan bahwa syariat Islam itu mengandung dua dimensi: lahiriah dan batiniah. Keduanya mesti selalu sublim satu sama lain, saling menguatkan, sehingga wujudnya di masyarakat menjadi holistik dan berkearifan.
Begini tamsilnya.
Babi jelas haram menurut Islam. Dalilnya banyak. Sharih pula. Tiada keraguan sedikit pun lagi. Jumhur ulama menisbatkan begitu.
Keharaman babi ini karena lidzatih, yakni secara zat memang ia diharamkan oleh Allah. Selesai. Tetapi, keharaman babi ini, mari pikirkan dengan kritis, apakah juga otomatis menisbatkan keharaman mempelajarinya, entah untuk tujuan medis, lingkungan, maupun ilmu pengetahuan, dan sebagainya? Lebih ekstrem, apakah juga lantas haram hukumnya memandang babi? Atau sekadar melihat foto babi? Atau mengatakan dan menuliskan kata “babi”?
Saya kira andai kita memiliki kritisisme obyektif, mudah bagi kita untuk memahami bahwa segala kajian, pembelajaran, riset, perihal babi sama sekali tak ada hubungan logisnya dengan status keharaman zatnya tadi. Inilah aspek batiniah di balik teks dalil haramnya babi itu yang seyogianya tidak kita gebyah-uyah begitu saja menjadi keharaman pada keseluruhannya. Keharamannya menjadi logis untuk memiliki pembatasan yang jelas.
Keharaman sesuatu bukan berarti keharaman seluruhnya, mungkin sebagiannya, mungkin dalam hal pelaksanaannya, dan mungkin pula dalam hal pembelanjaannya. Begitupun sebaliknya ihwal kehalalan, begitu prinsup Ushul Fiqh-nya.
Mari kita buat analogi.
Mencuri adalah perbuatan dosa. Haram. Dikutuk oleh dalil-dalil. Keharaman perbuatan pencurian ini jelas tak sama dengan keharaman sosok pelakunya. Sang pelaku tetaplah manusia macam kita yang walaupun ia telah berbuat dosa mencuri itu, ia tak bisa divonis haram secara zat manusiawinya, seperti keseluruhannya. Mungkin saja ia akan insaf setelah menjalani hukumannya. Atau dimaafkan. Atau diberi pekerjaan yang pantas. Atau diwongke. Atau ada peran para jutawan pula di dalam keharaman perbuatannya. Atau negara. Dan sebagainya.
Jadi, keharaman selalu ada batas tegasnya yang tak boleh melibas habis semuanya tanpa pengecualiaan atau peluang untuk “terlibat” di dalamnya –tentu, yang saya maksudkan adalah keterlibatan-keterlibatan yang positif.
Jika Ovo dinyatakan haram dengan pelbagai nalar tadi, sesungguhnya itu dapat kita pahami sebagai sistem bernalar analogis (qiyashi) kepada keharaman membelanjakan uang kepada hal-hal yang maksiat dan melanggar tata cara jual beli tradisional. Jika diminta dalilnya, kedua dasar analogi itu sungguh ada dalilnya.
Coba kita cermati dengan nalar begini sekarang.
Tatkala dunia terus bergerak maju dengan perubahan-perubahan teknologinya, sebutlah salah satunya adalah sistem interaksi antarorang yang tersambung via internet, tanpa harus bersemuka, lalu di dalamnya lahir sistem jual-beli online, tanpa bersemuka, jika kita terus bersikukuh dengan tata cara jua-beli tradisional yang mesti bertatap wajah, ada barang dagangan fisik, plus akad menjual dan membeli dengan terang lisanan, tentulah kita akan ketinggalan laju perubahan dunia ini. Kita takkan kebagian apa-apa dari percaturan online ini yang semestinya kita bisa turut mengeruk banyak kesempatan dan keuntungan positif dan besar andai kita berkecimpung pula di dalamnya. Apa yang kita dapat dari dunia online niscaya lalu akan bisa kita belanjakan untuk kebaikan-kebaikan. Dan itu jelas bernilai pembelanjaan yang positif dan dibenarkan oleh banyak dalil.
Sebutlah peluang marketplace hari ini. Pasar digital ini memang tak lagi menyediakan barang lahiriah dan bersemukanya penjual-pembeli. Jika bersikap ala jual-beli tradisional, jelas ini bervonis haram karena tidak memenuhi asas itu.
Tetapi, coba renungkan, dalam jual beli tradisional pun, yang bersemuka, keharaman tetaplah ada peluangnya untuk terjadi jika ada gharar di dalamnya. Penipuan. Misal mengurangi timbangan atau menjual barang yang tak sama speknya dengan contoh barang fisik yang disepakati.
Prinsip keharaman jual-beli serupa juga berpeluang terjadi dalam perniagaan marketplace. Ada atau tidaknya pratik gharar adalah kunci bagi ada tidaknya keharaman itu.
Jika poin Anda masihlah perihal bersemukanya penjual-pembel dan adanya barang fisik yang bisa dilihat dan dipegang langsung oleh calon pembeli sebagai asa kesahihan transaksi, ingatlah bahwa prinsip ini menjadi sia-sia jika masih saja ada gharar tadi. Dapat dikatakan bahwa dua pola tadi hendak menggaransikan tiadanya praktik gharar. Begitu, kan?
Di marketplce pun seyogianya prinsip yang sama bisa dipakai. Sepanjang tidak ada gharar pada spek barang sesuai dengan fotonya dan keterangannya, maka itu telah menyelesaikan ihwal jaminan kehalalan tadi. Tiadanya gharar adalah jaminan bagi kesahihan transaksinya.
Dengan kata lain, jika Anda berkomitmen tinggi pada kejujuran yang hakiki kepada pembeli online Anda, lalu tak ada gharar sama sekali di dalamnya, lantas apa lagi yang jadi soalnya untuk terus diharamkan?
Sebagai tambahan, mari ingat selalu bahwa prinsip jual-beli dalam Islam, dalam dalil al-Qur’an, adalah ‘an taradhin, saling rela, alias happy to happy. Tentu, ‘an taradhin ini terbatas pada barang-barang yang tidak diharamkan zatnya, misal jual-beli babi.
Jika barang yang Anda jual halal, misal sarung batik Lar Gurda, lalu postingan Anda dan speknya sesuai dengan barang yang kelak diterima oleh pembeli, ‘an taradhin telah terjadi. Pembeli rela, penjual rela. Saling suka, saling happy. Lantas apa lagi soalnya?
Jika masih saja ihwal teknis yang Anda persoalkan, maka mengertilah bahwa kita ini sebagai manusia yang hidup dalam lingkaran pergaulan dan keilmuan dan peradaban yang terus bergerak pesat, mau tak mau, akan tetap berada di dalam laju kapal besarnya. Kita tak mungkin terus tinggal di dalam gua teknis traksaksi abad 10 Masehi tatkala dunia riil kita kini ialah teknis abad 21 M. Bukankah kita tak mungkin naik onta ke Arab Saudi untuk berhaji tatkala telah tersedia transportasi yang lebih cepat, aman, nyaman, dan praktis?
Saya kira keterbelengguan kita kepada khazanah teknis begituan hanya akan membuat kita kehilangan banyak potensi kemajuan ilmu, ekonomi, dan akses kita sendiri. Ya, kemajuan umat Islam sendiri. Dan ini sikap yang tak produktif bagi kita sendiri untuk terus hela, atas nama apa pun, termasuk jargon-jargon salafus shalih. Sekali lagi, pada aspek-aspek teknis itu.
Praktik syariat Islam pada dasarnya adalah keberdinamikaan itu sendiri. Bukan kejumudan. Kekakuan. Apalagi keterbelakangan.
Kita menyaksikan bagaimana hukum-hukum Islam terus bergerak dinamis merespons dinamika zamannya masing-masing. Apa yang kita kenal sebagai Mazhab Syafii, misal, pada kenyataannya hari ini lebih tepat disebut “Syafiiyah”, yakni pandangan-pandangan hukum yang terus dikembangkan oleh para penerus dan penganut mazhab Syafii sesuai dengan dinamika kehidupannya masing-masing. Bukan semata secara tekstual hanya menganut apa yang dikandung oleh kitab al-Umm, misal.
Tidak berarti Imam Nawawi sebagai salah satu ulama penerus mazhab Syafii tidak lagi menjadi Syafiiyah tatkala beliau merumuskan konsep hukum Islam yang tak sama persis teknisnya dengan kandungan al-Umm. Tidak begitu. Al-Umm tetaplah landasan prinsipilnya, fondasinya, asasiahnya, ihwal pengembangan teknisnya tentu mesti berdinamika tanpa henti. Begitupun fatwa-fatwa kekinian yang dikeluarkan oleh para ulama Al-Azhar hari ini yang notabene Syafiiyah.
Prinsip serupa juga terjadi pada mazhab-mazhab lainnya.
Dimensi batiniah teks syariat inilah yang akan mengatasi segala keterbatasan teknis di hadapan zamannya. Ini satu sisi. Pada sisi lain, ia akan menjenterahkan sistem hukum Islam dinamis yang bernapaskan keadilan, yakni pada tempatnya, dan kearifan (hikmah) berdasar hakikat ajaran syariatNya atau maqashidus syari’ah. Dengan prinsip demikian, hukum Islam perihal apa pun akan selalu menjadi nyambung, kontekstual, dengan realitas kehidupan umat Islam sendiri.
Dulu, sistem pemerintahan monarki diterima luas, dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Hari ini, kita hidup di era nation-state, bukan khilafah sedunia. Sistem yang kita anut di negeri ini ialah Demokrasi Pancasila.
Sistem ini adalah teknis operasionalnya yang dirasa tertepat hari ini. Sistem monarki ala khilafah pun tak lagi dipandang cocok kini.
Lantas, apakah kita akan terus berkelahi antarkita sendiri atas nama sistem teknis pemerintahan itu dengan ideal-ideal dan argumen-argumen yang tentu saja takkan pernah ada ujungnya?
Andai kita senantiasa melibatkan dimensi batiniah suatu dalil syariat, maka dalil-dalil itu akan justru memondasikan bangunan hukum yang kita anut sesuai dengan khazanah kita kini sehingga hidup kita bercahaya dalam naungan syariat itu. Sebaliknya, jika kita terus bersikukuh dengan bunyi tekstual dalil syariat, alias lahiriahnya belaka, sudah pasti dalam banyak hal kita akan ketinggalan kereta peradaban dunia dan sekaligus akan menjebak kita pada kerawanan berdebat tanpa ujung antarkita sendiri. Kita bukannya mendapatkan “api Islam”, kata Bung Karno, tapi hanya feses-fesesnya, abu-abunya.
Syariat Allah saya kira diturunkan kepada kita, hingga akhir zaman, untuk kemaslahatan kita sendiri, bukan kepentingan Allah. Allah tak butuh syariat. Karena kita obyeknya, khitbahnya, sekaligus lalu menjadi subyek penafsir dan pelaksananya, seyogianya tujuan kemaslahatan itulah yang terus kita kedepankan. Begitu ruhnya.
Saya kira Islam malah akan makin kehilangan makna filosofis rahmatan lil ‘alamin-nya, itu salah satu mukjizat al-Qur’an dan itu berarti kesinambungan nilai-nilai muatan dalil dengan perjalanan dunia dan manusianya hingga akhir zaman, jika kita terus mengidealkan tata cara lama, sekali lagi tata cara, ke konteks hari ini, sebagaimana secara alamiah ideal-ideal syariat hari ini pun kelak akan ketinggalan bila tidak diperbarui secara dinamis.
Wallahu a’lam bish shawab.
Jogja, 17 Januari 2020