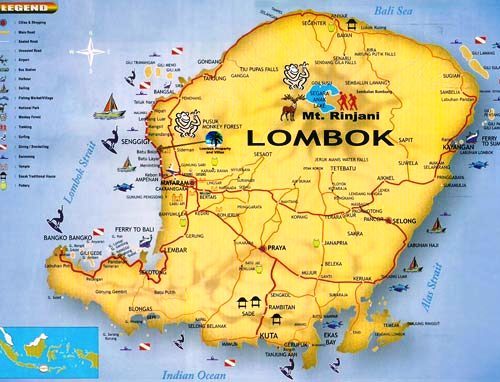Oleh: Edi AH Iyubenu Penulis adalah esais dan wakil ketua LTN PWNU DIY @edi_akhiles FB: Edi Mulyono
Carl Gustav Jung, filsuf psikoanalisis yang sejajar nama besarnya dengan Sigmund Freud, di dalam buku Diri yang Tak Ditemukan, menyatakan bahwa ada dua pola yang lazim dianut umat manusia sejak dahulu kala terkait diri dan lingkungannya. Bahasa filsafatnya adalah mikrokosmos dan makrokosmosnya.
Pola pertama ialah meletakkan diri (mikrokosmos) dalam suatu pandangan makrokosmos. Diri menjadi cermin narasi semesta yang telah terminikan. Itulah lalu yang menjadi identitas dirinya dengan penuh. Diri yang subyek tenggelam dalam tonggak besar makrokosmos. Seruan maju ke medan peperangan pada sejarah Perang Salib, misal, cocok menjadi tamsilnya. Orang-orang dengan bergairah menyambut narasi besar (makrokosmos) untuk beperang itu ke dalam dirinya.
Pola kedua ialah diri yang subyek kecil (mikrokosmos) berkorespondensi dengan narasi besar (makrokosmos) dengan rasional. Catat, berkorespondensi. Diri tak benar-benar tenggelam di dalam narasi makrokosmos. Diri tetaplah ada, suatu individu mikrokosmos yang punya otonomi, meski bisa jadi menyerap sebagian narasi besar makrokosmos. Itulah maksud korespondensi Jung.
Pola pertama menjadi tradisi umum di masa lalu, pola kedua menguat di masa kini yang rasional.
Jadi, dapat diandaikan bahwa manusia-manusia masa kini sekalipun berada di bawah bangunan suatu konsep atau bahkan hukum makrokosmos tertentu (entah negara, agama, bahkan yang lebih kecil macam keluarga), ia tetaplah wujud individu-individu yang ‘otonom’. Sengaja saya beri tanda petik di kata otonom untuk sekadar menandai bahwa irisan korespondensi antara diri yang mikro dengan tatanan yang makro bisa sangat majemuk bentuknya.
Dalam guyonannya, kira-kira begini: manusia-manusia hari ini mustahil digalang oleh suatu narasi besar (makrokosmos) untuk maju serempak ke medan perang macam zaman dulu.
Namun belakangan ini kita terperangah menyaksikan fenomena ‘menyimpang’ dari teori psikologi Jung tersebut.
Dapat dirunut dari kasus Ahok soal tafsir al-Maidah 51 yang sangat menguras energi bangsa, kita kini sangat familiar dengan istilah ‘bela Islam’ ala-ala kelompok 212 itu. Ini fakta yang sangat faktual representatif untuk kita angkat –tanpa perlu ditafsir ada tendensi apa pun di tulisan ini. Ternyata ada begitu banyak orang Islam yang rela menenggelamkan narasi diri subyektif-mikrokosmosnya dalam suatu narasi makrokosmos bernama ‘aksi bela Islam’.
Kita tersentak dan menggumam, betapa agama di era milenial ini tataplah entitas psike yang benar-benar mampu mengeduk emosi banyak umatnya!
Saya sepakat dengan ‘narasi abadi’ tersebut. Pun sebagai muslim saya pun memandang bahwa hunjaman emosi-keimanan di dalam jiwa haruslah selalu ada untuk menandai kita yang religius dengan yang asketis dan ateis.
Hanya problem faktualnya kemudian ternyata betapa kita telah menyaksikan dengan mata telanjang kecenderungan manipulatif dari lunturnya korespondensi diri yang mikro dengan narasi agama yang makro itu. Ini faktanya. Semoga Anda tak keburu jengah di sini.
Apa yang saya maksud ‘manipulatif’ ialah menyelubungnya praktik-praktik ideologisasi dan politisasi Islam sampai ke taraf yang partisan-pragmatis yang mengenaskan. Tragisnya, sebagian kita masih saja gagal memahami praktik manipulatif yang merugikan entitas umat Islam sendiri.
Pertanyaannya kini, mengapa tipikal manusia rasional macam era kita ini masih bisa gagal membangun korespondensi rasional dan patut (tepat-guna) antara subyek diri yang otonom (ya bebas, merdeka, dan punya hak penuh) dengan narasi-narasi ideologis-politis tendensius yang mengatasnamakan marwah Islam? Ada apa dengan akal sehat kita dan pola apakah yang sebenarnya tengah menjenterah dalam relasi agama yang besar dengan diri yang kecil?
****
Ya, ada apa dengan akal sehat kita untuk sekadar memahami dengan mudah bahwa kita yang hidup di antara kemajemukan bangsa ini sangat membutuhkan korepondensi rasional demi merawat harmoni sosial? Atau, dalam ungkapan khas Nahdliyyin, mengapa kita cenderung rela mengoyak ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basyariyah hanya karena perbedaan pandangan dan pilihan politik praktis?
Nampaknya, meski barangkali menyinggung, hal paling awal yang mesti dinyatakan terbuka di sini ialah kenyataan pola pikir kita yang cenderung kembali ke masa lalu dengan melahapnya bulat-bulat. Kita terbius sedemikian mitologisnya untuk kembali kepada tiga generasi pertama umat Islam yang oleh Rasulullah Saw disebut sebagai generasi terbaik (salafus shalih). Ya era sahabat, era tabi’in, dan era tabi’it tabi’in. Parahnya, iktikat ini dalam epistemologisnya begitu rancu dan dalam praktiknya berubah politis-ideologis.
Pertanyaan kritisnya di sini yang mestinya selalu kita jadikan pegangan pokok dalam gerakan merujuk masa lalu (baca: salafus shalih) itu ialah apanya? Spiritnya atau teknisnya?
Kita mengerti konsekuensi yang akan timbul langsung dari dua pilihan ini. Jika kita memilih merujuk spiritnya, sudah pasti kita akan menghidupi nilai-nilainya. Soal bentuk-bentuknya bisa sesuai dan selaras dengan rumusan kekinian.
Jika pilihannya ialah teknis-teknisnya, dapat dibayangkan betapa kita sontak menjadi ahistoris. Maksud ahistoris di sini ialah –dalam ungkapan AS Laksana di salah satu esainya untuk konteks yang berbeda—“kita hidup berjalan ke depan tetapi dengan terus-menerus menolehkan wajah ke belakang”.
Bayangkan!
Dengan cara berjalan demikian kita rawan betul menabrak-nabrak apa-apa yang ada di depan, alias realitas kehidupan kita sendiri, seperti kemajemukan bangsa ini.
Dan rupanya pilihan kedua inilah yang menjadi kecenderungan utama pilihan kebanyakan muslim masa kini. Sontak terpanggungkanlah narasi-narasi besar berjejuluk sunnah. Sunnah-sunnah yang dilekatkan kepada sosok Rasulullah Saw –tentu lengkap dengan tashih dalil-dalil naqlinya—begitu digdaya menyeret hal-hal teknis yang secara rasional acap tak nyambung dengan realitas hidup kita kini karena situasinya memang telah sangat jauh berubah dan berbeda.
Itulah hidup yang ahistoris.
Jenggot, misal. Kita begitu tersugesti untuk memanjangkan jenggot, tidak boleh memotongnya karena itu meniru orang-orang kafir (tasyabuh) dan hukumnya haram, sampai perawakan sebagian kita menjadi terlihat ganjil dan asing. Untuk mempertegas posisi identitasnya yang nyunnah, sikap-sikap kritis pada pemujaan jenggot ini direspons dengan tudingan-tudingan yang dinyatakan tidak mencintai Rasul Saw.
Sebut lagi soal celana. Kita begitu ribet dengan hukum celana yang melampaui mata kaki. Yang melampaui mata kaki dituding tasyabuh dengan kaum kafir, hukumnya haram. Yang sesuai sunnah Nabi Saw ialah yang di atas mata kaki, yang tak tasyabuh dengan orang kafir.
Ada pula soal dzikir berjamaah yang jahr (terang) yang dituding sebagai tidak sesuai tuntunan Rasul Saw. Dinyatakan bahwa para sahabat Nabi tidak berzdikir dengan mengeluarkan suara. Ditambahkan bahwa di al-Qur’an pun ada ayatnya. Saya heran: betapa jemawanya kita yang mbuh-mbuhan ini berani menyetarakan diri dengan dzikiran para sahabat yang bahasa ibunya saja adalah bahasa Arab dan pula jika suatu masjid tak pernah mengumandangkan dzikiran terang usai shalat, lantas anak-anak kita akan tahu dzikir-dzikir itu dari mana?
Lalu ada lagi yang ramai disebut sebagai ciri-ciri masjid yang mesti begini dan tidak begitu. Belum lagi soal bentuk jilbab yang mesti sepanjang ini dan tidak itu.
Saya tidak pernah berada di posisi anti terhadap segala bentuk meniru Rasulullah Saw sampai ke sandang-sandangannya. Tidak. Saya pun berjenggot. Saya pun bukannya muslim yang anti Arab style. Tidak. Saya punya banyak jubah Arab di rumah. Kerap saya pakai ke masjid dan pengajian. Tetapi, tekanan saya pada contoh-contoh di atas ialah janganlah kita terjebak pada kesunnahan teknis yang artifial, labelistik, sandang-sandangan begitu, sebab semua itu sangat tidak substantif dan karenanya menjadi majemuk saja terapannya. Mestinya sunnah-sunnah Rasul Saw yang substantiflah yang kita ikuti, rawat, dan kembangkan dalam laku keseharian kita, seperti keadaban, kerendahan hati, empati, simpati, penyabar, dan mudah menitikkan air mata.
Yang justru terjadi kini ialah betapa pada tataran yang riuh dan gahar begini atas nama mengikuti sunnah Rasul Saw, segala pertanyaan kritis tentang sosok nyata kita sebagai manusia Indonesia yang berbeda secara genetis dengan Rasulullah Saw dan para sahabatnya dan para tabi’in dan para tabi’it tabi’in tidak mendapatkan tempat yang logis untuk dikaji. Padahal itu adalah soal yang sangat alamiah yang menjadikan kita secara given (kodrati) berbeda dengan para salafus shalih. Bukankah malang sekali jadinya nasib muslim yang secara genetis tak memiliki jenggot jika perkara jenggot kita besar-besarkan dengan mutlak sebagai ciri pengikut Rasul Saw?
Begitu pula dengan betapa berbeda jauhnya khazanah kultur bangsa kita dengan kultur Arab Saudi (representasi hidup Rasul Saw di Mekkah dan Madinah), yang mestinya logis belaka menisbatkan perspektif khusus yang tak perlu sepenuh-penuhnya dipaksa sama. Ini malah diabaikan begitu rupa padahal ini adalah aspek dasein yang sangat besar dan mendasar dalam kehidupan tiap manusia.
Lagi-lagi, respons yang sering sekali kita dapatkan atas kajian-kajian kritis tentang praktik mengikuti tuntunan Rasul Saw dan salafus shalih di masa kini dalam konteks khusus kultural kita ialah penolakan-penolakan mutlak dengan klaim-klaim sesat. “Islam haruslah sama persis dengan Islamnya Rasulullah Saw, bukan selainnya dengan alasan apa pun.”
Walhasil, kita yang milenial dipaksa hidup dengan terus melangkah ke depan sembari terus pula menoleh ke belakang. Dan, sekali lagi, apa yang kita tolehi ke belakang bukanlah spiritnya, substansinya, melainkan sekadar labe-label dan teknis-teknisnya yang jelas terbatas zaman.
Dalam ungkapan Jung di atas, fakta ini mencerminkan gagalnya psike kita dalam membangun korespondensi yang rasional antara diri (mikrokosmos) yang milenial dengan khazanah salafus shalih (makrokosmos) yang kita warisi. Kita sebagai individu-individu yang otonom dalam konteks kita yang khas menjadi tenggelam dalam makrokosmos yang kita pancangkan dengan harga teknis dan mati.
Sebab perkara-perkara macam inilah dalam banyak aspek kehidupan riil kita hari ini umat Islam menjadi serba ketinggalan, terbelakang, dan bak anak bawang. Di hadapan percaturan hidup global ini, umat Islam (maaf kata) tak ubahnya sekadar kucing yang selalu merasa dirinya singa. Bangsa lain telah mumpuni bikin teknologi komunikasi yang menakjubkan, kita masih ruwet saja dengan teksnis-teknis hidup yang naturally dinamis.
Ini jelas akibat kita terbius korespondensi mikrokosmos-makrokosmos yang ahistoris, akibat kita gagap (gagal) berkorespondensi secara rasional dan progresif.
Semoga bermanfaat.
Kafe Basabasi, Jogja, 30 Mei 2018