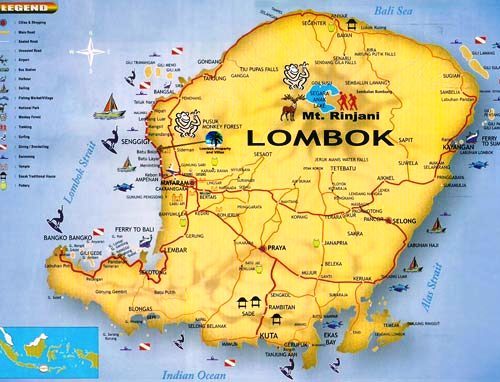Pendirian Nahdlatul Ulama
Pendirian Nahdlatul Ulama
Didirikannya Nahdlatul Ulama memang tidak terlepas dari faktor perjuangan kemerdekaan melawan penjajah. Akan tetapi sebenarnya antara faktor terpenting pendiriannya adalah keresahan para ulama pesantre melihat organisasi-organisasi Islam lokal yang lebih dulu didirikan –seperti Syarekat Islam dan Muhammadiyah-, tidak mencerminkan pemahaman keagamaan sebenar masyarakat Nusantara. Sedang secara Internasional, para ulama prihatin melihat perilaku al-Su’ud, Raja Saudi berpaham Wahabi, yang bertindak brutal dan serampangan terhadap peninggalan-peninggalan peradaban Islam di Makkah dan Madinah.
Para Ulama yang disponsori oleh KH. Abdul Wahab Hasbullah, pada 31 Januari 1926 kemudian berkumpul di Surabaya dan sepakat mendirikan organisasi bernama “Kebangkitan Ulama” atau “Nahdlatul Ulama”. Semangat utama pendirinya dengan demikian adalah melestarikan pemahaman ASWAJA dengan menggunakan cara pendekatan dakwah inovatif dan toleran ala Wali Songo.
Nahdlatul Ulama= ASWAJA + Walisongo
Cara berdakwah dan penyebaran agama ala Walisongo dijadikan panduan oleh NU, karena apa yang mereka lakukan terbukti sukses. Identitas ini oleh NU kemudian ditegaskan dengan simbol “bintang sembilan” dalam logo benderanya. Demikian pula lambang “Bumi” dalam bendera NU, juga memberi gambaran bahwa pijakan dakwaan Islam mesti membumi, berdasar kondisi masyarakatnya. Hal ini bermakna, dakwah NU mesti rahmatan lil-alamin dengan senantiasa dilakukan secara cerdas melalui pendekatan yang inovatif dan mempertimbangkan kondisi lokal Nusantara atau ke-Indonesiaan.
Identitas penting lain yang menjadi asas ditubuhkannya NU adalah pilihan untuk bermadzhab. Hal ini sangat jelas dan tegas sejak NU didirikan. Peraturan dasar (al-qanun al-asasi) pertama yang dibuat oleh Hadratus Syaikh KH. Muhammad Hasyim Asy’ari rahimullah, menyebut bahwa pahaman NU adalah bersadar madzhab empat. Pilihan ini kemudian dikukuhkan dalam keputusan pertama Muktamar NU yang pertama di Surabaya pada 13 Rabiul Tsani 1345 H bertepatan tanggal 21 Oktober 1926 M.[1]
Pilihan untuk bermadzhab bermakna, NU justru menginginkan terjaganya kemurnian agama Islam sebagaimana diamalkan oleh Rasul dan para sahabat dan kemudian dirumuskan oleh para ulama mujtahidin. Dengan bermadzhab, kemurnian agama ini terjamin berdasar sanad. Dengan bermadzhab pula, pola pengambilan hukum dapat dilakukan secara selamat dan teratur, karena ia mesti sesuai dengan prosedur dasar-dasar (usul) dan kaidah-kaidah (qawaid) agama serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiyyah. Pilihan untuk bermadzhab juga karena ia menjadi madzhab-madzab yang dianut dan diamalkan oleh mayoritas masyarakat dunia Islam.
Secara lebih rinci, NU kemudian membuat rumusan madzhab ASWAJA. Rumusannya adalah:
- Dalam Aqidah, berpandangan sesuai dengan dasar-dasar yang telah dirumuskan oleh
- Imam Abu Hasan Ali Ibn Isma’il al-Ash’ari (wafat 324 H)
- Imam Abu Mansur Muhammad Ibn Muhammad al-Maturidi (w. 333).
Antara prinsip keduanya adalah prinsip “jalan tengah”, yang bermaksud menjadikan teks agama (nash al-Qur’an dan al-Sunnah) sebagai pedoman utama. Sekaligus memberikan kesempatan kepada akal sebagai pembuka jalannya. Nash didahulukan daripada akal. Nash berfungsi menunjukkan dan akal menjelaskan. Hal ini bermakna adanya keseimbangan peran antara dalil naql dan aql. Akal dianggap penting sebab ia menjadi agen utama penalaran. Inilah differentia utama manusia, yang membedakannya dengan hewan jin, malaikat dan makhluk-makhluk Allah lainnya.
- Dalam hukum Fiqh, mengikuti jalan pendekatan (madzhab) yang telah diasaskan oleh:
- Imam Abu Hanifah Nu’man ibn Tsabit (w. 150)
- Imam Malik ibn Anas ibn Malik (w. 179)
- Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi’I (w. 204)
- Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal (w. 241)
Keempat mereka sepakat bahwa antara dalil yang dijadikan pedoman hukum adalah al-Qur’an, al-Sunnah, Ijma’ Ulama dan Qiyas. Pilihan NU kepada keempat madzhab fiqh, juga didasarkan pada bahwa dari sekian mujtahid yang layak untuk diikuti, hanya empat daripada mereka yang catatan dan prinsip-prinsip madzhabnya masih lengkap. Pilihan ini juga didasarkan fakta, bahwa madzhab-madzhab ini masih “hidup” dan diamalkan oleh mayoritas masyarakat muslim di dunia. Madzhab Maliki menjadi madzhab yang dominan di Afrika, seperti Sudan, Chad, Tunis, dan Maroko. Madzhab Hanafi menjadi pedoman masyarakat Afrika bagian utara, seperti Maroko, Aljazair, Tunis, Libya, Iran, India, Pakistan, Turki dan negara-negara Eropa Timur. Madzhab Ahmad dianut oleh sebagian besar masyarakat di negara-negara Timur Tengah. dan madzhab Syafi’I dianut oleh mayoritas masyarakat muslim Irak, Yaman, Syiria, Mesir, Somali dan sekitarnya serta Asia Tenggara.
- Dalam bidang akhlak-tasawuf, mengikuti model penghayatan keagamaan yang dilakukan, antara lain oleh:
- Imam Abu al-Qaasim al-Junayd ibn Muhammad (w. 298)
- Imam Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali (w.505)
Pandangan tasawuf mereka yang terpenting adalah tidak adalah tidak ada pertentangan antara syariat dan hakikat. Keduanya mesti seimbang dan berjalan beriringan. Hal ini berarti, penghayatan keagamaan (riyadhah dan mujahadah) tidak boleh dilakukan dengan meninggalkan pengamalan ritual keagamaan (ibadah)
Paham ASWAJA dalam konsep NU dengan demikian mencakup 3 hal, yaitu akidah, syariah dan akhlak. Terlihat bahwa ketiganya memiliki kemiripan dalam hal pendekatan “jalan tengah”. dalam perkara akidah, diakui peran akal meskipun kedudukan dalil naql lebih diutamakan. Dalam hal syari’ah, peran akal juga diakui, antara lain menjadikan qiyas sebagai salah satu dasar hukum. Demikian pula dalam masalah akhlak-tasawuf, ada sisi keseimbangan antara yang zhahir dan yang batin.
Rumusan-rumusan tersebut, ditambah dengan cara pendekatan dakwah ala Walisongo, kemudian menjadi identitas Nahdlatul Ulama. Pendekatan gaya Walisongo ini barangkali boleh dikatakan sebagai rumusan “jalan tengah” NU khususnya dalam bidang kebudayaan. Intipati dari pendekatan ini adalah menjaga nilai lama yang baik dan mengambil nilai baru yang lebih baik.
(المحافظة على القديم الصالح والأخد بالجديد الأصلح)
Karakter ASWAJA
Pendekatan ”jalan tengah” sebagaimana paparan di atas inilah yang kemudian melahirkan prinsip-prinsip tawassuth (moderat), tawazun (seimbang) dan tasamuh (toleran) dan I’tidal (proporsional) dalam berbagai aspek kehidupan. Berdasar prinsip-prinsip ini, NU tidak memiliki kamus ekstrim (tatharruf) dalam sejarah perjalanannya. NU juga tidak mudah mengkafrikan ahlul qiblat dan tidak gampang menuduh sesat orang-orang yang masih menjalankan shalat. NU tidak mengharuskan Islam sebagai dasar negara, tetapi terus dan selalu mengusahakan agar syari’at Islam bisa diakomodir dalam perundang-undangan.
Bahan Bacaan
- Abu Hasan al-Asy’ari, Maqalat al-Islamiyyin wa Ikhtilaf al-Musallin
- Aceng Abdul Aziz Dy. dkk. Islam Ahlussunnah Waljamaah di Indonesia Sejarah Pemikiran dan Dinamika Nahdlatul Ulama, Pustaka Ma’arif NU, Jakarta, Cet. II Maret 2007
- Abdul Muchith Muzadi, NU Dalam Perspektif sejarah dan ajaran (Refleksi 65 th Ikut NU), Khalista, Surabaya, Cet. III, Juli 2006.
- A. Aziz Masyhuri, Ahkam al-Fuqaha Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama Kesatu (1926) s/d Kedua puluh Sembilan (1994), PP. RMI Jakarta, 1997
- Muhammad ibn Isa al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi.
- Sekretariat Jenderal PBNU, Hasil-hasil Muktamar XXXI Nahdlatul Ulama, Jakarta, 2005.
*Disampaikan dalam Workshop ASWAJA yang diselenggarakan oleh Pimpinan Fatayat NU DIY, di Wisma Meliwis Cottage Demangan Yogyakarta, pada 17 Mei 2015 M/28 Rajab 1436 H.
[1] K.H. A. Aziz Masyhuri, Ahkam al-Fuqaha’, hlm.2-3